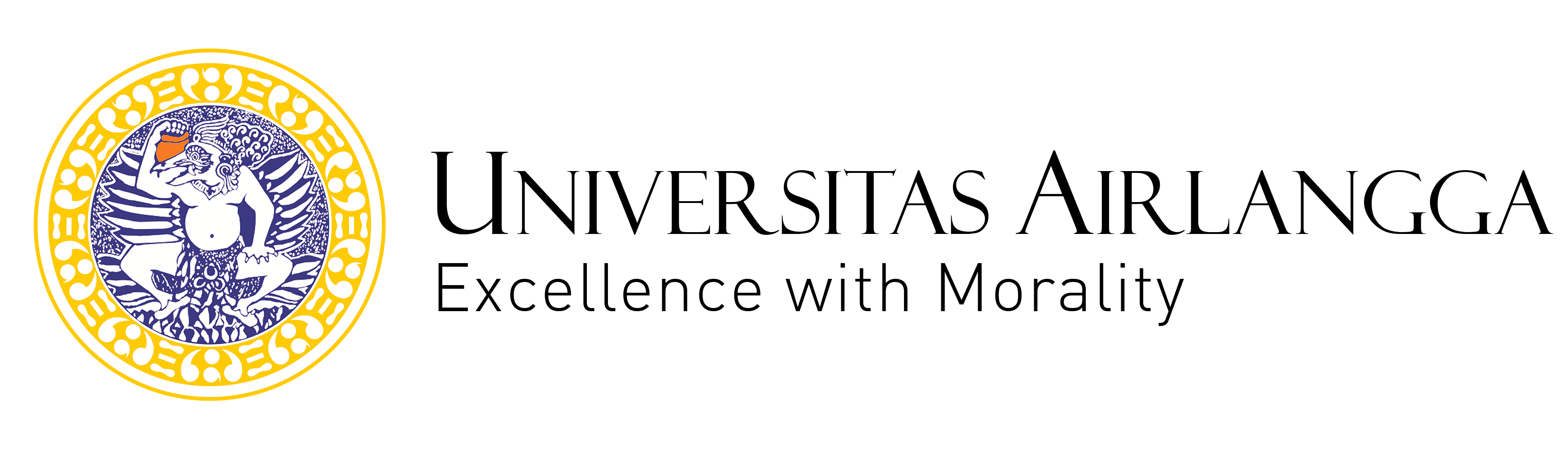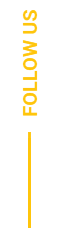UNAIR NEWS – Dekolonisasi menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah dan DPR menggodok Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Senayan. KUHP yang kini berlaku di Indonesia adalah warisan Belanda, oleh karena itu memiliki KUHP yang dibuat oleh warga Indonesia merupakan pemutusan warisan kolonial.
Mengacu pada opini Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) RI Prof. Eddy Hiariej, salah satu elan dekolonisasi terkandung dalam Pasal 2 RKUHP. Pasal tersebut mengatur bahwa seseorang dapat tetap dipidana menggunakan hukum pidana adat (living law/hukum yang hidup di masyarakat) yang ditegaskan dan dikompilasi via Peraturan Daerah. Untuk mengeksplor ketentuan ini, tim redaksi mewawancarai Pakar Hukum Adat UNAIR Joeni Arianto Kurniawan, Ph.D. yang memberikan catatan kritis terkait kerancuan konseptual Pasal 2.
Joeni menegaskan bahwa living law itu harus berbeda dengan hukum negara/hukum positif. Ia merupakan hukum yang menjadi dasar ikatan pembentukan suatu kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA). Oleh karena itu, akan sangat rancu bila hukum adat diatur secara formal layaknya dalam Pasal 2 RKUHP. Hal ini dikarenakan bahwa hukum pidana merupakan hukum negara, yang pada esensinya digunakan sebagai alat kekerasan negara pada warga negara.

“Maka dari itu, terdapat asas legalitas dalam hukum pidana dimana tak ada seorangpun yang dapat dipidana bila tidak diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Gunanya ini adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang pada warga negaranya. Hukum pidana itu harus lex certa, rumusan delik pidananya harus jelas,” paparnya pada awak media (21/8/2022).
Konsep ini tak berlaku dalam hukum adat karena ia bersifat dinamis dan berdimensi pada kesatuan kosmis, yakni kesatuan antara dunia materiil dan spiritual. Dari sini, Joeni mengatakan bahwa terlanggarnya suatu hukum adat dimaknai oleh masyarakat adat sebagai suatu peristiwa yang memicu terjadinya ketidakseimbangan kosmis, sehingga sanksi adat disini adalah untuk mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa atau pelanggaran adat selalu dilakukan melalui musyawarah adat.
“Hal ini berbeda dengan esensi sanksi pidana yakni untuk memberi nestapa atau efek jera pada pelanggar. Konsep pidana adat ini tidak dikenal dalam masyarakat adat, karena pelanggaran adat tidak berdimensi perdata-pidana,” ujar Direktur Center for Legal Pluralism Studies FH UNAIR itu.
Joeni mengatakan bahwa dipaksakannya hukum adat masuk ke dalam RKUHP akan mengingkari prinsip dekolonisasi itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa esensi kedinamisan hukum adat akan hilang karena dipositivisasi oleh negara. Ditambah pula, rancangan pemasukan pidana adat dilakukan saat KMHA masih belum diakui eksistensinya, otoritasnya, dan kedaulatan wilayah ulayatnya dalam sistem hukum Indonesia.
“Saya sempat berargumen pula bahwa pidana adat ini merupakan bentuk kolonisasi, karena negara mengkooptasi otoritas KMHA dalam memberlakukan hukum adat oleh negara. Namun ini sudah dijawab saat saya menjadi pemateri webinar GMNI bersama Wamenkumham RI Prof. Eddy. Beliau mengatakan bahwa negara tidak dimungkinkan berpartisipasi dalam menegakkan hukum adat, ia eksis hanya sebagai penghapus pidana seseorang dengan dalih bahwa ia sudah diproses secara adat,” tutur alumni Università di Pisa itu.
Meskipun demikian, Joeni mengatakan bahwa Pasal 2 RKUHP sebagai bentuk dekolonisasi masih patut dipertanyakan. Seharusnya bila berpatuh pada ideal NKRI yang demografisnya heterogen, Joeni mengatakan bahwa seharusnya negara harus bisa melakukan abstraksi dalam formulasi RKUHP.
“Jangan karena kita beragam suku dan rasnya, relativitas hukum pidana malah dilembagakan. Abstraksi disini bahwa pembuat RKUHP harus bisa menemukan nilai-nilai apa saja dalam heterogenitas masyarakat itu yang bisa diterima oleh semua orang. Nilai-nilai budaya/kepercayaan/agama yang spesifik kalau sudah masuk ke ranah publik ya harus jadi kaidah yang bisa diterima oleh semua orang, termasuk mereka yang berbeda,” tutupnya.
Penulis: Pradnya Wicaksana
Editor: Nuri Hermawan