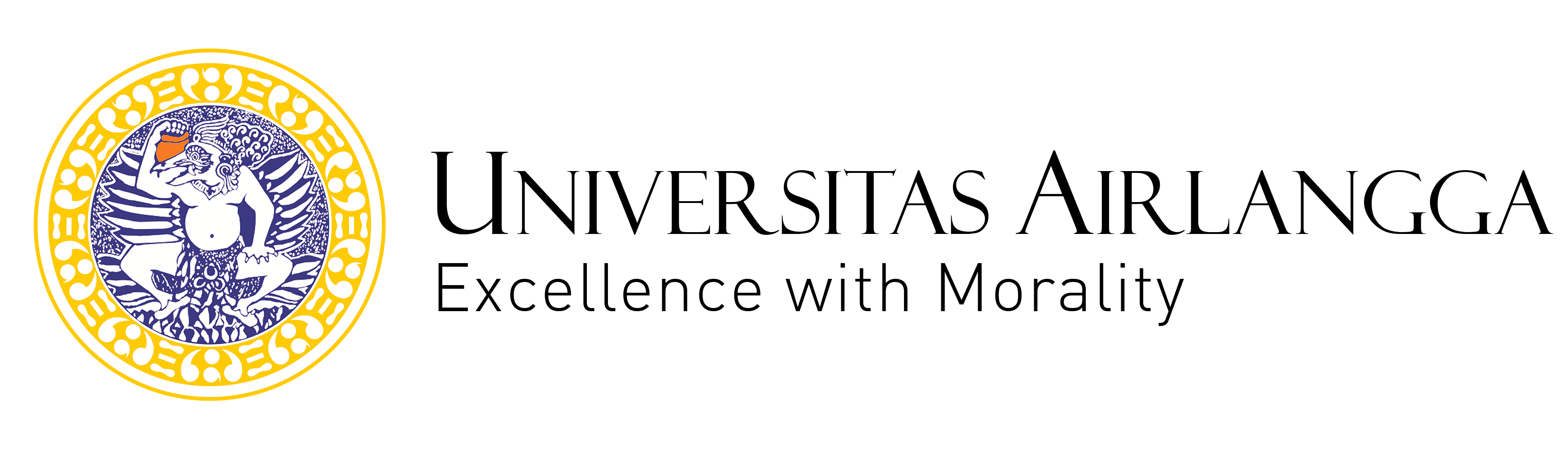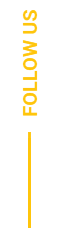Humas (5/4/2023) | Zaman telah berubah sedemikian rupa sehingga alam dan manusia terpaksa harus beradaptasi. Pada setiap perubahan itu, ada pula renungan-renungan yang dilakukan oleh umat manusia, berpikir, apakah perubahan itu membawakan sesuatu yang positif atau malah negatif. Renungan-renungan tersebut bermuara ke kata-kata disrupsi. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul adalah, Apa itu disrupsi? Sampai mana bidang hukum harus beradaptasi?
Pada seminar nasional yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang berjudul The 1st National Seminar on Digitalization in Law and Society in Indonesia “Memaknai Perubahan Hukum dan Masyarakat Indonesia terhadap Disrupsi Digital” hari Senin (3/4/2023) lalu, telah dijelaskan asal usul dari kata-kata disrupsi oleh Prof. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. Nyatanya, disrupsi di sini lahir dari dampak perkembangan tekonologi. Pemanfaatan yang dilakukan oleh berbagai sektor melahirkan dampak positif dan negatif, dan keduanya berarti sama, yakni menimbulkan perubahan. Perubahan ini menyebabkan inovasi besar-besaran, sangat besar sehingga mau tidak mau, sadar tidak sadar akan menyebabkan perombakan signifikan pada sistem yang baru. Dan itu lah yang dinamakan disrupsi.
Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Di dalam bidang hukum sendiri, disrupsi digital marak terjadi pada bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). “Perlu diketahui, HKI itu terdiri dari Hak Cipta dan juga Hak Milik Industri,” Ujar Rektor Universitas Islam Riau, Prof. Syafrinaldi pada plenary session pertama di seminar nasional itu. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia senang sekali membeli produk-produk imitasi atau “KW”. Merek-merek yang sering dibeli oleh masyarakat Indonesia adalah Supreme, Ray Ban, dan juga Vans. Hal ini bukan hanya melanggar HKI perusahaan yang memilikinya, tetapi juga menurunkan devisa negara.
Lalu mengapa disrupsi teknologi kemudian menjadi sangat berpengaruh terhadap HAKI? Hal itu dikarenakan kemudahan akses teknologi sebagai alat untuk membangkitkan ekonomi pihak-pihak tertentu dengan cara mudah. Tidak jarang, alat ini mampu melakukan plagiarisme, pengambilan data input yang ilegal, atau bahkan menghasilkan sesuatu yang bisa melanggar HAKI orang lain. Hal ini dapat memicu pembelian pada merek imitasi seperti pada contoh di atas, atau hal-hal lain yang akibatnya lebih besar dan menyeluruh.
Artificial Intelligence (AI)
Melalui plenary session kedua, Prof. Stefan Koos yang merupakan seorang profesor dari Universität der Bundeswehr München juga mengatakan bahwa AI (artificial intelligence) adalah katalisator atau “alat” yang rawan digunakan sebagai media plagiarisme. Hal ini lantaran AI bisa memasukan data input yang berasal dari sumber terbuka. Meskipun pihak pembuat AI mengatakan bahwa AI hanya bisa mengambil input dari sumber-sumber yang bisa diakses secara langsung di internet, tidak menutup kemungkinan data input tersebut memiliki lisensi.
Seperti yang kita tahu ada AI seperti “Dall-E” dan juga “ChatGPT” yang deskripsinya cocok dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Stefan Koos. Dilansir dari web OpenAI, Dall-E adalah versi parameter 12 miliar dari GPT-3 yang dilatih untuk menghasilkan gambar dari deskripsi teks menggunakan kumpulan data pasangan teks dan gambar. Hal ini membuat Dall-E mampu untuk mencomot gambar yang sesuai dengan keyword yang diberikan penggunanya untuk membuat sebuah gambar baru. Hal yang sama terjadi dengan ChatGPT, namun yang digenerasikan adalah bukan gambar, tetapi tulisan. Hal-hal seperti inilah yang menyebabkan perlu berkembangnya regulasi dan juga hukum dalam pengaturannya.
Prof. Stefan Koos juga mengatakan, “Dua tahun yang lalu kita tidak melihat AI sebagai sesuatu yang dapat diubah menjadi subjek hukum. Tapi sekarang, kita sudah menyadari bahwa AI terkadang adalah penguasa mereka sendiri, dan bukan alat. Beberapa pekerjaan mereka terkadang perlu dimintai pertanggungjawaban,”. Lalu berkaitan dengan kalimat ini, beliau juga meminta kita untuk menjadi lebih kritis dalam menyikapi hal ini. Siapa tahu, 5 atau 10 tahun lagi, kita harus merekonstruksi pemahaman kita soal “alat” dan juga miskonsepsinya sebagai subjek hukum tersendiri. Namun berkaitan dengan hal ini, pada era sekarang Prof. Stefan Koos lebih nyaman untuk memanggil AI sebagai sebuah entitas yang tidak lebih sebagai for use concept dan juga sui generis copyright dalam hal penggunaannya.
Peran Penegakan Hukum
Lalu kemudian dibutuhkan pula peran hukum di dalam disrupsi digital. Prof. Syafrenaldi mengatakan bahwa paling tidak, yang bisa kita lakukan adalah penegakan hukum. Beliau kemudian mengatakan “Amerika maju karena undang-undang patennya, dan Jepang juga kemudian maju karena undang-udang dalam hal risetnya.” Beliau juga mengingatkan audiens tentang bunyi Pasal 27 dari Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk ikut serta secara bebas dalam kehidupan budaya masyarakat, untuk berbagi kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya, dan untuk mendapatkan penghargaan atas hasil karyanya sendiri”.
Hal ini menandakan bahwa peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai instrumen hukum dalam menyikapi disrupsi digital. Tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan pasti membawa banyak entropi, yakni ketidakteraturan, keacakan, dan ketidakpastian, sehingga ditengah-tengah entropi itu harus ada satu patokan. Patokan tersebut adalah hukum. Karena dengan tegaknya hukum, akan memberikan jalan yang lebih lurus kepada perkembangan dan disrupsinya.
Penulis: Alldeira Lucky Syawalayesha