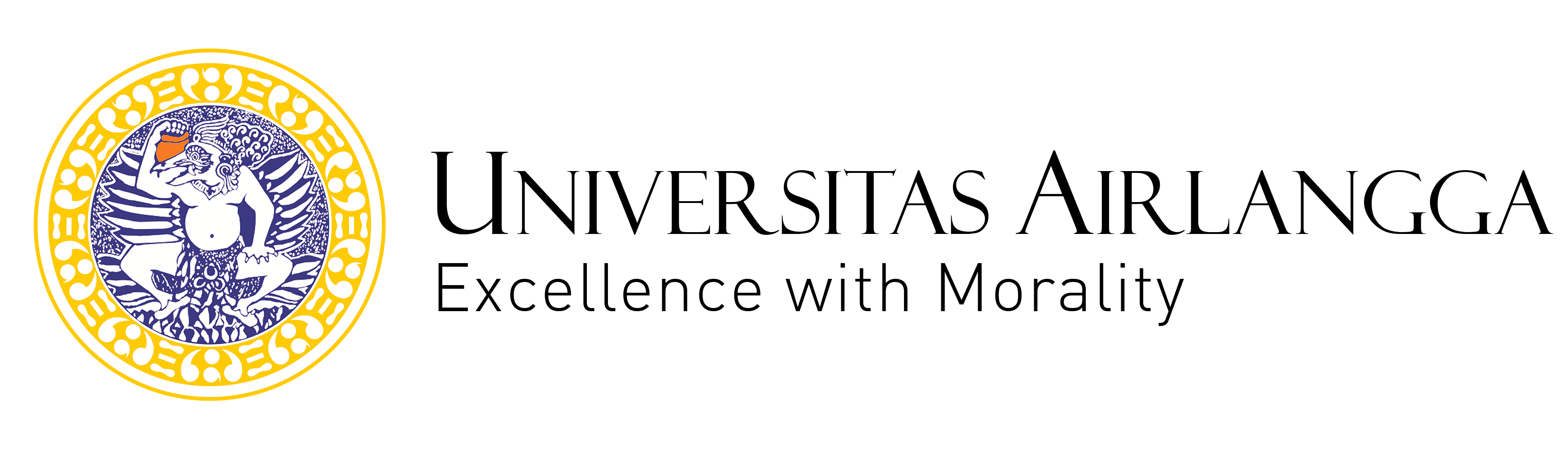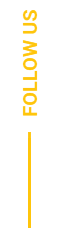Seiring dengan perjalanan waktu, jaman, dan perkembangan kemajuan ekonomi, banyak kita saksikan berbagai perubahan baik di bidang sosial, ekonomi, dan politik termasuk lifestyle atau gaya hidup suatu masyarakat. Tulisan saya ini tentang perubahan kondisi masyarakat menjalankan ibadah bulan puasa dan menghadapi hari raya Idulfitri berdasarkan perspektif pengalaman saya waktu kecil periode tahun 50-60 an dan bagaimana situasinya sekarang.
Ramadan merupakan waktu yang membahagiakan bagi kami anak-anak kampung Surabaya, suasana religiusnya begitu kental. Seperti pada umumnya keluarga santri, saya bersama mbakyu dan mas saya berpuasa. Namun karena saya anak yang paling bungsu, maka puasa saya adalah puasa bedhuk, artinya saya sudah berbuka pada waktu beduk siang atau zuhur. Tak jarang karena tidak kuat berpuasa, sebelum zuhur saya diam-diam ke kamar mandi pura-pura buang air kecil tapi minum air kran.
Yang mengasyikkan bagi kami adalah sebelum salat tarawih di musala milik keluarga besar saya di kampung Kapasari Surabaya, kami sama-sama naik tangga musala itu dimana ada beduk besar, kami bermain beduk, kami sebut bermain beduk keter. Menabuh beduk dari kulit sapi itu dengan gerakan yang rancak mengingatkan saya permainan drum tradisional dari Korea dan Jepang. Kami berlama-lama bermain menabuh beduk sampai waktunya salat isya dan tarawih.
Seperti umumnya anak-anak kecil kampung ketika salat tarawih, tidak ada yang fokus salat tapi bergurau. Misalnya menggoda teman yang sedang sujud dengan menyingkap sarungnya karena dia tidak pakai celana dalam. Atau, memperlebar rentangan kedua tangan waktu sujud agar merintangi teman sebelah yang akan sujud. Seingat saya, kami tidak dimarahi oleh orang-orang yang lebih tua. Mungkin beliau-beliau ini punya pikiran yang sama seperti pengumuman yang ada di salah satu masjid di Kairo Mesir yang berbunyi antara lain agar orang-orang tua tidak memarahi anak-anak kecil yang berlarian dan berteriak-teriak di Masjid. Karena merekalah nanti menjadi generasi penerus yang mengurus dan memakmurkan masjid.
Dalam bulan puasa itu kadang saya ikut bapak-bapak dan anak-anak melakukan patrol. Bukan patrol untuk menjaga keamanan, tapi berkeliling kampung untuk membangunkan warga kalau waktunya sahur. Dengan berbekal alat dari bambu yang tengahnya dilubangi atau panci yang ditabuh berkali-kali sambil teriak-teriak “Sahur-Sahur!!!”.
Dua-tiga hari menjelang lebaran, saya selalu ikut menunggu dan melihat ibu saya menjahit pakain baru untuk kami dan membuat kue yang dimasukkan oven terbuat dari seng tipis dan diletakkan di atas tungku, kami menyebutnya angglo, yang membara dengan arang sebagai bahan bakarnya. Jangan dibayangkan seperti sekarang dimana ibu-ibu tidak membuat sendiri kue-kue itu, tapi beli yang sudah jadi di mall atau order di penjualan online.
Membuat kue sendiri seperti yang dilakukan ibu saya, kita bisa merasakan kesakralan Ramadan dan menjelang lebaran. Selain itu bagi warga Surabaya yang mempunyai uang tentu belanja persiapan lebaran untuk anak-anaknya misalnya membelikan sepatu di Jalan Tembaan (sebelum Blauran) atau membeli baju di Pasar Atom.
Biasanya sehari-dua hari menjelang lebaran warga nyumet atau menyalakan petasan, baik yang dinyalakan di halaman rumah dan meledak atau menyalakan mercon sreng, yaitu petasan yang melesat ke atas setelah dinyalakan seperti peluru kendali. Kita bisa melihat tetangga kita itu kaya atau tidak dari ketebalan sisa-sisa petasan di halamannya. Bagi warga yang kurang mampu yang tidak bisa membeli petasan, tetap bisa menikmati kebahagiaan yang sama yaitu dengan membuat mercon bumbung, petasan terbuat dari bambu yang agak panjang dan dilubangi kemudian dimasukkan karbit, disulut api, dan mengeluarkan suara ledakan seperti meriam artileri.
Di hari lebaran, warga kampung kami menuju Lapangan Tambaksari untuk salat Idulfitri. Setelah salat kami melakukan unjung-unjung atau pergi ke tetangga-tetangga atau famili di kampung lain untuk saling memaafkan. Anak-anak sebaya kami juga melakukan kegiatan itu sendiri, bukan untuk minta maaf atau mengucapkan selamat lebaran, tapi menunggu diberi uang oleh pemilik rumah atau mengambil kacang goreng di toples tanpa sepengetahuan pemilik rumah. Unjung-unjung ini adalah budaya kearifan lokal yang dilakukan selama satu minggu atau lebih. Kegiatan budaya ini juga menimbulkan perasaan religi dan tradisi yang dalam, sehingga kesakralan lebaran begitu terasa.
Sayang sekarang di dunia modern dengan IT yang canggih ini, budaya unjung-unjung itu sudah hilang diganti dengan silaturahim singkat lewat dunia maya, lewat WhatsApp, Instagram, Twitter, dan Facebook sambil mengucapkan selamat lebaran dan mohon maaf lahir batin. Dengan cara ini sepertinya kita sudah bersilaturahmi, padahal itu maya atau virtual.
Selain dengan media sosial, kita sekarang melakukan unjung-unjung singkat yaitu halalbihalal di suatu gedung atau restoran, dan tidak pernah menginjakkan kaki di rumah saudara atau sahabat. Apalagi baru-baru ini ada peraturan pemerintah yang melarang adanya makanan dan minuman pada acara halalbihalal mengingat situasi pandemi, maka suasana lebaran seperti masa lalu tidak akan terjadi.
Karena itu wajar, kita sekarang tidak melihat kesakralan lebaran itu, karena sehari setelah lebaran, jalan-jalan sudah macet lagi dan banyak orang sudah masuk kantor. Yang dirasakan oleh warga tentang lebaran dewasa ini hanyalah hiruk pikuk mudik yang kemacetannya di siarkan TV berhari-hari.