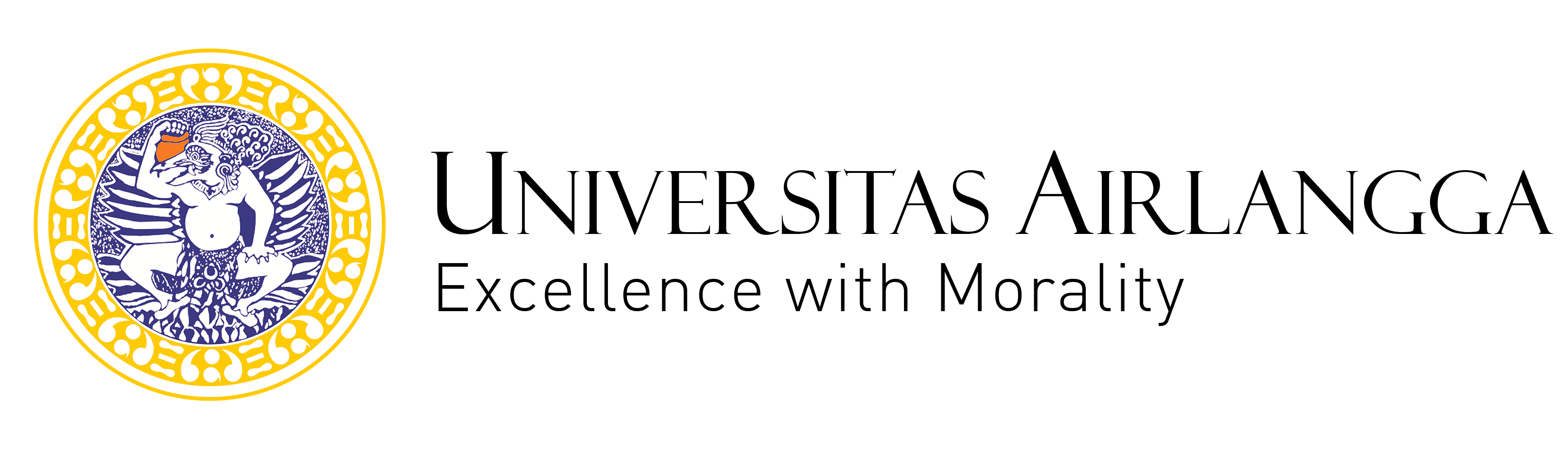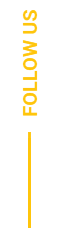Di Indonesia, perusahaan perantara digital (digital intermediaries) nasional telah berkembang pesat, dimana hal ini diikuti dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja digital yang signifikan pula. Maraknya perusahaan perantara digital nasional yang memanfaatkan tenaga kerja digital cenderung ditanggapi secara positif oleh negara sebagai solusi atas pengangguran di negara ini. Harus diakui bahwa bahwa perusahaan perantara digital nasional telah menyerap banyak tenaga kerja. Namun sejatinya jauh lebih penting untuk mencermati kondisi kerja dan kesejahteraan tenaga kerja digital ini. Di Indonesia, fenomena tenaga kerja digital muncul ditengah situasi dimana Indonesia masih memiliki PR serius, yakni masalah kesejahteraan tenaga kerja tradisionalnya.
Di Indonesia, terdapat perbedaan signifikan terkait organisasi buruh trandidional dan buruh digital. Buruh tradisional sebagian besar telah terorganisir dalam serikat pekerja, dimana mereka setiap tahun turun ke jalan melakukan aksi May Day. Secara berbeda, hingga publikasi ilmiah ini ditulis, buruh digital di Indonesia cenderung memiliki tingkat kesadaran yang rendah tentang perlunya serikat buruh. Buruh digital yang terlibat dalam penelitian ini secara literal menyatakan bahwa mereka tidak seharusnya mengikuti aksi buruh tersebut, karena mereka menganggap dirinya “bukan buruh”, bahwa mereka “berbeda dengan buruh (tradisional) itu”.
Studi ini mengambil pandangan tentang pentingnya serikat pekerja untuk advokasi tenaga kerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menghambat serikat pekerja digital di Indonesia. Adapun metodenya, data primer dikumpulkan melalui survei, serta FGD dan wawancara dengan tenaga kerja digital. Terakhir, tinjauan pustaka dimanfaatkan untuk mengumpulkan data tentang sejarah serikat buruh tradisional di Indonesia, serta perdebatan terkini mengenai hak-hak buruh digital.
Sebagai permulaan, sangat penting bagi peneliti mengklarifikasi pengertian ‘tenaga kerja tradisional’ dan ‘tenaga kerja digital’ yang dibahas dalam artikel ini. Meninjau definisi kedua konsep tersebut sangat penting karena telah terjadi perdebatan tentang apakah ‘tenaga kerja digital’ dapat dianggap sebagai bagian dari kategori tenaga kerja. Istilah ‘tenaga kerja tradisional’ yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada sekumpulan individu yang melakukan pekerjaan yang terikat atau dibatasi oleh wilayah geografis tertentu di mana para pemberi kerja dan/atau alat-alat produksi berada. Sebagaimana dikemukakan Hudson (2001), “work has traditionally been geographically bounded”. Akibatnya tenaga kerja tradisional cenderung harus mengunjungi lokasi dimana pemberi kerja dan/atau alat-alat produksi berada untuk melakukan pekerjaannya.
Dengan perkembangan teknologi internet, kita sekarang menyaksikan bagaimana karyawan, pengusaha, dan alat produksi dapat berada di tempat yang jauh berbeda di bumi (Graham, Hjorth & Lehdonvirta, 2017, hal.136). Kita sekarang mengalami era ketika informasi menjadi bahan mentah dari suatu proses produksi, dimana bekerja dengan bahan baku informasi dapat dilakukan dari jarak jauh (Graham & Anwar (2018). Di tingkat industri, muncul perusahaan perantara digital (digital intermediaries): “any entity that enables the communication of information from one party to another (Cotter, 2005, p.2). Perusahaan perantara digital biasanya mengembangkan platform yang dapat digunakan tenaga kerja digital untuk memproduksi dan/atau menyebarkan konten atau layanan. Istilah ‘digital tenaga kerja’ selanjutnya banyak digunakan untuk merujuk pada pekerja, baik berupah
maupun tidak, yang sangat bergantung pada platform tenaga kerja digital untuk berkomunikasi dengan dan melakukan pekerjaan untuk pemberi kerja atau klien mereka, seringkali dari jarak jauh.
Artikel ini mengikuti pemikiran Scholz (2013) yang memahami bahwa “digital labor as a continuation of the social relations surrounding the traditional work-place”. Selain itu, tenaga kerja digital sering disebut sebagai ‘tenaga kerja tidak tetap’ (precarious labour). Woodcock (2017) menjelaskan bahwa “The term precarity has been used to describe the conditions of insecure employment” (hal.136). Mengenai kelangkaan tenaga kerja digital, Scholz (2013) mengkritik bahwa: “These are new forms of labor but old forms of exploitation. There are no minimum wages or health insurance, and so far, federal and state regulators have not intervened” (hal.1).
Studi ini mengungkap fakta bahwa para pengemudi online dan pembuat konten di Indonesia cenderung membedakan diri mereka dari tenaga kerja tradisional. Hal ini sangat mungkin disebabkan, salah satunya oleh politik pelabelan buruh pada masa Orde Baru (1966-1998) yang melahirkan konotasi negatif label ‘buruh’: sebagai kelompok masyarakat berpendidikan rendah, pekerja kerah biru, kasar, miskin, dll. Akibatnya, banyak kelompok kelas pekerja di Indonesia (seperti guru dan jurnalis) cenderung menolak dicap sebagai ‘buruh’ (buruh). Berikutnya, praktik diskursif yang dilakukan perusahaan perantara digital di Indonesia tampaknya telah berhasil membentuk kesadaran semu (false consciousness) bahwa pengemudi online dan pembuat konten bukan ‘buruh’ (buruh), sayangnya praktik diskursif ini cenderung diamini pebuat kebijakan.
Kegagalan tenaga kerja digital untuk memahami diri mereka dalam kategori ‘buruh’ menjadi penyebab keengganan mereka menginisiasi atau bergabung dalam serikat buruh di Indonesia. Serikat buruh dan gerakan buruh dianggap identik dengan kehidupan buruh tradisional. Buruh digital cenderung menganggap diri mereka berbeda dari buruh tradisional, sehingga bergabung dengan serikat buruh dan gerakan cenderung dianggap tidak relevan.
Penulis: Titik Puji Rahayu
Link Jurnal: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003161875-36/divided-unionisation-titik-puji-rahayu