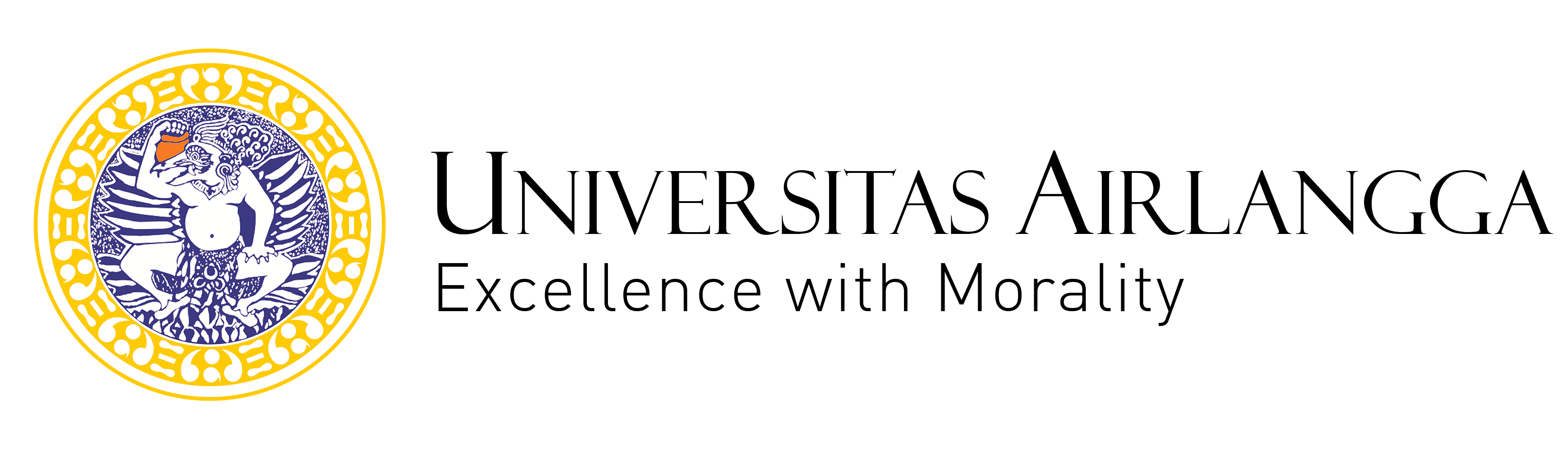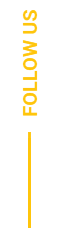Pelembagaan ajaran dan praktik demokrasi di Indonesia rupanya masih memerlukan waktu yang panjang. Tesis seperti ini berangkat dari pengamatan penulis saat berinteraksi dengan kawan-kawan muda di mana masih banyak di antara mereka yang memiliki sikap prasangka bercampur sinis terhadap demokrasi. Munculnya sikap prasangka bercampur sinis itu didasarkan pada anggapan bahwa sistem demokrasi datang dari Barat dan karenanya tidak sepenuhnya sesuai dengan kebudayaan dunia Timur, termasuk Indonesia.
Namun, tindakan mempersoalkan asal demokrasi seperti itu sungguh tak sebanding apabila melihat manfaat yang telah diberikan oleh sistem demokrasi bagi peradaban global, terlebih khusus dalam soal mendorong perdamaian dan persaudaraan antara bangsa-bangsa. Dalam konteks itu, tulisan ini hendak mengulas sejarah, makna, dan perkembangan demokrasi. Melalui itu, diharapkan bangsa ini, terlebih khusus kaum muda, akan menerima demokrasi yang didasari oleh sikap percaya terhadapnya.
Sejarah dan perluasan makna demokrasi
Demokrasi adalah sebuah ajaran dan praktik yang pada awalnya berkembang di Yunani pada abad V SM. Secara etimologis, demokrasi berasal dari dua kata mandiri dalam bahasa Yunani yakni demos yang berarti rakyat dan kratos/kratein yang berarti kekuasaan/memerintah. Jadi, secara etimologis, demokrasi adalah bentuk kekuasaan dari rakyat (Budiardjo, 2010:105). Berdasarkan pengertian etimologis ini pula, terlihat bahwa pada awal perkembangannya, istilah demokrasi hanya merujuk pada sumber kekuasaan yaitu kekuasaan dari rakyat.
Namun, konvergensi historis antara demokrasi dan wacana liberal yang terjadi pada abad XVII-XIX, dan kemajuan peradaban di abad XX, menyebabkan demokrasi mengalami perluasan makna yang kompleks. Demokrasi bukan lagi hanya merujuk pada sumber kekuasaan tetapi juga mengintegrasikan banyak konsep lain seperti perwakilan melalui parlemen (representative parliaments), pemisahan kekuasaan (separation of powers), negara berdasarkan hukum (rechtsstaat/rule of law), kebebasan sipil (civil liberties, yang di antaranya mencakup gagasan dasar tentang freedom, liberty, dan equality), kekuasaan mayoritas (majority rule), pluralisme (pluralism), kewarganegaraan (citizenship), perlindungan kaum minoritas, emansipasi kaum perempuan, hak asasasi manusia (HAM), dan multikulturalisme (Sparringa, 2021; Danujaya, 2012:144-150).
Perkembangan demokrasi
Perang Dunia Kedua dan dampak yang ditimbulkannya adalah titik balik (turning point) dalam perkembangan demokrasi. Setelah Perang Dunia Kedua, demokrasi, di samping pembangunan, menjadi moda perubahan sosial yang dijalankan oleh negara-negara di dunia. Demokrasi menjadi perhatian banyak negara di dunia. Negara-negara di dunia didorong untuk menganut demokrasi sebagai sistem pemerintahan mereka.
Tujuan penguatan dan promosi demokrasi, selain untuk memperbesar pengaruh Amerika ke seluruh dunia, juga terutama dimaksudkan untuk mengantisipasi munculnya kembali pemimpin fasis seperti Adolf Hitler dan Benito Mussolini. Antisipasi terhadap munculnya tokoh seperti Hitler dan Mussolini diyakini akan menjauhkan negara-negara di dunia dari kemungkinan untuk kembali berperang. Maka, perluasan demokrasi dimaksudkan untuk menjaga perdamaian antara negara-negara di dunia.
Dan, data menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-20 sampai sekarang kondisi dunia telah menjadi semakin damai. Pada 2012, sekitar 56 juta orang mati di seluruh dunia, 600.000 di antaranya akibat kekerasan manusia (perang membunuh 120.000 orang, dan kejahatan membunuh 500.000 lainnya). Bandingkan, 800.000 orang melakukan bunuh diri, dan 1,5 juta orang mati karena diabetes (WHO, 2012; UNDOC, 2013 dalam Harari, 2019:16).
Peningkatan kondisi damai itu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah negara demokrasi. Data tentang perkembangan demokrasi di periode 1975-2018 menunjukkan bahwa jumlah negara yang menganut sistem demokrasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun 2018, lebih dari separuh negara di dunia (62 persen, atau 97 negara) telah menjadi negara demokrasi, dibandingkan dengan kondisi pada tahun 1975 yang jumlahnya hanya 26 persen (Laporan International IDEA, 2019).
Lantas, apa yang menyebabkan demokrasi mampu manjadi landasan bagi terciptanya perdamaian? Jawaban atas pertanyaan ini dapat ditelusuri kembali pada nilai-nilai dasar yang dikukuhkan demokrasi yaitu kebebasan dan kemerdekaan manusia. Pengukuhan atas nilai-nilai dasar seperti itu mendiktekan bahwa penyelesaian masalah dalam kehidupan bersama mesti melalui mekanisme yang akan menjamin kebebasan dan kemerdekaan dari setiap orang. Mekanisme itu dalam demokrasi disebut dengan dialog. Sebaliknya, setiap upaya penyelesaian masalah dengan mekanisme yang akan merampas kebebasan dan kemerdekaan individu, seperti pemaksaan dan kekerasan, mesti dijauhkan. Jadi, demokrasi dalam ajaran dasarnyanya adalah mendiktekan nir-kekerasan.
Kontekstualisasi demokrasi
Alasan lain yang membuat kaum muda tidak perlu mempertahankan sikap prasangka bercampur sinis terhadap demokrasi adalah karena ia dapat disesuaikan dengan nilai-nilai dan budaya-budaya lokal dari suatu negara. Itulah yang dinamakan dengan kontekstualisasi demokrasi. Dalam konteks Indonesia, misalnya, pelembagaan demokrasi mesti menyertakan nilai-nilai yang terdapat dalam empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Penyertaan nilai-nilai yang tercakup dalam empat pilar kebangsaan itu akan membuat demokrasi menjadi relevan dan bermakna bagi kehidupan masyarakat Indonesia, dan karenanya menjadi lebih mudah untuk diterima.
Kepercayaan terhadap kontekstualisasi demokrasi seperti itu didasarkan pada kenyataan bahwa demokrasi yang berkembang di Amerika, Prancis, Inggris, India, Jepang, atau Korea Selatan, misalnya, masing-masing memiliki elemen unik dalam sistem demokrasi mereka. Namun, poin penting yang telah diingatkan oleh penganut paham demokrasi kontekstual perlu ditekankan di sini, bahwa penyertaan nilai-nilai dan budaya-budaya lokal dalam demokrasi tidak boleh mengurangi esensi nilai-nilai universal demokrasi seperti kebebasan, kemerdekaan, kesetaraan, persaudaraan, toleransi, dan sejenisnya.
Berdasarkan pentingnya sumbangsih demokrasi dalam meningkatkan perdamaian, maka sudah semestinya bagi kaum muda membuang sikap prasangka bercampur sinis terhadap demokrasi. Sebaliknya, kaum muda mesti ikut menjadi bagian dalam mendorong dan mempromosikan demokrasi sehingga pelembagaannya semakin matang, baik di tingkat lokal maupun global. Lebih dari itu, upaya kaum muda dalam mendorong dan mempromosikan demokrasi demi perdamaian tak lain adalah tindakan memanifestasikan salah satu tujuan bernegara yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Penulis: Ransis Raenputra, Mahasiswa Sosiologi FISIP Universitas Airlangga