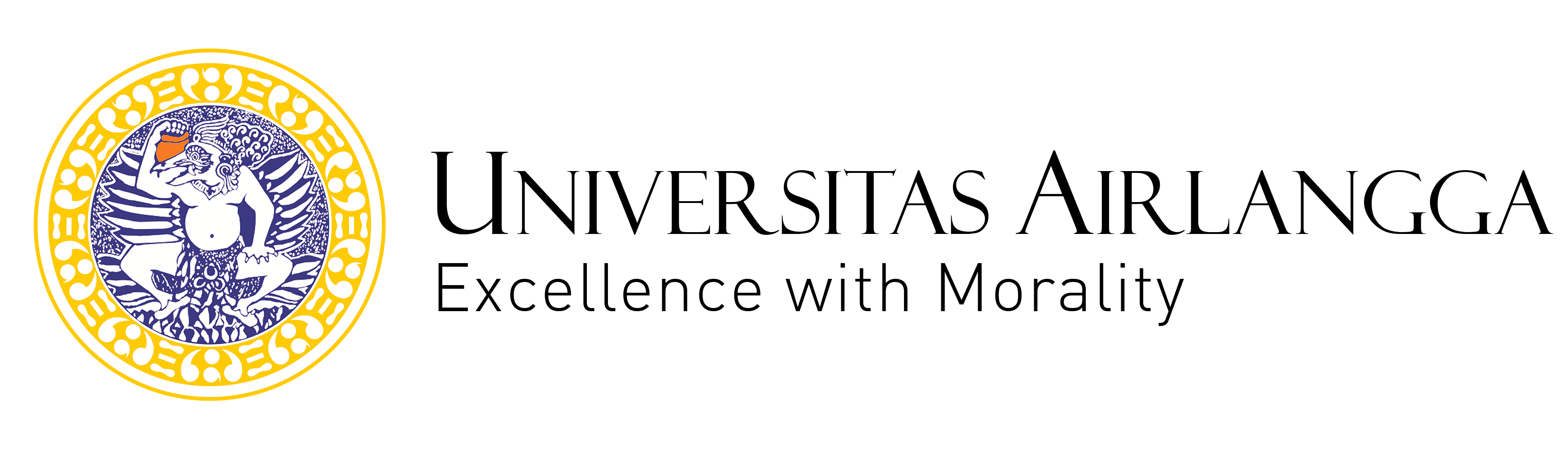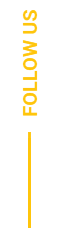Madiun adalah daerah paling barat Provinsi Jawa Timur. Saat Mataram berkuasa, luasnya hanya meliputi sebagian areal di sisi timur Gunung Lawu (Ong Hok Ham, 2018). Akan tetapi, setelah berstatus sebagai karesidenan, daerahnya semakin luas. Madiun juga dikelilingi Gunung Kelud, Gunung Lawu, Gunung Wilis, Gunung Liman, hingga Pegunungan Kendeng. Madiun merupakan daerah strategis yang kaya akan komoditas tanaman pertanian dan tanaman ekspor, seperti kayu manis, teh, indigo, kina, cengkeh, kopi, kakao, kapuk, tebu, serta hutan-hutan produksi. Keberadaan komoditas tersebut tidak lepas dari aktivitas pembudidayaan tanaman yang diberlakukan oleh Belanda pada masa Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel), tahun 1830. Akan tetapi, pembudidayaan berbagai macam komoditas penting tersebut, tidak selalu berjalan lancar. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah banjir.
Banjir di Madiun dan Penyebabnya
Banjir pertama kali terdeteksi di daerah Madiun tahun 1858. Saat itu, banjir terjadi cukup besar dengan ketinggian air mencapai 3,5 meter (Merdeka, 1963). Memasuki abad ke-20, misalnya tahun 1926, beberapa surat kabar terbitan Belanda kembali memuat berita tentang banjir, salah satunya De Telegraaf. Menurut koran ini, tanggal 6 April 1926, telah terjadi banjir di Madiun. Banjir diawali oleh hujan yang turun dengan lebat. Akibatnya air di Kali Madiun naik hingga setinggi 1 meter. Kemudian, di berbagai lokasi, seperti di Pabrik Gula Redjo Agoeng, dan tiga perkebunan tebu milik Pabrik Gula Soedhono terendam banjir dan tidak sedikit permukiman maupun rumah penduduk yang roboh atau hancur.
Sampai tahun 1939, banjir masih terus terjadi di Madiun. Oleh karena itu, pemerintah kolonial memutuskan untuk memasang pompa listrik di Jalan Lawu tahun 1940. Walaupun pemasasangan pompa telah dilakukan, banjir tidak berhenti begitu saja. Satu tahun setelah pemasangan pompa, banjir kembali melanda daerah Madiun sebanyak dua kali. Meskipun hujan tidak begitu lebat, beberapa desa serta sebagian jalanan di permukiman tergenang banjir, sehingga tidak dapat dilalui. Penduduk pun harus membersihkan rumah dan mengungsikan barang-barang berharga mereka ke lokasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, banjir kembali terjadi pada 23 Desember 1941. Akibatnya, perkampungan yang berada di dekat Kali Madiun serta lahan milik Pabrik Gula Redjo Agoeng terendam banjir.
Menurut beberapa surat kabar maupun sumber lainnya, salah satu faktor dominan penyebab terjadinya banjir di Madiun adalah curah hujan. Selain curah hujan, banjir juga disebabkan oleh anak sungai Bengawan Solo yang melintasi daerah Madiun dan sekitarnya, yakni Kali Madiun. Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa dengan luas sepanjang 600 km yang berhulu di Pegunungan Sewu hingga Laut Jawa (R. Gunawan, 2010). Meskipun keberadaan Bengawan Solo memberikan manfaat, tetapi sungai ini dapat menjadi ancaman, terutama bagi penduduk yang bermukim di daerah-daerah, seperti Solo, Sragen, Ngawi, Madiun, Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik.
Penanggulangan Banjir
Menyadari bahwa Madiun menjadi salah satu daerah yang rawan terhadap banjir, pemerintah akhirnya berupaya untuk melakukan tindakan penanggulangan. Penanggulangan banjir adalah segala tindakan yang meliputi pencegahan sebelum banjir (prevention), penanganan ketika banjir (response/intervention), dan pemulihan kondisi pasca banjir (recovery). Ketiga hal tersebut membentuk suatu siklus yang dimulai dari terjadinya banjir. Banjir kemudian dikaji oleh para ahli sebagai bahan dalam menentukan pencegahan.
Setelah itu, dilakukan tindakan pencegahan, baik secara mikro maupun makro Langkah yang terakhir ialah melakukan pemulihan sesegera mungkin supaya mempercepat perbaikan dan mengembalikan kondisi seperti sedia kala. Penanggulangan banjir, terutama dalam bentuk mitigasi bencana aktif telah dilakukan oleh Belanda di daerah Madiun sejak masa kolonial, tepatnya pada awal abad ke-20. Hal ini berlangsung setelah munculnya kebijakan politik etis. Melalui politik etis, Belanda kemudian memaksimalkan Kali Madiun sebagai DAS yang digunakan untuk irigasi serta penanggulangan banjir.
Akan tetapi, upaya penanggulangan banjir tidak berhenti begitu saja. Pada tahun 1940, Belanda kembali melakukan penanggulangan melalui program perbaikan kampung (kampong verbetering) (Husain, 2016b), perbaikan terhadap pipa pembuangan utama, serta pembangunan pipa saluran air di Kota Madiun, tepatnya di Kelurahan Sumber Umis dan Kelurahan Nambangan Lor. Mulanya, pemerintah mengurus pipa-pipa. Setelah pembangunan jaringan pipa saluran air di Sumber Umis selesai, kampung yang terletak di sepanjang jalur pipa tidak lagi mengalami masalah. Kemudian, pekarangan penduduk dan sebagian permukiman yang berada di seberang kantor telepon juga tidak dilanda banjir ketika air di Kali Madiun sedang tinggi. Hal tersebut karena Belanda telah menempatkan pompa listrik di ujung pipa-pipa Sumber Umis, sehingga air hujan dapat mengalir ke arah Kali Madiun. Usai mengurus pipa-pipa, Belanda melakukan perbaikan di dalam kampung, antara lain dengan membangun beberapa jalan dan sistem drainase.
Penulis: Nabila Amelia, Sarkawi B. Husain
Informasi detail tentang riset ini dapat dilihat dalam tulisan kami di:
http://diakronika.ppj.unp.ac.id; DOI: doi.org/10.24036 diakronika/vol22-iss2/251