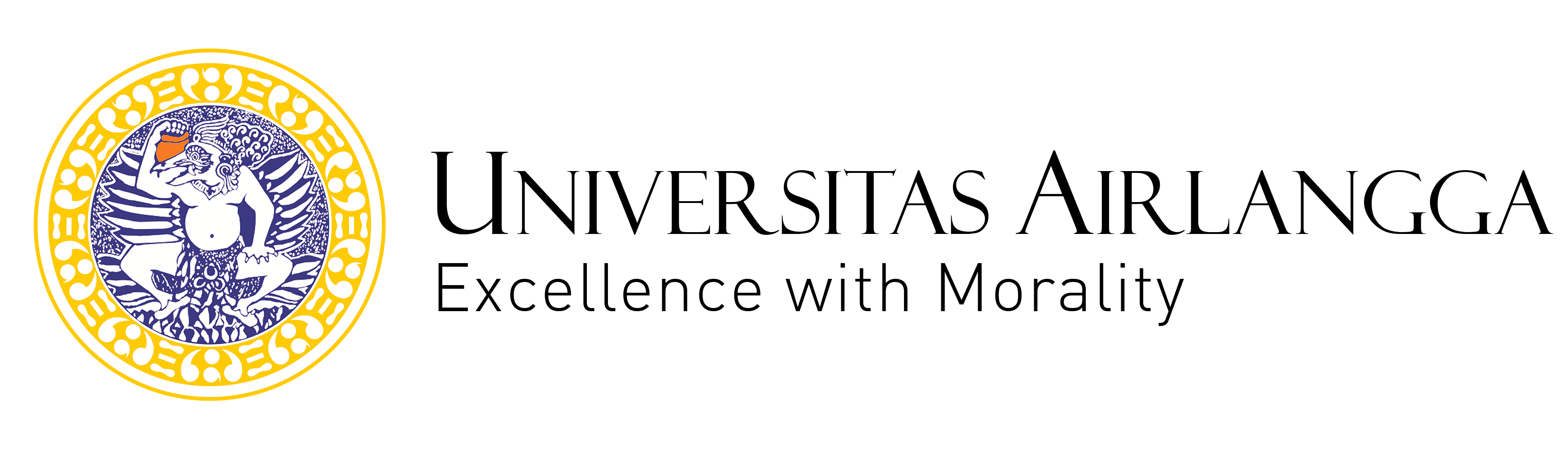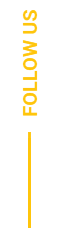Selama ini kita mengenal karya sastra setidaknya berfungsi sebagai dua hal, yakni sarana edukasi untuk pengenalan kekayaan bahasa, serta fungsi rekreasional seperti seni dan estetika. Penggunaan karya sastra sebagai sarana kritik sosial juga semakin berkembang terutama di era reformasi sebagai respon pada bentuk pemerintahan yang otoriter sehingga menjadikannya sebagai salah satu medium yang dianggap dapat mengungkapkan kritik yang terbalut keindahan bahasa.
Beragam rupa turunan dari karya sastra yang berbentuk satire, sarkasme, atau parodi (political burlesque) telah banyak digunakan sebagai sarana kritik sosial dan politik. Akan tetapi, kemampuan untuk dapat menyampaikan kritik tidaklah datang dalam sekejap, melainkan dibentuk dari pengasahan literasi politik yang tajam melalui pendidikan dan pengalaman pembelajaran baik dalam konteks formal ataupun informal.
Sekalipun karya sastra muncul sebagai wadah yang begitu populer digunakan untuk menyampaikan kritik, namun fungsi lainnya yang juga penting tapi seringkali terlupakan ialah peranannya secara khusus dalam membangun literasi politik. Fungsi ini kerap diabaikan sehingga upaya-upaya yang secara serius ditujukan untuk menggarap karya sastra khusus untuk instrumen penumbuh literasi politik.
Artinya, karya sastra tidak saja berfungsi sebagai wahana penampung ekspresi kritik, tetapi juga mampu memberikan pelajaran penting terkait tiga komponen literasi politik: (1) pengetahuan dasar politik seperti asal-usul demokrasi, sistem politik yang berlaku, dan sejarah negara-negara; (2) kemampuan untuk turut serta di dalam proses pengambilan kebijakan, merangkai argumen dan opini politik secara logis dan rasional, serta partisipasi politik lainnya; (3) pemahaman akan nilai-nilai kebaikan bersama seperti filsafat dan aliran politik, status sosial-ekonomi, keberagaman, serta penghargaan terhadap martabat dan hak asasi manusia.
Indonesia sendiri masih memiliki pekerjaan besar dalam hal membangun literasi politik warganya. Pasalnya, fakta bahwa disinformasi dan hoaks marak terjadi serta menjurus pada terbentuknya polarisasi politik menunjukkan bahwa literasi politik masyarakat masihlah lemah. Disinformasi yang bertebaran di media sosial – disebut pula sebagai propaganda terkomputasi – telah mewarnai dinamika demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, media sosial menjadi instrumen yang cukup vital dalam membantu masyarakat memperoleh informasi publik serta menghadirkan akses agar mereka dapat berpartisipasi dalam ruang-ruang publik secara digital. Namun di sisi lainnya, media sosial juga memiliki sisi gelapnya tersendiri yang justru dapat mengancam demokrasi.
Sebagai negara yang masih berada dalam fase konsolidasi demokrasi, literasi politik sangatlah penting untuk ditumbuhkembangkan. Literasi politik yang bagus berkonsekuensi pada pemahaman warga yang baik terhadap hak-hak sipilnya. Selain itu, kunci dari kuatnya demokrasi juga terletak pada kemampuan berpikir kritis dan tingginya kesadaran terhadap politik yang penuh dengan moralitas dan tanggung jawab. Memelihara kehidupan demokrasi yang baik dan berkesinambungan diperlukan upaya serentak, baik negara ataupun masyarakat sipil untuk sama-sama mengemban tanggung jawab untuk membangun dan memperkuat literasi politik.
Sayangnya, pembangunan literasi politik yang selama ini dilakukan oleh negara belumlah mencapai titik optimal. Hal ini karena pembudayaan literasi politik masih didominasi pada sekolah-sekolah formal dengan kurikulum yang juga secara rigid telah ditentukan oleh otoritas pusat melalui Kementerian Pendidikan misalnya.
Namun, model penumbuhan literasi politik seperti ini masih kurang efektif. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan misalnya, masih cenderung bermodel indoktrinasi selama masa orde lama, baru, dan reformasi. Pendidikan kewarganegaraan seperti ini cenderung bias kepentingan penguasa yang relatif justru ingin menghilangkan kesadaran dan nalar kritis warga negara. Contohnya ialah ketika sosialisasi Pancasila yang bersumber dari negara juga ditegakkan oleh apparat negara, justru yang terjadi ialah adanya dominasi doktrinasi dan kepentingan rezim semata.
Oleh karena itu, alternatif yang dapat dikembangkan ialah menggunakan karya sastra sebagai sarana membentuk literasi politik. Karya sastra menjadi pilihan yang mumpuni karena sifatnya yang tidak selalu formal dan juga inklusif. Berbeda dengan pendidikan formal, karya sastra dapat dibaca secara luwes dan bebas oleh berbagai kalangan dengan rentang usia yang berbeda. Selain itu, karya sastra sendiri seringkali muncul sebagai sebuah gagasan yang secara organik berasal dari masyarakat sipil sendiri dan bukan dari negara. Inilah poin menarik yang ditawarkan karya sastra bahwa masyarakat sipil pun juga bisa berperan besar dalam mengedukasi dan menumbuhkan literasi politik bagi sesamanya melalui karya-karya nyata.
Dari penelitian kami yang mengkaji karya sastra dari penulis J. S. Khairen didapatkan bila terdapat banyak sekali unsur-unsur sastra yang bisa dikembangkan untuk membangun literasi politik. Dari novel ini dipaparkan mengenai prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat, serta pemikiran-pemikiran yang pro pada penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Aspek lain dari pembangunan literasi politik yang perlu diperkuat adalah multiplikasi dari karya-karya yang memang menekankan edukasi politik serta dorongan bagi masyarakat sipil untuk dapat saling belajar mengenai arti demokrasi dan hak sipil masyarakat.
Adapun manfaat karya sastra dalam mengembangkan literasi politik begitu terasa terutama di tengah iklim sebuah negara yang sedang mengalami konsolidasi demokrasi. Literasi politik yang sangat baik membantu warga masyarakat untuk memahami keadaan dan realitas politik, mengetahui sikap dan partisipasi apa yang harus dilakukan, serta memiliki pertanggungjawaban moral atas pilihan-pilihan politik yang dibuat secara konsisten dalam kurun waktu yang panjang.
Penulis: Febby Risti Widjayanto, S.IP., M.Sc
Sumber: Charisse Renica Benedicta Awa, Febby Widjayanto, “Karya sastra sebagai sarana literasi politik: Novel “Bungkam Suara” karya J. S. Khairen sebagai narasi melawan propaganda terkomputasi”.
Link jurnal: https://e-journal.unair.ac.id/POLINDO/article/view/65355/30447