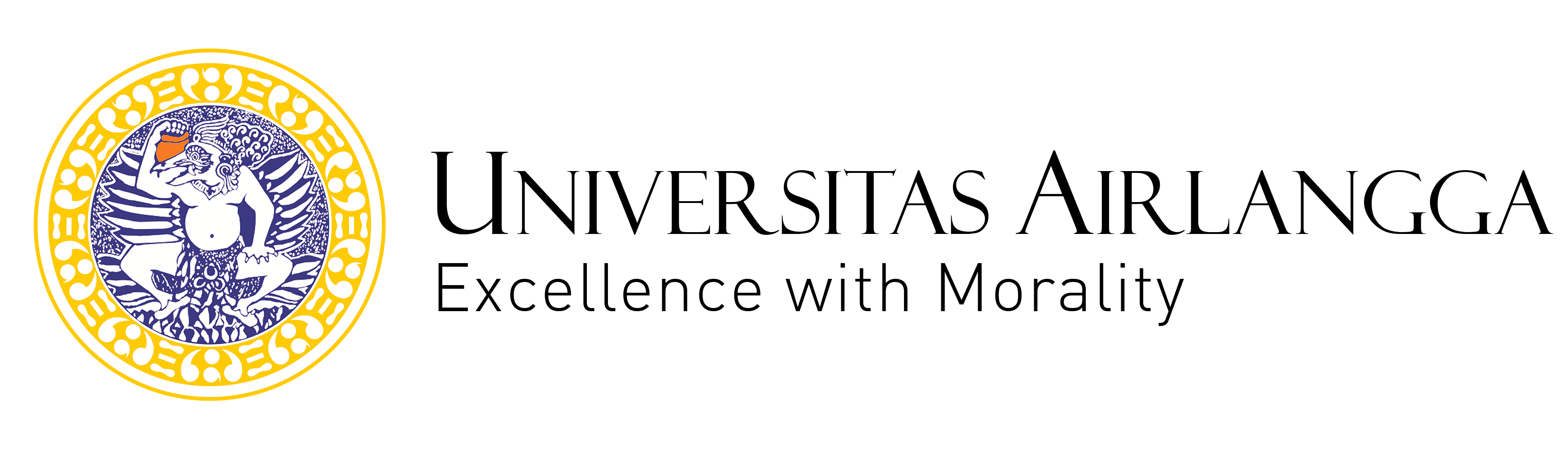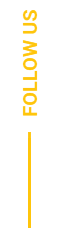Tujuh belas Agustus bukan sekadar tanggal dalam kalender, melainkan penanda sejarah ketika bangsa ini menegaskan dirinya sebagai entitas yang merdeka. Namun, makna kemerdekaan tidak berhenti pada bebas dari penjajahan fisik. Ia seharusnya menjelma dalam bentuk kemandirian di berbagai lini kehidupan, termasuk yang paling mendasar yakni pangan. Di negeri yang subur ini, ironisnya, kita belum sepenuhnya merdeka untuk menghidupi diri sendiri.
Indonesia adalah negeri yang dipeluk garis khatulistiwa, dianugerahi dua musim, tanah vulkanik yang subur, dan kekayaan hayati yang tak terkira. Di banyak tempat, bayangan sawah hijau dan aroma tanah basah setelah hujan adalah pemandangan sehari-hari. Dalam dongeng nasionalisme, kita sering menyebut tanah air ini sebagai negeri agraris, tanah surga yang konon, “Tongkat kayu dan batu pun bisa jadi tanaman” Tapi di balik pujian-pujian manis itu, realitas berkata lain.
Di tengah kekayaan lahan dan limpahan cahaya matahari sepanjang tahun, Indonesia masih tergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar: makan. Impor beras, gula, kedelai, dan bahkan garam, terus membengkak dari tahun ke tahun. Tahun 2023 saja, Indonesia mengimpor lebih dari 2 juta ton beras dari Thailand dan Vietnam. Data CNBC Indonesia (2025) mengungkap fakta yang lebih mengejutkan: peringkat swasembada pangan Indonesia di dunia hanya berada di posisi ke-69 dari 113 negara. Kita kalah jauh dari negara-negara yang bahkan tidak memiliki tanah subur seperti kita. Ini bukan sekadar ironi, tapi tamparan telak bagi narasi besar bahwa kita adalah negeri agraris.
Mengapa ini bisa terjadi? Satu jawabannya terletak pada fakta bahwa sektor pertanian sering kali dianggap sebagai sektor kelas dua. Petani identik dengan kemiskinan, kotor, dan kerja keras tanpa jaminan kesejahteraan. Anak-anak muda tak ingin lagi bercita-cita menjadi petani. Mereka lebih tertarik menjadi konten kreator, pekerja digital, atau pegawai di kota. Padahal, siapa yang akan mengolah tanah bila generasi penerusnya terus menjauh? Sementara itu, petani yang masih tersisa makin menua. Menurut data BPS, rata-rata usia petani di Indonesia pada tahun 2023 adalah 54 tahun. Regenerasi nyaris tak terjadi. Dalam diam, ketahanan pangan kita rapuh digantungkan pada bahu yang kian membungkuk dimakan usia. Kita seperti menabuh genderang perang kemerdekaan, tapi lupa mengisi perut sendiri.
Negara-negara maju mulai menyadari hal itu. Korea Selatan misalnya, justru memperkuat pertanian lokal dan melindungi petaninya dengan kebijakan yang tegas. Di Jepang, profesi petani disubsidi besar-besaran dan dihormati sebagai bagian dari kekuatan nasional. Petani tidak dianggap sebagai sisa masa lalu, tapi sebagai pelaku masa depan. Sementara kita? Masih sibuk mencetak sawah baru tanpa memperhatikan siapa yang akan menggarapnya. Masih menggelontorkan pupuk subsidi tanpa evaluasi menyeluruh. Masih membanggakan surplus ekspor nikel dan mobil listrik, tapi lupa bahwa kedaulatan pangan jauh lebih krusial bagi keberlangsungan bangsa.
Namun, harapan belum mati. Di berbagai daerah, muncul gerakan-gerakan kecil yang menunjukkan bahwa petani muda tidak benar-benar punah. Komunitas pertanian urban, petani milenial berbasis teknologi, hingga anak-anak muda lulusan universitas yang memilih kembali ke kampung untuk bertani mulai tumbuh. Mereka membawa cara pandang baru bahwa bertani bukan sekadar bertahan hidup, tapi juga bisa menjadi laku hidup yang modern, berkelanjutan, dan bermartabat.
Teknologi digital kini menjembatani mereka dengan pasar. Media sosial mengubah wajah petani dari pekerja pinggiran menjadi wirausahawan. Platform e-commerce lokal hingga aplikasi cuaca dan pemantauan tanah berbasis AI telah dimanfaatkan untuk memaksimalkan produksi sekaligus memperpendek jalur distribusi. Inovasi ini seharusnya menjadi perhatian utama negara. Sayangnya, dukungan sistemik terhadap petani muda masih belum maksimal. Akses terhadap lahan, permodalan, hingga perlindungan harga hasil panen masih jadi persoalan pelik. Pemerintah seharusnya tidak hanya bangga pada data produksi beras, tapi juga berani membangun ekosistem pertanian yang berpihak kepada generasi baru petani.
Di tengah gegap gempita perayaan 17 Agustus, semangat merdeka seharusnya juga menyala di sektor pertanian. Bukan dalam bentuk parade, tetapi dalam keberanian untuk merevolusi cara kita memperlakukan pangan dan petani. Tak ada gunanya berdiri tegap menyanyikan lagu kebangsaan jika masih ada anak-anak kelaparan karena beras harus menunggu impor. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita bisa memberi makan bangsa sendiri dengan hasil bumi sendiri, dari tangan rakyat sendiri. Itulah kedaulatan pangan. Di sanalah, kemerdekaan mendapatkan maknanya yang paling konkret dan membumi.
Penulis: Ameyliarti Bunga Lestari