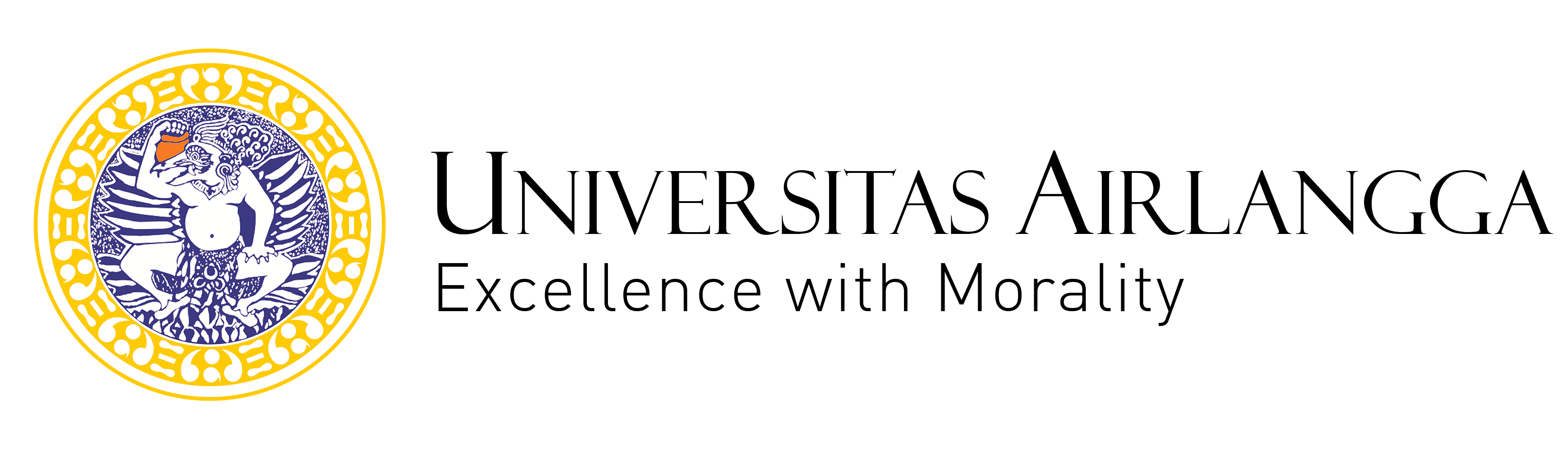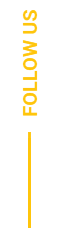Sejak dikeluarkannya wacana pariwisata sebagai motor penggerak pertumbuhan di kawasan konservasi, timbul konflik kepentingan terkait opsi pengembangan wilayah dan dampaknya terhadap lingkungan, budaya, dan ekonomi lokal (Hampton, 1995). Masalah ini menjadi lebih kompleks jika melibatkan isu sosial, geografi, politik, perencanaan, psikologi, dan infrastruktur (Collins-Kreiner & Wall, 2007). Oleh karena itu, kegiatan pariwisata pada kawasan konservasi diupayakan untuk selalu berada dalam konteks pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (Karim, Kusuma, & Mahfud, 2019; Rhama, 2020).
Meskipun pembangunan pariwisata berkelanjutan telah menjadi paradigma dalam pengembangan kawasan konservasi, banyak destinasi yang gagal mengatasi masalah keberlanjutan seiring semakin bertambahnya kunjungan wisatawan dan menyempitnya ruang dan waktu (Kušcer & Mihalic, 2019). Sistem zonasi yang diterapkan di beberapa taman nasional dihadapkan pada tekanan pariwisata sehingga harus memberikan ruang yang lebih luas pada kebutuhan ekowisata ketimbang konservasi. Apalagi dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan jumlah wisatawan saat ini cenderung berada pada kawasan-kawasan yang kaya biodiversitas tetapi rentan secara ekologis dan budaya (Hakim, Kim, & Hong, 2009). Studi dari Chung, Dietz and Liu (2018) mengkonfirmasi bahwa kunjungan wisatawan paling mungkin pada destinasi dengan keanekaragamanhayati yang tinggi, lebih tua, lebih besar, lebih mudah diakses dari kawasan kota, dan memiliki elevasi yang tinggi.
Studi ini mengkaji ancaman lingkungan terhadap pariwisata berkelanjutan taman nasional, seperti yang ditunjukkan melalui lima studi kasus taman nasional di Indonesia dan Afrika Selatan. Pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur digunakan dalam penelitian ini. Taman nasional yang dipilih terkait dengan kesamaan ekosistem, posisi, dan umur relatif terhadap taman nasional lainnya.
Dari perspektif ilmu sosial, fenomena pariwisata berkelanjutan dapat ditinjau dari perspektif TALC (Tourism Area Life Cycle) (Hawkins & Mann, 2007). Teori ini dikemukakan oleh Butler pada tahun 1980 dan telah mengalami banyak perkembangan kemudian.
Pada fase awal, setelah destinasi ditemukan dan ditetapkan (Exploration), masyarakat akan mengalami antusiasme, khususnya dengan potensi ekonomi yang akan mereka peroleh dan kemampuan untuk membangun daerahnya khususnya dari segi infrastruktur. Pada kondisi ini, masyarakat memasuki tahap keterlibatan dan destinasi mulai memasuki tahap pengembangan. Seiring waktu, masyarakat mulai merasakan dampak negatif dari pariwisata dan masyarakat mulai bersikap apatis dan euforia telah lenyap (Ionnaides, 2008). Pada gilirannya, masyarakat menjadi antagonis pada pariwisata karena menganggap kehidupan sehari-hari mereka telah terganggu dan pariwisata memasuki tahap stagnasi. Tahap selanjutnya, tergantung pada banyak faktor, akan membawa pada situasi rejuvenasi yang positif atau penurunan yang negatif.
Penelitian menunjukkan bahwa sedikit kemajuan telah dibuat dalam menerapkan pariwisata berkelanjutan di seluruh dunia dan di Afrika Selatan. Kurangnya kemajuan ini diperkuat oleh kurangnya kerangka kerja dan perencanaan pengelolaan yang tepat, termasuk pendekatan yang mendukung implementasi pariwisata berkelanjutan (Glen & Mearns, 2020). Studi ini menjelaskan dan membandingkan upaya yang dilakukan oleh lima taman nasional di Indonesia dan Afrika Selatan, dua negara berkembang, dalam mengelola, memelihara, dan meningkatkan pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini dibatasi pada lima taman nasional dengan karakteristik serupa. Taman nasional dari Indonesia adalah Baluran, Kayan Mentarang, dan Komodo, sedangkan Kruger dan Kgalagadi berasal dari Afrika Selatan. Baluran dipilih karena memiliki ekosistem sabana yang sama dengan Afrika, sehingga sering disebut sebagai Afrika van Java. Baluran merupakan satu-satunya taman nasional di Indonesia yang memiliki ciri khas tersebut. Kayan Mentarang dan Kgalagadi sama-sama diposisikan di perbatasan negara. Kgalagadi berada di perbatasan antara Afrika Selatan dan Botswana, sedangkan Kayan Mentarang berada di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Komodo adalah taman nasional tertua di Indonesia, seperti Kruger di Afrika Selatan. Kesamaan antara taman nasional yang diteliti didasarkan pada kesamaan ekosistem, umur, dan posisi geografis, bukan berdasarkan pendekatan standar pengelolaan konservasi.
Taman nasional di Indonesia dan Afrika Selatan dihadapkan pada banyak permasalahan yang unik dan umum. Taman nasional di kedua negara menghadapi hilangnya keanekaragaman hayati, spesies invasif, perubahan iklim, dan perburuan ilegal. Baluran memiliki masalah unik berupa invasi kera ekor panjang, sementara Taman Nasional Komodo dihadapkan pada perubahan perilaku megafauna utama, komodo. Masalah air dan kebakaran Taman Nasional Kruger unik dibandingkan dengan taman nasional lain yang diulas.
Kerangka dan perencanaan pengelolaan yang praktis diperlukan untuk mengatasi hambatan dan ancaman agar pengelolaan taman nasional dapat menerapkan praktik pariwisata berkelanjutan. Kerangka kerja pengelolaan dan perencanaan praktis ini perlu memperhitungkan masyarakat Taman nasional berbasis sabana perlu lebih fokus pada ketersediaan air. Sebaliknya, taman nasional berbasis perbatasan perlu fokus pada keanekaragaman hayati, yang melibatkan lebih banyak program konservasi dan keamanan untuk mengatasi penyakit dan perburuan ilegal. Taman nasional lama perlu lebih fokus pada masalah invasif, seperti spesies invasif dan interaksi manusia.
Setiap kendala yang dihadapi masing-masing taman nasional di Indonesia dan Afrika Selatan perlu diidentifikasi kesesuaian mekanisme yang dilakukan dengan kerangka dan perencanaan pengelolaan. Banyak model tidak memiliki skalabilitas dan replikasi, sehingga tidak dapat diartikulasikan dengan baik dan sering menyebabkan implementasi dan interpretasi yang tidak jelas atau salah. Intinya, kerangka yang sesuai perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing taman nasional.
Hasil studi menunjukkan sepuluh ancaman terhadap pariwisata berkelanjutan: hilangnya keanekaragaman hayati, spesies invasif, invasi ke luar, pembangunan infrastruktur, perubahan perilaku, perubahan iklim, kelangkaan air, kebakaran hutan, penyakit, dan perburuan liar. Isu-isu unik di Indonesia adalah invasi ke luar, pembangunan infrastruktur, dan perubahan perilaku, sedangkan isu-isu unik di Afrika Selatan adalah kelangkaan air, penyakit, dan kebakaran hutan. Taman nasional yang lebih tua cenderung memiliki masalah dengan spesies invasif, sementara taman nasional berbasis batas memiliki lebih banyak masalah dengan perburuan liar (perburuan liar). Taman nasional berbasis sabana dihadapkan pada hilangnya keanekaragaman hayati. Taman nasional perlu lebih fokus pada ancaman fisik ini untuk meningkatkan agenda pariwisata berkelanjutan mereka. Penelitian ini berkontribusi pada Model Siklus Hidup pariwisata taman nasional berkelanjutan dengan menyoroti kemungkinan jalur dalam model yang diikuti oleh taman nasional di Indonesia dan Afrika Selatan.
Penulis: Dian Yulie Reindrawatia, Bhayu Rama, Ulis Fajar CH
Link Jurnal: https://www.ajhtl.com/uploads/7/1/6/3/7163688/article_1_11_3_919-937.pdf