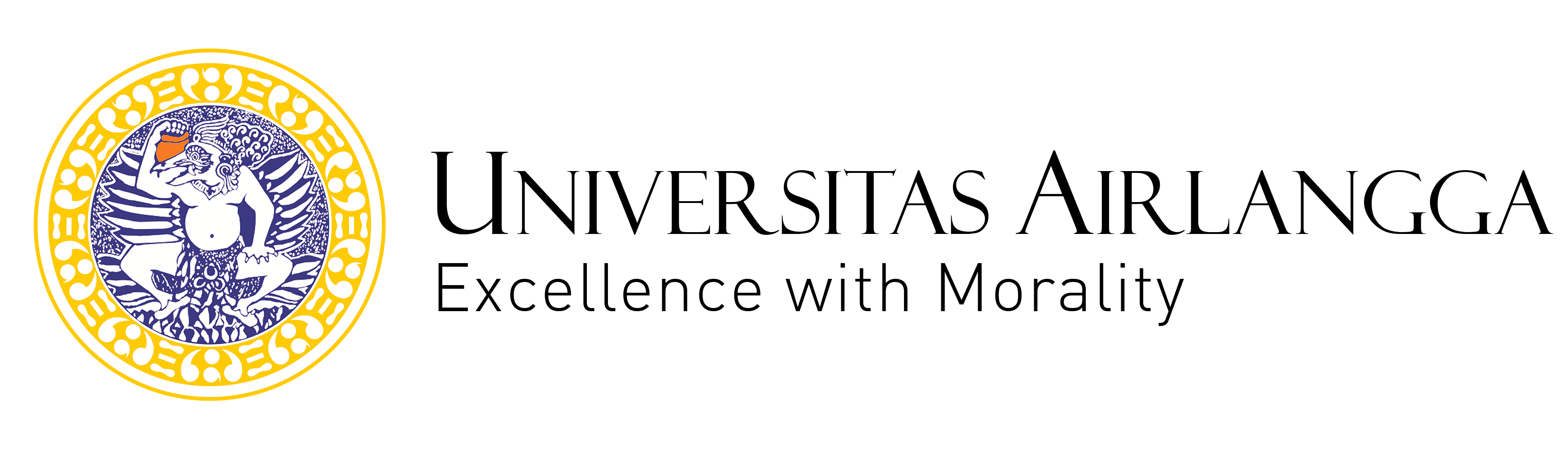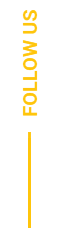Di Indonesia, kasus anak menikah di usia dini sudah lama menjadi keprihatinan berbagai pihak, karena besaran kejadian dan dampaknya yang mencemaskan. Secara nasional angka pernikahan dini masih berkisar pada angka 25,71 persen –yang berarti dari 100 perkawinan, 25 di antaranya dilakukan oleh anak di bawah umur. Data BPS memperlihatkan, angka pernikahan dini tahun 2018 meningkat menjadi 15,6% dibanding tahun sebelumnya yang hanya 14,18%. Provinsi dengan jumlah persentase kasus pernikahan dini tertinggi adalah Kalimantan Selatan (22,77%), Jawa barat (20,93%) dan Jawa Timur (20,73%).
Di Provinsi Jawa Timur, kasus pernikahan dini anak terutama banyak terjadi di daerah Tapal Kuda, yaitu Pulau Madura, Pasuruan, Probolinggo, Bondowo dan Situbondo yang kebanyakan dilakukan masyarakat etnis Madura. Pernikahan dini menjadi bagian dari kultur masyarakat di daerah Tapal Kuda, karena bagi anak perempuan, terutama, menikah dalam usia dini dianggap sah secara agama (Islam) dan secara sosial sudah selayaknya dilakukan agar tidak menjadi perawan tua.
Banyak studi telah membuktikan bahwa permasalahan dan efek pernikahan di usia dini bukan hanya terkait dengan kesiapan mental memasuki kehidupan berumah tangga yang berat, tetapi juga karena pernikahan di usia anak terbukti memutuskan peluang karier mereka dan menghambat upaya pengembangan potensi ekonomi anak di masa depan (Suyanto, 2013; Nguyen & Wodon, 2015; Durgut & Kisa, 2018). Bisa dibayangkan, apa yang terjadi ketika anak perempuan yang seharusnya masih berpeluang untuk meningkatkan modal sosial dan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tiba-tiba putus sekolah dan memilih atau dipaksa menikah karena berbagai pertimbangan. Alih-alih mengembangkan potensi sosial-ekonomi yang dimiliki, ketika menikah dan memiliki anak yang mengharuskan anak perempuan mengurus tugas-tugas domestik, maka apa yang semula dicita-citakan besar kemungkinan akan pupus di tengah jalan.
Dalam berbagai kasus, pernikahan anak ini mengundang keprihatinkan semua pihak, karena pernikahan anak bukan saja dinilai merampas hak-hak dasar anak perempuan untuk belajar, berkembang dan menjadi anak-anak seutuhnya, tetapi juga berpotensi membuka pintu bagi terjadinya berbagai tindak kekerasan (Boyce, Brouwer, Triplett, Servin, Magis-Rodriguez, & Silverman, 2018). Tidak mustahil terjadi, anak perempuan yang seharusnya masih menghabiskan waktunya untuk bersekolah dan bermain, kemudian dinilai sudah pantas berumah tangga, yang kemudian mensahkan para suami untuk mendidik atau bahkan mencari istri lain sebagai pelengkap. Di Indonesia, tidak sedikit anak menjadi korban praktik poligami. Mereka menikah dalam usia dini, tetapi kemudian suaminya mencari istri baru dengan dalih atau pembenar secara moral-sosial yang tidak memungkinkan anak perempuan itu protes. Pernikahan dini dan poligami adalah dua hal yang acapkali terjadi berbarengan –yang menyebabkan anak perempuan menjadi korban ketidakadilan.
Sudah bukan rahasia lagi, bahwa anak-anak perempuan yang terjerumus menikah dalam usia dini, mereka dalam tempo yang cepat kemudian menyandang status sebagai janda muda yang harus menghadapi stigma dan beban kehidupan yang lebih berat. Akibat ketidaksiapan mental dan kekeliruan menafsirkan romantisme percintaan, anak-anak perempuan tidak sedikit yang terpaksa cerai ketika pernikahan mereka belum memasuki hitungan tahun. Anak perempuan yang menikah di usia dini, seringkali mereka tidak dapat melanjutkan sekolah, dan lebih mungkin menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, dan bahkan tindak pemerkosaan (marital rape).
Untuk memastikan agar tidak muncul kasus-kasus yang merugikan masa depan anak perempuan ini, selama ini sejumlah organisasi besar yang peduli nasib perempuan, seperti Fatayat NU, KUPI, dan lain-lain gigih memperjuangkan upaya merevisi UU perkawinan, khususnya pada pasal usia minimal anak perempuan diperkenankan menikah. Batas usia minimal bagi perempuan untuk menikah, yang semula 16 tahun disepakati diubah menjadi 19 tahun. Batas ini juga berlaku bagi laki-laki. Selain untuk mencegah praktik perkawinan anak, keputusan menaikkan batas usia minimal perempuan menikah ini diharapkan akan menciptakan generasi emas sesuai cita-cita pembangunan nasional (Tajuk Rencana Kompas, 23 September 2019).
Dari segi medis, keputusan menaikkan batas usia minimal menikah bagi perempuan ini, diharapkan bermanfaat menurunkan resiko kematian pada ibu dan anak, sekaligus juga mencegah agar perkawinan pada usia dini tidak berakhir dengan perceraian yang merugikan perempuan dan anak. Sejauhmana perubahan payung hukum dan ketentuan yang meningkatkan batas minimal usia anak perempuan menikah ini berhasil mengerem laju kasus pernikahan dini di Indonesia, tentu masih diuji oleh waktu. Tetapi, paling-tidak dengan disahkannya aturan tentang peningkatkan batas usia menikah ini, para aparat di tingkat lokal memiliki pegangan dan acuan yang lebih kuat untuk mencegah kasus pernikahan dini di lapangan.
Studi yang dilakukan penulis telah mewawancarai 300 anak perempuan yang menikah di usia dini. Studi ini menarik karena telah memetakan bahwa akar penyebab terjadinya kasus pernikahan dini bukan sekadar karena alasan ekonomi, tetapi juga ada factor-faktor sosial-budaya yang mempengaruhi, termasuk kondisi habitus yang mendukung. Anak-anak perempuan yang kurang berpendidikan, terkontaminasi bias ideology patriakrhis, dan sikap anak perempuan yang cenderung makin permisif, sedikit-banyak mempengaruhi cara pandang massyarakat yang pro kepada pernikahan dini anak perempuan. Anak perempuan yang menikah dalam usia dini bukan hanya beresiko mengalami gangguan medis, tetapi juga menyebabkan anak perempuan harus terhambat kelangsungan pendidikan dan kesempatan mereka untuk bekerja setelah harus bertanggungjawab pada tugas-tugas domestik rumah tangga. Perkawinan pada usia muda membebani anak perempuan dengan tanggung jawab menjadi seorang istri, pasangan seks, dan ibu, peran-peran yang seharusnya dilakukan orang dewasa, yang belum siap untuk dilakukan oleh anak perempuan. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini juga memiliki kaitan yang erat dengan kemungkinan terjadinya tindak kekerasan oleh pasangan intim (intimate partner violence), paling-tidak verbal abuse yang melukai perasaan mereka.
Bagong Suyanto, Rahma Sugihartati, Medhy Aginta Hidayat, Nadia Egalita, Siti Masudah. The Causes and Impact of Early Marriage, The Ordeal of Girl in east Java, Indonesia. Sociologia, Problemas & Praticas, No. 101, 20232, pp 71-94. DOI: 10.7458/SPP202310126851