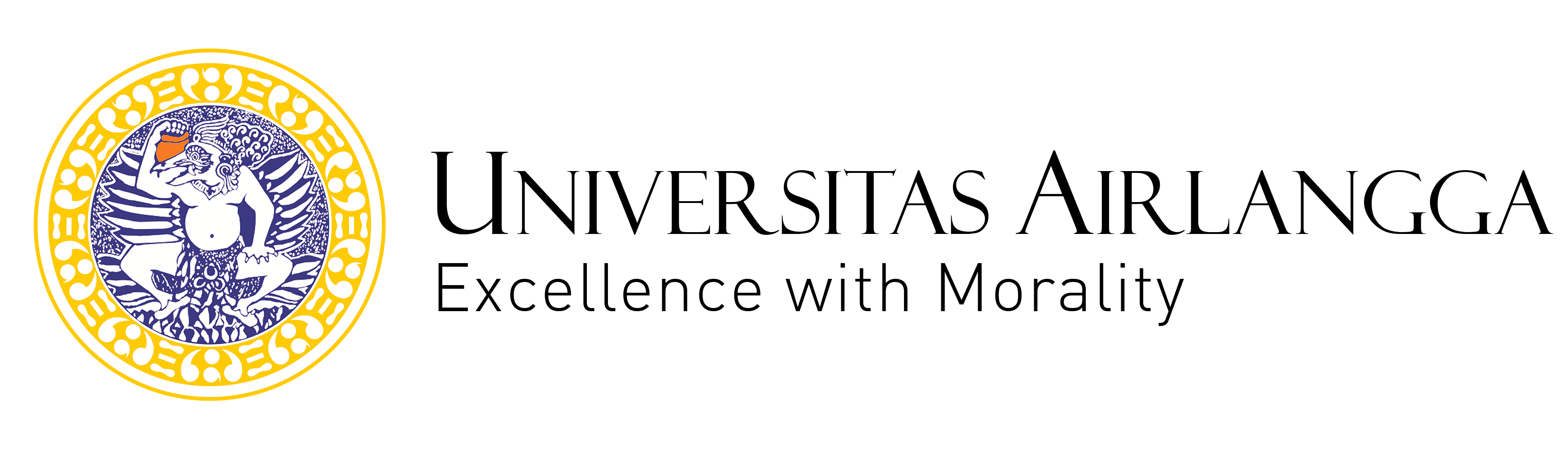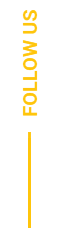UNAIR NEWS — Rangkaian kegiatan BBK 7 Internasional dibuka melalui agenda Disaster Management Lecture & Planning yang menekankan disaster risk reduction, community preparedness, dan resilience sebagai fondasi membangun komunitas yang lebih tangguh. Sesi ini dipresentasikan oleh Dr. Miki Mochizuki, Senior Lecturer dari Shizuoka University, yang memandu peserta memahami bahwa bencana tidak semata dipahami sebagai fenomena alam, tetapi sebagai kondisi krisis yang mengganggu keberfungsian kehidupan sehari-hari—mulai dari komunikasi, rutinitas, akses layanan, hingga jejaring sosial yang menopang masyarakat. Cara pandang ini memperjelas relevansi SDG 11 (Sustainable Cities and Communities): ketangguhan kota dan komunitas bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang kesiapan sosial, koordinasi warga, dan kapasitas untuk pulih secara kolektif.
Materi dibuka dengan pertanyaan mendasar “What is a disaster?” sebagai pengantar untuk membangun kerangka berpikir yang lebih sosial dan sistemik. Pembahasan kemudian menekankan hubungan hazard (ancaman) dan vulnerability (kerentanan), dengan pengingat bahwa risiko terbentuk bukan hanya dari besarnya ancaman, tetapi juga dari siapa/apa yang terpapar serta seberapa siap komunitas merespons. Upaya pengurangan risiko bencana pada akhirnya berfokus pada penurunan kerentanan serta peningkatan kapasitas masyarakat. Di titik ini, lecture tidak berhenti pada konsep, tetapi mendorong risk awareness yang lebih nyata: peserta diajak memahami mengapa bencana yang sama dapat berdampak berbeda pada komunitas yang memiliki tingkat kesiapan, sumber daya, dan jaringan dukungan yang berbeda. Pendekatan ini selaras dengan SDG 4 (Quality Education) karena membangun disaster education yang aplikatif dan memperkuat capacity building—bukan hanya “tahu”, tetapi mampu menilai risiko, mempersiapkan langkah, dan mengambil keputusan dalam waktu terbatas.
Diskusi mengenai ragam bencana di Jepang memperlihatkan bahwa strategi mitigasi harus berbasis konteks ancaman dan kondisi sosial setempat, termasuk gempa besar, tsunami, serta bencana hidrometeorologi seperti topan dan banjir akibat hujan ekstrem. Pada bagian ini, keterkaitan dengan SDG 13 (Climate Action) menjadi semakin kuat: climate adaptation dan climate resilience menuntut kesiapan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif—mulai dari perencanaan wilayah, pemutakhiran peta risiko, hingga latihan evakuasi yang meniru situasi riil. Ketika intensitas cuaca ekstrem meningkat, kesiapsiagaan komunitas harus berkembang menjadi kebiasaan yang terus diperbarui, bukan sekadar agenda sesekali.
Salah satu poin kuat dalam sesi ini adalah pembahasan ekosistem respons bencana di Jepang yang menyeimbangkan public assistance (dukungan pemerintah/institusi), mutual support (dukungan komunitas/relawan), dan self-help (kesiapsiagaan individu/keluarga). Kerangka ini menunjukkan bahwa pada fase awal pascabencana, kapasitas institusional dapat terganggu
oleh skala kerusakan, akses yang terputus, dan keterbatasan layanan, sehingga kekuatan komunitas—melalui koordinasi warga dan relawan—menjadi penentu pemenuhan kebutuhan dasar. Kerja sama tiga pilar ini memperkuat SDG 11 karena membangun sistem sosial yang mampu bergerak cepat saat krisis, sekaligus mengurangi ketimpangan akses bantuan bagi kelompok rentan.
Sesi juga menguraikan tahapan pascabencana—dari evakuasi, kehidupan di tempat pengungsian, hingga rekonstruksi—yang menegaskan bahwa pemulihan bukan hanya soal “membangun kembali”, tetapi memulihkan keberfungsian sosial dan kualitas hidup. Dalam konteks SDG 3 (Good Health and Well-being), pembahasan emergency response dan first aid menjadi krusial karena keselamatan pada jam-jam awal sangat bergantung pada kesiapan warga untuk merespons secara tepat. Lebih jauh, materi menekankan aspek mental health melalui risiko isolasi sosial pascabencana, termasuk fenomena solitary deaths dan konsep double loss ketika penyintas kehilangan jaringan sosial berulang kali akibat relokasi. Artinya, kesejahteraan setelah bencana tidak cukup diukur dari pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga dari keberhasilan menjaga martabat, rutinitas, peran sosial, dan makna hidup penyintas.
Keterkaitan antara bencana dan adaptasi iklim juga terlihat dalam pembahasan tsunami melalui pembedaan skenario Level 1 dan Level 2. Skenario yang lebih sering terjadi menuntut perlindungan struktural yang “rutin”, sementara skenario besar yang jarang terjadi menuntut pendekatan mitigasi korban jiwa melalui evakuasi efektif dan pertahanan berlapis. Contoh implementasi seperti seawall, evacuation hills, serta relokasi terencana menunjukkan bagaimana perencanaan berbasis risiko dapat memperkuat climate resilience di wilayah pesisir—sejalan dengan SDG 13—karena risiko bencana berlapis seringkali diperparah oleh dinamika cuaca ekstrem.
Pada bagian akhir, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok bersama mahasiswa Shizuoka University untuk membandingkan praktik disaster drills di Jepang dan Indonesia. Diskusi ini memperkuat SDG 4 karena mendorong pembelajaran reflektif dan berbasis pengalaman: peserta tidak hanya menerima materi, tetapi mengidentifikasi gap praktik, menilai relevansi kebijakan, dan menyusun insight yang dapat diadaptasi. Benang merah yang muncul adalah pentingnya latihan yang konsisten, realistis, dan inklusif—melibatkan kelompok rentan, menguji manajemen shelter, serta membiasakan koordinasi komunitas—sehingga respons darurat dapat lebih cepat dan lebih terstruktur ketika situasi nyata terjadi.
Secara keseluruhan, Disaster Management Lecture & Planning menegaskan bahwa ketangguhan bukan hasil satu kebijakan atau satu infrastruktur, melainkan kombinasi pemahaman risiko, edukasi yang berulang, perencanaan berbasis data, serta jejaring dukungan yang hidup di komunitas. Dengan menghubungkan disaster risk reduction (SDG 11), climate adaptation dan climate resilience (SDG 13), disaster education dan capacity building (SDG 4), serta emergency response, first aid, dan mental health (SDG 3), kegiatan ini memberi fondasi yang utuh bagi peserta untuk memahami kesiapsiagaan sebagai upaya yang menyeluruh—melindungi keselamatan fisik sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupan sosial dan kesejahteraan manusia.
Penulis: Mahasiswa BBK 7 Shizouka