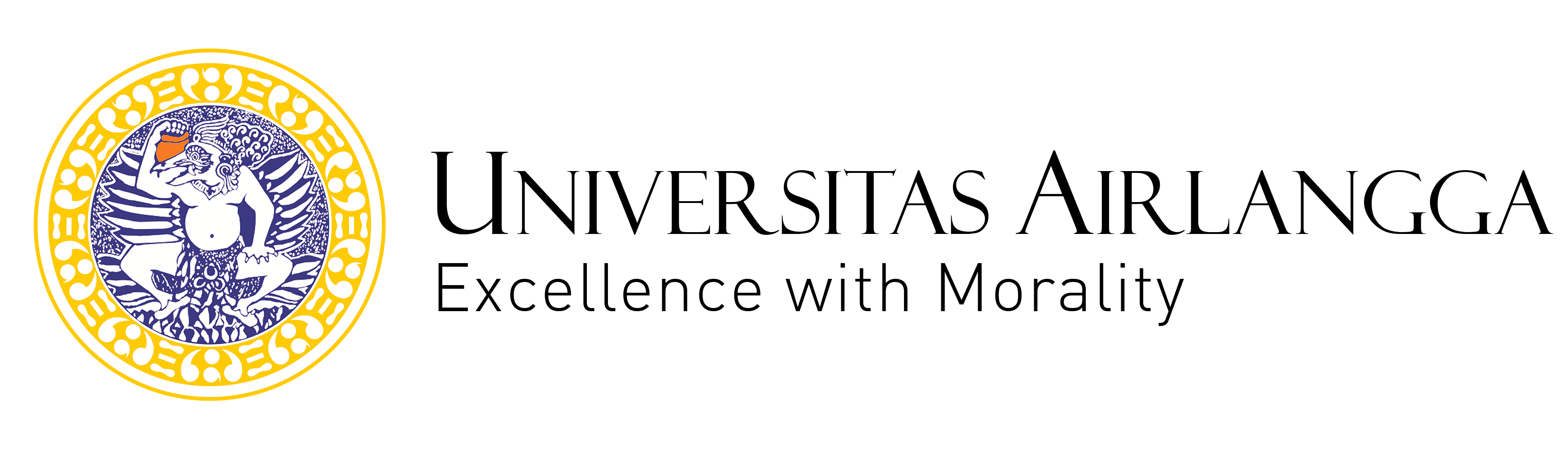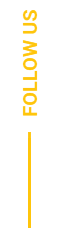Setiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Penetapan tanggal tersebut disesuaikan dengan tanggal kelahiran Suwardi Suryaningrat atau yang biasa dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantara, yang lahir pada 2 Mei 1889. Ki Hadjar Dewantara adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia pertama (dulu disebut Menteri Pengajaran Indonesia), tokoh pelopor pendidikan di Indonesia, dan telah dihormati sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia.
Semboyan pendidikan yang terkenal dari Ki Hadjar Dewantara adalah: ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani, yang artinya “di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan.”
Dalam suasana peringatan Hardiknas itu, perlu bagi bangsa ini untuk melakukan refleksi terhadap makna dari pendidikan. Melalui itu, diharapkan kita mendapat energi yang segar sehingga mampu lebih maksimal dalam mengembangkan iklim pendidikan di Indonesia di hari-hari selanjutnya.
Makna pendidikan
Pendidikan adalah sarana sosialisasi terbaik dalam sejarah peradaban umat manusia. Pendidikan membekali seorang individu untuk menjadi berkembang dalam berbagai dimensi: mulai dari soal pengetahuan, keterampilan, logika, sikap dan karakter, nilai-nilai, hingga yang paling tinggi yaitu kebijaksanaan.
Sementara itu, Paulo Freire (1921-1997), seorang ahli pendidikan dari Brasil, menekankan arti penting pendidikan sebagai sarana pembebasan. Artinya, pendidikan mesti menjadikan seorang individu sebagai manusia yang independen, berdaya, dan merdeka. Pendidikan mesti ditujukan agar seorang individu berdaya dalam merumuskan nilai-nilai yang relevan yang akan menjadi pedoman bagi individu tersebut dalam menavigasi diri dan kehidupannya.
Dalam upaya membentuk individu yang independen, berdaya, dan merdeka itu, peran pengajar dalam proses pendidikan menjadi sangat sentral di sini. Ihwal ini, Latif (2020) menjelaskan bahwa peran pengajar adalah membantu para siswa dalam menemukan dan mengembangkan potensi mereka. Kepekaan seorang pengajar akan potensi siswa sangat penting di sini. Dalam konteks ini pula, maka, model pendidikan di mana seorang pengajar mendikte para siswa dalam gaya “harus ini, harus itu!” adalah sesuatu yang mesti dijauhkan. Tak kalah penting, pengajar juga mesti mengingatkan secara teratur kepada peserta didik agar pengembangan potensi mereka untuk menjadi individu yang independen, berdaya, dan merdeka tidak boleh ditujukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi mesti selalu dalam semangat untuk kepentingan yang lebih luas yaitu kepada orang di sekitar, kepada bangsa, dan kepada masyarakat global.
Pendidikan di era digital
Selain itu, dunia sekarang mengalami perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat masif, atau yang biasa disebut sebagai era digital. Dan, di era digital ini, timbul persoalan-persoalan kolektif yang serius seperti hoax, ujaran kebencian, fitnah, dan narasi-narasi intoleran di ruang-ruang digital. Maka, kegiatan pendidikan mesti ditempatkan juga dalam konteks perkembangan era digital ini. Lembaga pendidikan mesti berkontribusi dalam menjawab tantangan-tantangan yang dibawa oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Ihwal kasus kejahatan di dunia digital di Indonesia, secara khusus mengenai hoax, data Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) tahun 2019 menunjukkan bahwa, sebanyak 87,50 persen responden mengklaim menerima hoax melalui media sosial dan 67 persen melalui aplikasi obrolan. Tema hoax yang paling banyak diterima oleh responden adalah tema sosial-politik (93,20 persen), SARA atau diskriminasi berbasis suku, agama, dan ras (76,20 persen), dan pemerintah (61,70 persen). Perluasan hoax yang masif ini menimbulkan ketegangan sosial dan pembelahan sosial di kalangan masyarakat, yang selanjutnya menggerus integrasi sosial bangsa.
Hemat penulis, kontribusi lembaga pendidikan dalam menghadapi persoalan kejahatan di dunia digital dapat dijalankan dalam bentuk meningkatkan literasi digital kepada peserta didik. Literasi digital ini harus mulai ditanamkan sejak di tingkat pendidikan dasar melihat kenyataan bahwa kebanyakan generasi yang lahir di abad ke-21 sudah menggunakan handphone, smartphone, dan perangkat teknologi informasi lainnya sejak usia mereka masih kecil. Literasi digital ini dapat dijalankan, misalnya, dengan mengajarkan kepada peserta didik agar ketika mereka menemukan informasi-informasi yang bernada sensitif dan provokatif di dunia digital, maka mereka tidak boleh langsung mencerna informasi tesebut, tetapi perlu meragukannya atau menanyakan kepada guru mereka atau orang yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan tentang kebenaran dari informasi itu.
Semangat mempertanyakan seperti itu dalam literasi digital tidak lain adalah peran lembaga pendidikan dalam membentuk peserta didik menjadi pribadi yang kritis. Pentingnya meningkatkan keterampilan berpikir kritis dikarenakan fenomena maraknya praktik kejahatan di dunia digital, misalnya berita bohong, menandakan rendahnya keterampilan berpikir kritis dari masyarakat kita. Ketika berita bohong begitu mudah dibagikan, itu berarti penilaian kita kabur dan kemampuan analisis kita menyedihkan. Kondisi ini dalam tingkat tertentu adalah hasil dari kurikulum pendidikan yang tidak berfokus pada aspek berpikir kritis. Di Indonesia kita menemukan kenyataan itu. Siswa terbiasa menghafal sejak di sekolah dasar tanpa berfokus pada keterampilan berpikir kritis. Ketika menerima informasi, siswa diminta untuk menghafal, bukan untuk mempertanyakan apakah informasi yang mereka terima benar, atau mengapa begitu adanya. Hal-hal seperti itu berlanjut dibawa ke domain publik, domain di mana seseorang semakin banyak berhadapan dengan lalu lintas informasi. Masyarakat kita terbiasa menerima informasi begitu saja, alih-alih mempertanyakannya (Dwifatma, 2019).
Berdasarkan itu, pola pendidikan konvensional yang menempatkan peserta didik dalam posisi sekadar menerima materi yang diajarkan atau menghafal bacaan-bacaan, mesti digeser ke arah peserta didik yang terangsang untuk bertanya atau menanggapi materi yang diajarkan dan melakukan analisis atas bacaan-bacaan. Dorongan untuk mempertanyakan dan menganalisis seperti itu dalam lingkup akademis kemudian dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peserta didik ketika berhadapan dengan berbagai realitas sosial di sekitar tempat tinggalnya, termasuk di antaranya fenomena berita bohong, ujaran kebencian, fitnah, narasi-narasi intoleran dan kejahatan-kejahatan lainnya yang terdapat di dunia digital.
Dalam suasana seputar peringatan Hardiknas, sambil terus menegaskan pendidikan sebagai sumber utama kemajuan peradaban manusia, bangsa ini juga mesti secara sungguh memastikan dan menjadikan pendidikan sebagai kompas yang adaptif dan relevan dalam menuntun kehidupan bangsa di jalur yang tepat, termasuk dalam berhadapan dengan era digital ini.
Penulis: Ransis Raenputra, Mahasiswa Sosiologi FISIP Universitas Airlangga