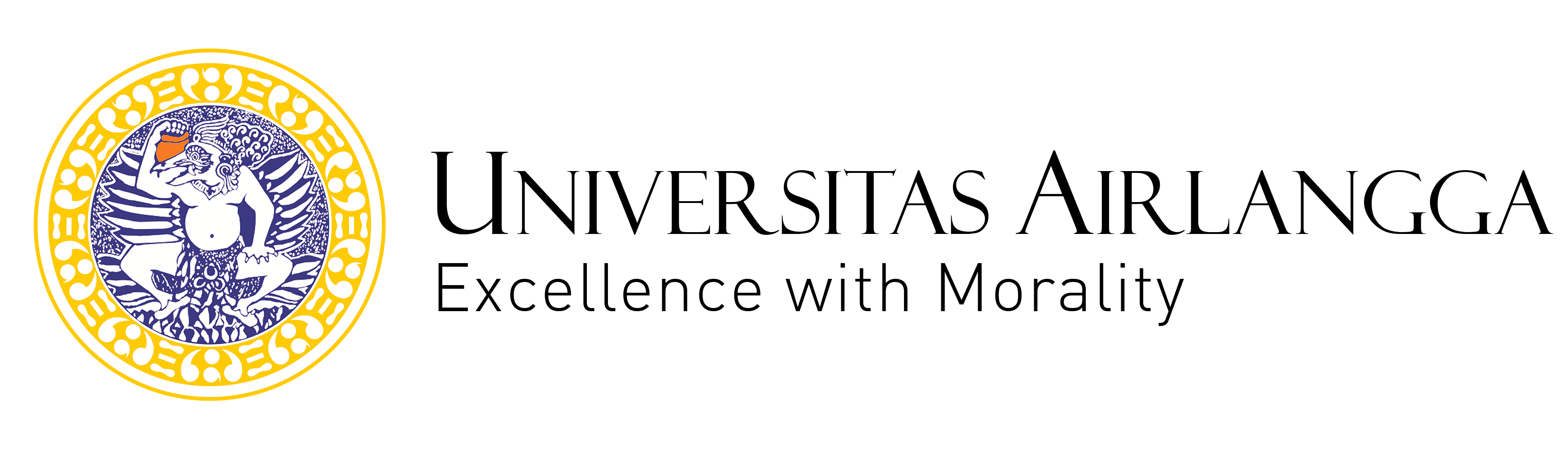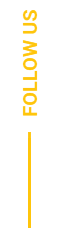Penyakit dekompresi masih menjadi masalah dalam dunia penyelaman. Di Indonesia, insiden penyakit dekompresi pada penyelam tradisional mencapai lebih dari 50%. Penyakit dekompresi juga dapat terjadi pada pekerja penyelam kering (pekerja tambang atau caisson) dan penerbang. Penyakit dekompresi mempunyai gejala klinis yang luas dan dapat mengalami perburukan secara cepat. Bahkan, penyelam yang tidak pernah menunjukkan gejala penyakit dekompresi dapat mengalami gangguan kesehatan jangka panjang.
Awalnya, gelembung gas nitrogen yang terbentuk sewaktu penyelam naik ke permukaan diyakini sebagai penyebab penyakit dekompresi. Namun, penelitian terbaru membuktikan bahwa penyakit dekompresi didahului oleh terjadinya disfungsi endotel dan gelembung hanya berperan sebagai faktor pemberat dan bukan penyebab penyakit dekompresi. Gelembung nitrogen terbentuk melalui bubble nuclei sewaktu penyelam naik ke permukaan dan lepas ke dalam aliran darah. Lepasnya gelembung nitrogen menyebabkan terjadinya perubahan pola aliran darah (shear stress) sehingga terjadi kerusakan mekanik terhadap membran sel endotel dan berpotensi mencetuskan sinyal yang mengarah pada terjadinya inflamasi dan injuri endotel.
Upaya pencegahan penyakit dekompresi yang dilakukan selama ini terbatas pada perencanaan penyelaman menggunakan tabel penyelaman untuk meminimalisir pembentukan gelembung nitrogen sewaktu naik ke permukaan. Adanya fenomena adaptasi dalam penyelaman memungkinkan dilakukannya tindakan prakondisi yang mengubah paradigma pencegahan penyakit dekompresi. Berbagai penelitian yang telah dilakukan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir membuktikan bahwa tindakan prakondisi sebelum penyelaman terbukti mempengaruhi jumlah gelembung yang terbentuk setelah penyelaman, mencegah penurunan FMD dan disfungsi endotel serta mencegah terjadinya penyakit dekompresi. Beberapa bentuk prakondisi yang pernah diteliti baik pada manusia atau hewan coba adalah latihan fisik, whole body vibration, pajanan panas, konsumsi coklat, pemberian suplemen antioksidan, pemberian statin, hidrasi, dan oksigen hiperbarik.
Oksigen hiperbarik adalah pemberian 100% oksigen dalam ruangan yang diberi tekanan lebih dari 1 atmosfer. Tekanan yang diberikan pada oksigen hiperbarik dibatasi hingga 3 Atmosfer Absolut, apabila lebih dari itu maka risiko terjadinya keracunan oksigen semakin meningkat. Prakondisi Oksigen hiperbarik telah digunakan untuk mencegah penyakit dekompresi sebelum penerbangan atau pada awak kapal selam saat terjadinya kecelakaan yang mengharuskan mereka naik ke permukaan dengan cepat.
Efek proteksi prakondisi OHB diperkirakan terjadi melalui beberapa mekanisme antara lain peningkatan kandungan oksigen pada area yang mengalami iskemia akibat emboli gelembung, penurunan volume atau jumlah gelembung melalui eliminasi inti gelembung (bubble nuclei), melibatkan nitric oxide dan heat shock protein, meningkatkan sitokin anti-inflamasi, menurunkan penanda inflamasi (endothelin-1 (ET-1) dan VCAM-1) dan menginduksi ekspresi antioksidan yang secara keseluruhan dapat mencegah disfungsi endotel pada penyakit dekompresi. Prakondisi oksigen hiperbarik juga telah diterapkan pada model hewan coba lain dan menunjukkan adanya toleransi terhadap injuri melalui induksi ekspresi gen – gen protektif yang menjadikannya sebagai salah satu prakondisi stres yang dapat melindungi sel dari pajanan selanjutnya.
Pemberian prakondisi oksigen hiperbarik harus dilakukan pada waktu, dosis dan cara tertentu. Panjangnya interval waktu antara pemberian oksigen hiperbarik dengan penyelaman dapat menghilangkan efek mekanik oksigen hiperbarik, terlebih waktu yang umumnya dibutuhkan agar populasi bubble nuclei kembali ke kondisi awal antara 10 – 100jam. Efek pencegahan penyakit dekompresi oleh prakondisi oksigen hiperbarik tidak hanya disebabkan oleh tekanan per se namun juga akibat peningkatan tekanan parsial oksigen. Hal tersebut dibuktikan bahwa pemberian oksigen 100% dapat menurunkan insiden penyakit dekompresi namun prakondisi normoksik hiperbarik, yaitu pemberian oksigen dengan tekanan parsial 20% pada ruang bertekanan tinggi, tidak menurunkan insiden penyakit dekompresi.
Sama halnya dengan terapi lain, Oksigen hiperbarik juga memiliki efek samping diantaranya adalah barotrauma dan keracunan oksigen. Barotrauma merupakan cedera yang disebabkan oleh perubahan tekanan di tubuh akibat perubahan tekanan lingkungan. Perubahan tekanan lingkungan akan menyebabkan terjadinya penurunan volume area tubuh yang berongga, yang apabila tidak dilakukan penyesuaian dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada organ. Barotrauma dapat terjadi pada telinga tengah, sinus, paru-paru, gigi dan juga saluran pencernaan. Beberapa cara dapat dilakukan untuk menurunkan risiko terjadinya barotrauma adalah dengan pemeriksaan awal untuk memastikan tidak adanya sumbatan dalam saluran sinus atau telinga tengah, tehnik valsava, mengatur kecepatan kompresi dan dekompresi serta pemberian dekongestan. Oksigen dapat bersifat toksik terhadap sistem saraf pusat, paru-paru dan jaringan lainnya. Peningkatan fraksi oksigen dalam pernafasan selama pemberian oksigen hiperbarik meningkatkan risiko keracunan yang ditandai dengan pusing, mual, muntah, penglihatan terganggu, tinnitus, batuk dan yang paling buruk adalah kejang. Karena itulah dilakukan pembatasan dosis pemberian oksigen hiperbarik serta edukasi kepada pasien untuk dapat mengenali gejala-gejala awal dari keracunan oksigen.
Prakondisi oksigen hiperbarik mempunyai potensi yang dapat dikembangkan sebagai suatu metode pencegahan penyakit dekompresi. Namun hingga saat ini, belum terdapat standarisasi bagaimana pemberian prakondisi oksigen hiperbarik yang tepat dalam rangka mencegah terjadinya penyakit dekompresi. Diharapkan dimasa yang akan datang, penelitian terkait dengan prakondisi oksigen hiperbarik dalam mencegah penyakit dekompresi dapat dikembangkan sehingga bermanfaat terutama bagi penyelam tradisional di Indonesia.
Penulis : Sofia Wardhani, Aryati Aryati, and Bambang Purwanto
Artikel ini di publikasikan di jurnal : Pharmacognosy Journal
Dan dapat di akses di :