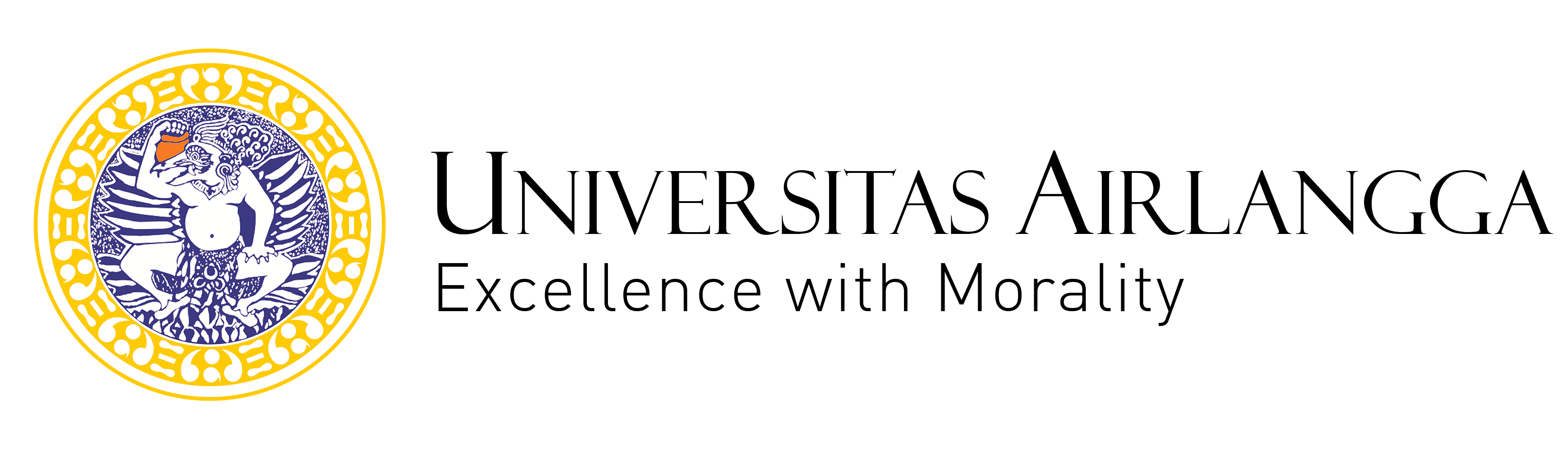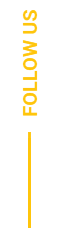Perkembangan perkudaan di Jawa Timur semakin baik seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan status sosial masyarakat. Pada awalnya kuda hanya dipergunakan sebagai salah satu moda transportasi yang menghubungkan antar kota dalam provinsi. Sekitar 1980-an setelah pordasi terbentuk di Provinsi Jawa Timur, olahraga kuda equestrian pertama kali masuk di Surabaya dan ikut menyumbangkan emas dalam event olahraga berkuda. Bidang peternakan daerah Jawa Timur pertama kali dan sampai sekarang di daerah Tretes dan dikelola menjadi dua bagian, yaitu profesional swasta pribadi dan peternakan rakyat.
Pasang-surut perkembangan kuda dipengaruhi juga dari sisi politik secara keseluruhan baik oleh pemerintah dan perkembangan olahraga berkuda. Sentra kuda di Jawa Timur sampai tahun 2015 adalah Surabaya, Malang, Pasuruan, Sidoarjo, Mojosari (Mojokerto), Magetan, Jember, Gresik, Pacitan, Banyuwangi, dan Kediri, dengan populasi tertinggi berada di Surabaya, Malang, Kediri. Sentra kuda terdapat juga di bangkalan Madura. Semua sentra tersebut mengembangbiakkan berbagai macam jenis ras kuda sesuai dengan kebutuhan dari aktivitas yang digunakan.
Cacingan pada kuda dapat menyebabkan gangguan Kesehatan dan golongan cacing Strongylids dapat menginfeksi kuda dan gejala klinis yang muncul adalah diare khususnya pada anak kuda. Gejala yang umum terjadi adalah diare, anemia, penurunan bobot badan, dehidrasi, gangguan pernapasan dan dermatitis. Kondisi ini bisa menjadi fatal jika terjadi pada anak kuda. Pengobatan biasanya dengan obat cacing tetapi beberapa kasus tidak menunjukkan hasil yang baik dikarenakan terjadinya resistensi anthelmintic. Cacing golongan Strongylids sebagian dapat menular ke manusia (zoonosis). Kuda terinfeksi oleh cacing Strongyloid dengan memakan rumput yang terkontaminasi telur cacing atau larva infektif dan penetrasi kulit oleh larva infektif. Manusia dapat terinfeksi cacing Strongylids melalui kulit, seperti berjalan kaki tanpa alas kaki.
Di Indonesia penelitian prevalensi Strongylids pernah dilakukan seperti pada kuda cidomo di Lombok Timur dengan hasil 12% kuda terinfeksi cacing. Penelitian cacing pada kuda juga sudah dilaporkan di luar negeri seperti di Kentucky dengan hasil 30% dan di distrik Al-Diwaniyah, Irak, dengan hasil 22,72% terinfeksi cacing Strongylids. Berat ringannya kejadian infeksi dipengaruhi oleh cara pemeliharaan. Pemeliharaan kuda di stable Jawa Timur bersifat semi intensif meskipun kadang dilepaskan untuk merumput.
Lantai kandang terbuat dari semen yang dilapisi serbuk kayu dan dibersihkan setiap pagi dan sore hari. Didasari dari kenyataan tersebut perlu dilakukan penelitian mengenai identifikasi dan untuk mengetahui prevalensi infeksi cacing nematoda khususnya golongan Strongylids yang berpotensi zoonosis pada kuda sehingga memudahkan perencanaan strategi pencegahan dan pengobatan serta pengendaliannya.
Penelitian dilakukan denga mengambil sampel feses 65 ekor kuda di berbagai kota di Jawa Timur yaitu Surabaya, Malang, Kediri dan Pasuruan. Selanjutnya sampel feses diolah dengan metode pengendapan dan pengapungan. Selanjutnya sampel diperiksa mikroskop dengan perbesaran 100x-400x untuk dilihat keberadaan telur cacing. Telur yang ditemukan dilihat morfologinya dan diukur menggunakan software optilab viewer dan image raster. Telur cacing Strongylids yang ditemukan mempunyai bentuk bulat/ellips dengan ukuran rata- rata 60-70µm x 50-60µm dengan terdapat larva di dalamnya.
Dari total 65 sampel feses yang diperiksa, tiga sampel positif yang berasal dari kota Surabaya dengan prevalensi 4,6%. Hasil ini lebih rendah jika dibandingkan dengan penelitian lain yang pernah dilaporkan. Penelitian di Kentucky Tengah didapatkan prevalensi Strongylids pada anak kuda Thoroughbred, dengan prevalensi rata-rata 28%. Prevalensi cacingan dapat diturunkan dengan memberikan obat cacing seperti thiabendazole.
Perkembangan cacing Strongylids dimulai dari perkembangan embrio yang memulai pembelahan blastomere untuk berubah menjadi larva hingga larva bergerak dan pada akhirnya larva terlepas dari telur. Terlepasnya larva 1 dari telur cacing dibutuhkan waktu selama 4 jam pada suhu 20- 30°C. Pada kuda yang terinfeksi umumnya tidak menunjukkan gejala klinis, tetapi pada anak kuda gejala yang sering adalah diare.
Penularan pada anak kuda bisa melalui air susu induknya dan L3 tertelan bersama makanan atau masuk melalui kulit. Infeksi endoparasit cacing atau helminthiasis dari hewan ternak memiliki angka kematian yang rendah, namun memiliki efek langsung pada produktivitas peternakan dan dampak zoonosis terhadap kesehatan Masyarakat. Kesehatan pada hewan ternak termasuk kuda perlu diperhatikan, karena berkaitan dengan tujuan pemeliharaan serta aspek resiko penularan penyakit dari hewan ke manusia atau bersifat zoonosis.
Penulis: Dr. Mufasirin, drh., M.Si., Sesa Puput, drh., M.Si., Prof. Dr. Lucia Tri Suwanti, drh., M.P., Prof. Muchammad Yunus, drh., M.Kes., Ph.D., Prof. Dr. Endang Suprihati, drh., M.S., Prof. Dr. Eduardus Bimo Aksono, drh., M.Kes., dan Heni Puspitasari, drh., M.Si.
Referensi pendukung dapat diakses melalui: https://e-journal.unair.ac.id/JMV/article/view/40949