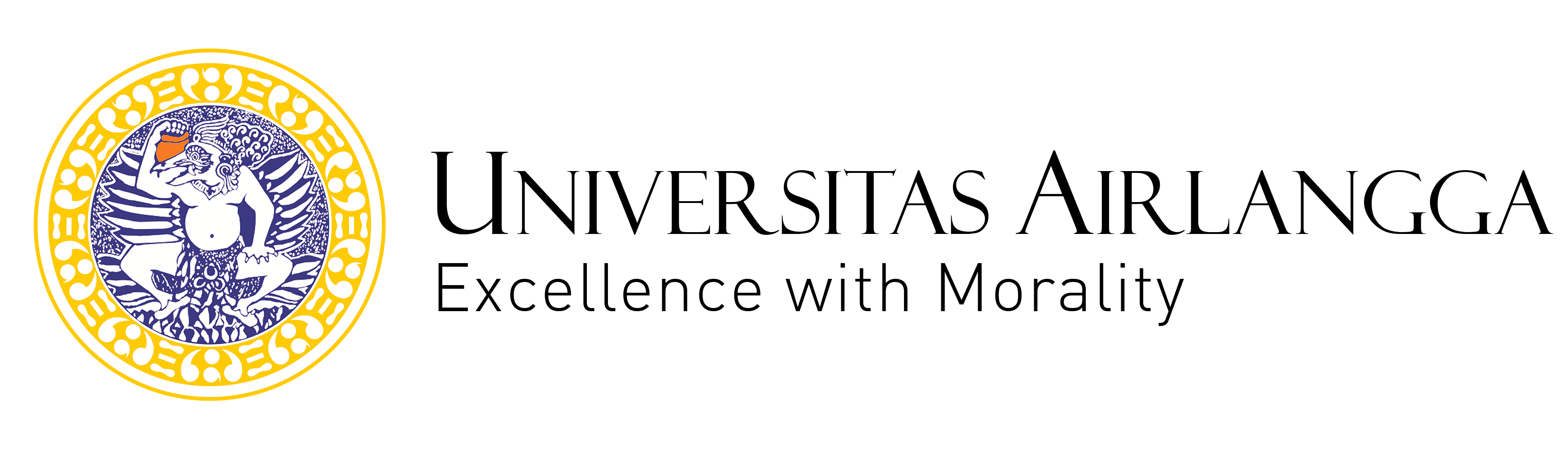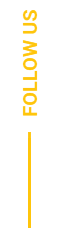Sepanjang tahun 2024, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan sipil menunjukkan kondisi yang melemah, atau setidaknya tidak banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya (tahun 2023). Hal ini tidak mengejutkan, karena selaras dengan melemahnya demokrasi dan hukum yang semakin memperkuat kepentingan politik kekuasaan, khususnya dalam konteks relasi kuasa oligarki. Berdasarkan catatan beberapa organisasi, terdapat 328 kasus dugaan serangan fisik dan digital terhadap kebebasan sipil dengan setidaknya 834 korban, yang terjadi antara Januari 2019 hingga Mei 2022.
Amnesty melaporkan bahwa sepanjang tahun 2023, terdapat 95 serangan terhadap para pembela hak asasi manusia, dengan jumlah korban mencapai 268 orang. Angka ini naik 63 persen dibandingkan tahun sebelumnya (168 korban) dan merupakan yang tertinggi sejak 2019. Dari total tersebut, 128 orang mengalami penangkapan, 96 orang menghadapi intimidasi fisik, dan 41 orang dikriminalisasi. Kelompok yang paling banyak menjadi sasaran pada tahun 2023 adalah aktivis Papua (103 orang), jurnalis (89 orang), petani (31 orang), dan masyarakat adat (24 orang).
Selama tahun 2023, pasal-pasal bermasalah dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tetap digunakan untuk membungkam kritik terhadap kekuasaan. Menurut catatan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), dari Januari hingga Oktober 2023, setidaknya ada 89 kasus kriminalisasi yang menggunakan pasal-pasal kontroversial dalam UU ITE. Kriminalisasi ini menjadi alat politik kekerasan baru melalui peradilan dan penahanan, yang menargetkan jurnalis, pelajar, mahasiswa, akademisi, dan pembela hak asasi manusia.

Selain itu, pada 5 Desember 2023, seluruh fraksi di DPR secara resmi mengesahkan revisi kedua UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam rapat paripurna ke-10 penutupan masa sidang II 2023-2024. Beberapa perubahan substansial dalam revisi kedua UU ITE ini antara lain Pasal 27 ayat (1) mengenai kesusilaan, ayat (3) tentang penghinaan atau pencemaran nama baik, dan ayat (4) mengenai pemerasan atau pengancaman yang merujuk pada KUHP. Selain itu, Pasal 28 ayat (1) tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, serta Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan serta tindakan yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, juga termasuk dalam revisi tersebut.
Masalahnya, pasal-pasal kontroversial yang selama ini mengancam kebebasan sipil warga negara masih diberlakukan. Padahal, publik mengharapkan adanya penghapusan atau perbaikan mendasar terhadap pasal-pasal ini, yang selama ini sering disalahgunakan, sehingga revisi yang dilakukan dapat menjamin keadilan bagi masyarakat.
Proses pembentukan hukum melalui revisi UU ITE ini terlihat tertutup dan dilakukan secara diam-diam, tanpa melibatkan partisipasi publik yang berarti (meaningful participation). Bahkan, hingga proses pengesahan, masyarakat sipil belum menerima salinan resmi rancangan revisi UU ITE. Pelibatannya sangat terbatas dan hanya bersifat prosedural.
Terdapat dua pasal yang sangat terkait dengan pembungkaman kebebasan sipil, yaitu pasal tentang pencemaran nama baik (cyber defamation) dan pasal tentang disinformasi serta misinformasi, yang sering digunakan secara keliru atau bahkan disalahgunakan oleh Negara.
Pembentukan hukum seperti ini tidaklah mengejutkan selama pemerintahan Jokowi Berkali-kali terlihat karakter pembentukan hukum yang otoriter, minim partisipasi, tidak teratur, dan bahkan melegitimasi aturan yang sering bertentangan dengan semangat konstitusionalisme hak asasi manusia maupun instrumen hukum hak asasi manusia internasional, terutama merujuk pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005).
Upaya untuk mengonsolidasikan pembentukan hukum juga tidak melibatkan institusi yang memiliki kapasitas kelembagaan negara, seperti Komnas HAM yang telah menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, serta lembaga-lembaga kajian kampus atau organisasi non-pemerintah yang bekerja secara mendalam terkait isu ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan parlemen kurang serius berupaya membentuk hukum yang melindungi kebebasan sipil warganya.
Dalam kondisi seperti ini, revisi UU ITE menjadi ancaman tersendiri bagi kebebasan warga negara dalam mengekspresikan pikiran dan pendapatnya, baik melalui forum akademik, media pers, maupun kritik melalui media sosial. Hal ini terjadi karena mekanisme hukum, khususnya peradilan, masih sangat dipengaruhi oleh politik kekuasaan. Ini dikenal sebagai “judicialization of authoritarian politics” yang mana politik peradilan sangat mencerminkan kepentingan politik kekuasaan.
Tahun 2023 ini memperlihatkan betapa mudahnya para pembela HAM dan para kritikus diseret ke ranah hukum, seperti kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, serta kasus yang melibatkan Rocky Gerung dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kasus-kasus tersebut seharusnya tidak terjadi jika institusi penegak hukum memahami bahwa kritik adalah hal biasa dalam negara hukum yang demokratis. Sayangnya, kritik dari para pembela HAM tentang ketidakadilan sosial dalam kasus pengerahan militer di Intan Jaya dan ketidakadilan sosial yang dihadapi buruh serta masyarakat adat karena Proyek Strategis Nasional (PSN), tidak lagi dianggap penting. Sebaliknya, pasal pencemaran nama baik terus disalahgunakan untuk membungkam mereka.
Kritik yang substansial dan berisiko tinggi sering kali berkaitan dengan ‘konsolidasi ekonomi politik oligarki’. Oleh karena itu, hukum sering kali menjadi alat kekuasaan, termasuk untuk represi. Karakter hukum yang mengancam kebebasan sipil ini sangat dipengaruhi oleh mekanisme hukum ketatanegaraan, yang tentu saja akan terus terkait dengan strategi politik oligarki.
Dalam penerapannya, hukum ini tidak hanya diskriminatif, tetapi juga cenderung mempertahankan impunitas, memfasilitasi kepentingan hukum kartelisasi politik, transaksi politik yang menjinakkan oposisi, serta secara sistematis mendukung korupsi dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, sekaligus bersifat represif.
Kekerasan dan ancaman terhadap kebebasan sipil diperkirakan akan terus meningkat menjelang Pelantikan Presiden 2024, termasuk setelah pelantikan. Mengapa hal ini sangat mungkin terjadi? Pertama, struktur kekuasaan masih didominasi oleh oligarki (embedded oligarch politics), yang berarti pemanfaatan hukum untuk mendukung kekuasaan dan relasi kuasa oligarki. Kedua, menguatnya “politik hukum pemanipulasian”, narasi dominan dengan kekuasaan pengetahuan (politics of deception), yang tidak hanya marak menjelang Pemilu, tetapi juga terus mereproduksi dirinya untuk mempertahankan rezim yang berkuasa.
Dalam situasi ini, jaminan kebebasan sipil bagi warga negara tidak akan berubah jika penyelenggara kekuasaan atau bahkan aktivisme masyarakat sipil hanya mengandalkan strategi teknokratisme dalam gerakan pembaruan Hukum dan HAM. Apalagi, jika upaya tersebut tenggelam atau setidaknya terfragmentasi dalam partisan politik dan terbatas pada arena programatik. Tantangan ke depan adalah sejauh mana ruang kebebasan sipil mampu memberikan alternatif atau narasi tandingan, dan sejauh mana basis gerakan kelas yang kuat mampu mempengaruhi dan mengendalikan berjalannya Negara Hukum yang demokratis.
Penulis: Nazhif Ali Murtadho (Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga)