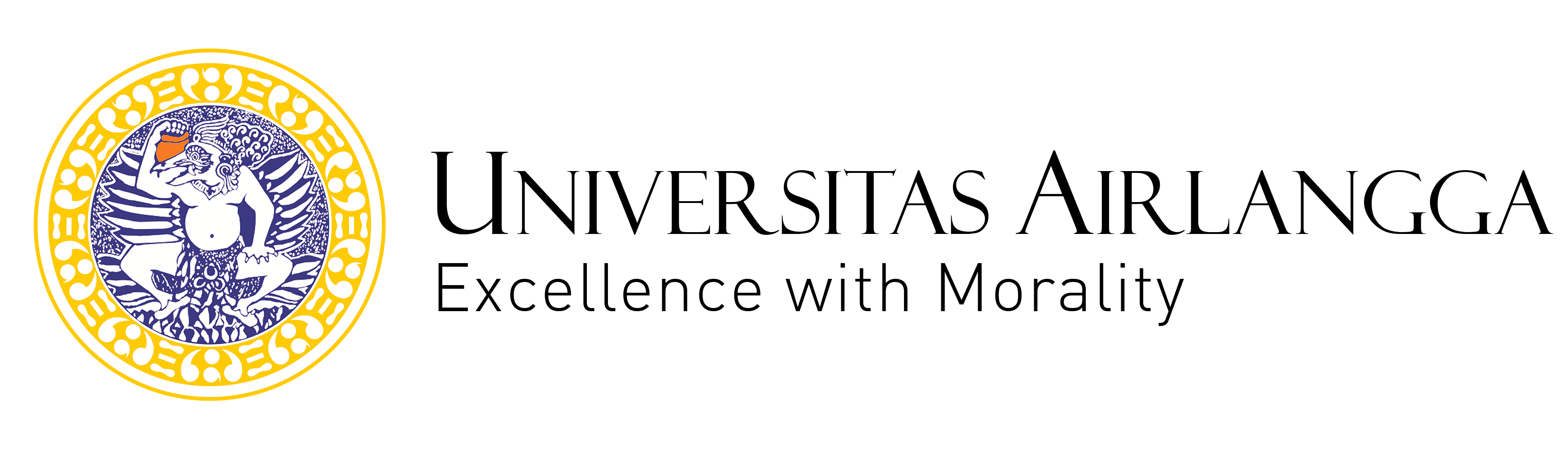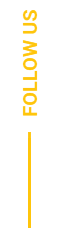Penyakit Tuberkulosis (TB) dan Corona Virus Disease (COVID-19) merupakan penyakit menular yang menginfeksi saluran pernafasan. Tuberkulosis disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis sedangkan COVID-19 disebabkan oleh SARS CoV-2. Penularan penyakit ini melalui batuk, bersin dan kontak erat dengan individu yang terinfeksi. Penyakit Tuberkulosis telah menjangkit di seluruh dunia dan dilaporkan Indonesia berada peringkat kedua di Dunia (543.874 kasus), sehingga, diperlukan perhatian serius oleh berbagai sektor untuk menekan penularan dan eliminasi penyakit ini. Saat Pandemi COVID-19 selama dua tahun terakhir terdapat indikasi adanya koinfeksi COVID-19 pada pasien tuberkulosis paru, hal ini disebabkan oleh risiko dan tingkat keparahan yang disebabkan oleh penyakit COVID-19 serta tingginya risiko kematian akibat perkembangan penyakit baru pada penderita TB.
Data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait dengan perkembangan kasus TB menunjukkan tren fluktuatif selama satu dekade terakhir. Pada tahun 2020, kejadian kasus TB di Indonesia meningkat menjadi 845.000 dengan mortalitas lebih dari 98.000 orang. Selanjutnya, tahun 2021 terjadi penurunan kasus mencapai 2,04% dari tahun sebelumnya sebanyak 393.323 kasus sebagai akibat perhatian pemerintah terfokus pada penurunan insiden COVID-19. Namun demikian, WHO menetapkan Indonesia sangat perlu untuk melakukan surveilans epidemiologi penyakit TB pada masa pandemi COVID-19, hal ini disebabkan oleh penurunan pemberitahuan TB bulanan dan triwulanan dan paruh pertama tahun 2021 secara substansial menurun dari tahun 2019 di sebagian besar negara dengan beban TB tertinggi. Dilaporkan, pengurangan relatif dalam notifikasi tahunan antara 2019 dan 2020 terlihat di Gabon (80%), Filipina (37%), Lesotho (35%), Indonesia (31%) dan India (25%) sehingga, jumlah riil dari kasus TB diperkirakan jauh lebih tinggi daripada yang ditemukan dan diobati serta penurunan pada tahun 2021 diduga banyak kasus yang tidak terlaporkan.
Memperhatikan update informasi yang dirilis oleh Organisasi Kesehatan Dunia, dilakukan surveilans epidemiologi berbasis data sekunder dengan memanfaatkan laporan data regional yang dirilis setiap tahunnya. Data yang digunakan yakni jumlah kasus terkonfirmasi positif TB dan COVID-19 yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur dan dibandingkan satu sama lain dengan faktor atau determinan lainnya. Pemetaan geografis persebaran kasus tuberkulosis dan COVID-19 juga dilakukan dengan menggunakan Quantum Geographic Information System (QGIS) untuk mengidentifikasi wilayah yang berpotensi memiliki tingkat risiko dan keparahan tertinggi dari kedua penyakit ini. Terdapat beberapa indikator yang ditinjau korelasi antar kedua penyakit ini meliputi: korelasi antara tingkat kejadian dan tingkat kematian kasus tuberkulosis dan COVID-19, hubungan antara angka kesembuhan kasus dan angka kematian kasus tuberkulosis, angka kejadian dan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis, korelasi antara tingkat keberhasilan pengobatan dan tingkat kematian kasus tuberkulosis, tingkat pemulihan kasus, dan tingkat kematian kasus COVID-19 serta perhitungan faktor geografis termasuk rasio puskesmas, jumlah dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli gizi, dan apoteker serta semua rasio dihitung per 100.000 penduduk.
Hasil penelitian diperoleh angka kejadian tuberkulosis di Provinsi Jawa Timur tahun 2020 sebesar 95,49/100.000 penduduk dengan angka kesembuhan kasus yang bervariasi. Kasus TB didominasi oleh masyarakat berjenis kelamin laki – laki. Jumlah perempuan di Jawa Timur tahun 2020 mencapai 20.374.104, sedangkan laki-laki mencapai 20.291.592. Penduduk dengan tuberkulosis yang didominasi oleh perempuan hanya ditemukan di kabupaten Probolinggo dengan jumlah perempuan (604) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (561). Selanjutnya, tingkat infeksi tertinggi ditemukan di Madiun (296,51/100.000 penduduk), sedangkan yang terendah di Malang (0,07/100.000 penduduk). Rasio insiden kasus tuberkulosis berdasarkan jenis kelamin diperoleh laki-laki (117,66/100.000 jiwa) lebih tinggi daripada perempuan (93.49/100.000 jiwa). Kabupaten dengan angka kejadian tuberkulosis pada laki-laki tertinggi adalah Madiun (342,62/100.000 penduduk) dan yang terendah terdapat di Pacitan (57,88/100.000 penduduk). Selanjutnya, pada jenis kelamin perempuan angka kejadian tuberkulosis tertinggi di Pasuruan (223,16/100.000 jiwa) dan terendah di Pacitan (93,49/100.000 jiwa). Berdasarkan temuan, angka kejadian infeksi COVID-19 tertinggi ditemukan di Mojokerto (789,9/100.000 penduduk), sedangkan terendah ditemukan di Sampang (52,5/100.000 penduduk). Analisis berdasarkan jenis kelamin diperoleh tingkat kejadian COVID-19 pada perempuan (210,74/100.000 penduduk) lebih tinggi daripada laki-laki (198,04/100.000 penduduk). Sedangkan Kabupaten dengan jumlah penduduk laki-laki tertinggi di Mojokerto (744,46/100.000 jiwa), sedangkan terendah di Sampang (48,58/100.000 jiwa). Kabupaten dengan angka kejadian COVID-19 pada perempuan tertinggi adalah Mojokerto (804,51/100.000 jiwa), sedangkan yang terendah terdapat di Madiun (51.14/100.000 jiwa). Angka kematian kasus tuberkulosis secara keseluruhan di Provinsi Jawa Timur di Indonesia adalah 3,6%. CFR infeksi TB tertinggi ditemukan di Probolinggo (7%), sedangkan terendah ditemukan di Surabaya (0,4%). Sementara itu, CFR infeksi COVID-19 tertinggi diperoleh di Pasuruan (11%), sedangkan terendah ditemukan di Tulungagung 2,1%. Selanjutnya, angka kesembuhan kasus tuberkulosis tertinggi terdapat di Magetan (96,6%), sedangkan terendah di Kota Batu (11,3%). Sementara itu, Case Recovery Rate COVID-19 didefinisikan sebagai pasien COVID-19 dengan hasil positif pada awal RT-PCR, dan hasil negatif pada akhir pemeriksaan. Angka kesembuhan kasus COVID-19 tertinggi terdapat di Sidoarjo (92,6%), sedangkan terendah ditemukan di Tuban (64,5%). Tingkat keberhasilan pengobatan tuberkulosis tertinggi terdapat di Magetan (95,97%), sedangkan terendah ditemukan di Bondowoso (65,89%). Perhitungan jumlah kasus COVID-19 berdasarkan kelompok umur diperoleh usia tertinggi di kisaran 46-59 tahun (23.947 individu), sedangkan terendah ditemukan pada usia 3-6 tahun (771 individu).
Pada studi tersebut, dilaporkan tidak ada hubungan yang bermakna antara angka kejadian dan angka kematian kasus tuberkulosis (p = 0,912, p>0,05). Ditemukan juga bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara angka kejadian dan angka kematian kasus untuk COVID-19 (p = 0,219, p >0,05), angka kesembuhan kasus dan angka kematian kasus tuberkulosis (p = 0,698, p >0,05), angka kejadian dan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (p = 0,795, p >0,05), angka keberhasilan pengobatan dan angka kematian kasus tuberkulosis (p = 0,659, p >0,05), dan case recovery rate dan case fatality rate untuk COVID-19 ( p = 0,164, p > 0,05). Perbedaan jumlah penderita tuberkulosis laki-laki dan perempuan (p = 0,202, p > 0,05) dan COVID-19 ( p = 0,942, p > 0,05) tidak signifikan. Perhitungan data geografis yang terdiri dari rasio jumlah puskesmas, dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli gizi dan apoteker, serta angka kejadian HIV di wilayah tersebut. Hasilnya, jumlah tenaga kesehatan per 100.000 penduduk berkorelasi bermakna dengan angka kejadian tuberkulosis ( p < 0,05). Variabel tersebut berkorelasi positif dengan angka kejadian tuberkulosis dan temuan selanjutnya tingkat kejadian HIV berkorelasi dengan tingkat kejadian TB ( p <0,05). Selanjutnya, angka kesembuhan kasus antara TB dan COVID-19 berbeda secara signifikan. Sedangkan pada aspek COVID-19, angka kejadian COVID-19 berkorelasi signifikan dengan angka kejadian HIV dan jumlah tenaga kesehatan (dokter, perawat, petugas kesehatan masyarakat, petugas kesehatan lingkungan, ahli gizi, dan apoteker). Temuan tersebut mengisyaratkan pemerintah dan sektor terkait untuk meningkatkan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis guna mencapai penurunan insiden, mortalitas dan penularan di masyarakat. Selain itu, diperlukan upaya terintegrasi dalam meningkatkan deteksi kasus tuberkulosis sejak dini untuk menekan penularan dan merealisasikan eliminasi TB tahun 2030.
Penulis: Dr. Budi Utomo, dr., M.Kes; Chow Khuen Chan, Ph.D., Prof. Dr. Ni Made Mertaniasih, dr., MS., Sp.MK(K); Dr. Soedarsono, dr., Sp.P(K)., Shifa Fauziyah, S.Si., M.Ked.Trop; Teguh Hari Sucipto, S.Si., M.Si; Febriana Aquaresta; M.Ked. Klin., Sp. MK; Dwinka Syafira Eljatin, dr; I Made Dwi Mertha Adnyana, S.Si., CMIE
Artikel dapat diakses pada link berikut: https://www.mdpi.com/2414-6366/7/6/83/htm