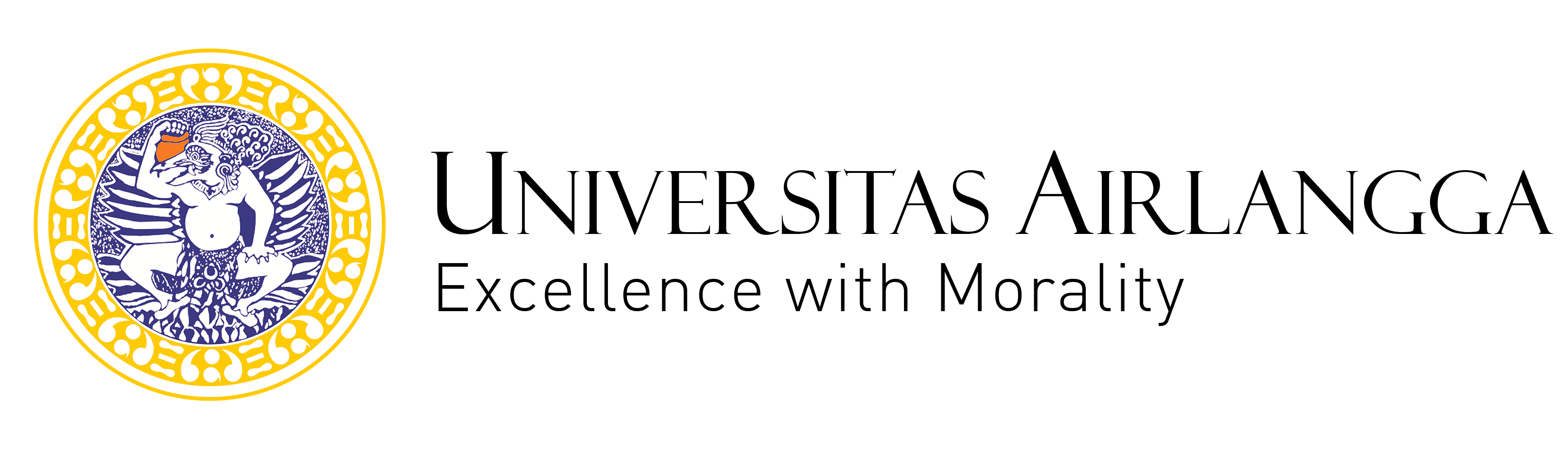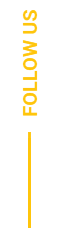Dalam era digitalisasi yang berkembang pesat, posisi Indonesia tampak berada di persimpangan antara kemajuan dan ketertinggalan. Masyarakat seolah-olah belum sepenuhnya siap untuk dipaksa bergerak lebih cepat dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di berbagai bidang. Hal ini terutama terlihat dalam ranah media dan komunikasi, yang pada era digital kini bukan hanya menjadi kebutuhan esensial, tetapi juga aspek krusial yang menentukan arah perkembangan sosial. Berbagai pertanyaan penting pun muncul: ke mana arah masyarakat Indonesia akan bergerak? Apakah benar masyarakat kita tertinggal? Dan sejauh mana keterlambatan dalam merespons mobilitas digital yang begitu cepat ini dapat memengaruhi kualitas nilai-nilai demokrasi yang telah dibangun?
Dilansir dari laman VOA Indonesia, Microsoft perusahaan teknologi komputer terkemuka dunia telah mempublikasikan “Indeks Keberadaban Digital” atau “Digital Civility Index”. Berdasarkan infografis pada laporan yang telah dirilis tersebut, dari survei yang diadakan di 32 negara, Indonesia berada di peringkat 29 sekaligus menempati peringkat terbawah di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Microsoft kemudian menghadiahi julukan kepada pengguna internet Indonesia sebagai “Netizen yang Paling Tidak Sopan Se-Asia Tenggara”. Tidak lama berselang, akun Instagram milik Microsoft dibanjiri komentar negatif dari netizen Indonesia yang mengakibatkan pihak Microsoft harus mematikan kolom komentar akun mereka pada saat itu.
Berdasarkan kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia secara normatif masih belum sepenuhnya siap menghadapi perubahan signifikan dalam bidang media dan komunikasi. Kondisi ini memunculkan berbagai problematika demokrasi yang bersifat dilematis. Secara sekilas, praktik berdemokrasi di ruang virtual tampak lebih mudah karena sifatnya yang bebas, cepat, dan egaliter. Tidak mengherankan jika sejak masa pandemi, banyak masyarakat beralih ke ranah digital, di mana memperjuangkan demokrasi seakan dapat dilakukan hanya dengan menggerakkan jari. Kemajuan teknologi komunikasi dan kemudahan akses terhadap media informasi semakin memfasilitasi penyampaian aspirasi maupun advokasi, yang kemudian dapat dengan cepat dipublikasikan ke ruang publik.
Mulanya terlihat seperti perayaan kedaulatan penuh rakyat. Seperti selebrasi akan hak-hak bernegara yang dulu pernah dilucuti. Seperti bentuk syukur dan pemanfaatan penuh dari segala kemajuan yang terjadi. Akan tetapi intensitas serta mobilitasnya yang semakin sulit dikendalikan kini perlahan-lahan menggores cacat. Sebab era digital membuat celah-celah dalam demokrasi kini terlihat semakin menggoda untuk disusupi.
Bertahun-tahun sebelum pandemi maupun sesudah pandemi, pencorengan nilai-nilai demokrasi yang disebabkan oleh penggunaan internet sudah memiliki daftar tersendiri. Contohnya seperti berita-berita bohong (hoax) yang umumnya meningkat setiap diadakannya pesta demokrasi. Temuan Kemenkominfo pada tahun 2019 menyatakan bahwa hoax paling banyak tersebar di bulan April yang dari 486 hoax tersebut, 209 merupakan hoax politik dengan target yang menyerang Capres-Cawapres, KPU, Bawaslu, serta partai politik dan Pemilu. Menilik kompas.com, hal ini juga terjadi pada tahun 2024 yang dimana Kemenkominfo menemukan sebanyak 3.144 konten hoaks tentang pemilu yang terjadi pada bulan Februari.
Alhasil sampai saat ini hoax dan sisa-sisa gesekan politik dari Pemilu 2019 sampai Pemilu 2024 menciptakan masyarakat demokratis yang sayangnya terpolarisasi. Hal ini diperburuk dengan mudahnya berbagai macam ideologi untuk berpenetrasi, baik itu yang kooperatif maupun radikal. Masyarakat yang ber-bhinneka akhirnya terkotak-kotakkan terkait preferensi dalam berdemokrasi. Sebuah hal yang ironis karena pada dasarnya demokrasi dimaksudkan untuk menyatukan segala lapisan masyarakat agar berjuang bersama melawan otoritarianisme dan diktatorisme. Seperti intisari pidato final Charlie Chaplin dalam film hitam putih gubahannya, The Great Dictator, pada tahun 1940 yang menavigasi demokrasi demi persatuan melawan gerusan Perang Dunia Kedua dan tercapainya solidaritas untuk perdamaian dunia.
Seperti antitesis, demokrasi kini diperalat untuk memecah belah masyarakat. Kesembronoan berbagai macam pihak dalam menggiring opini seperti menambah cacat yang sudah lebih dulu digoreskan oleh pemerintahan kita yang digerayangi oligarki dan politik dinasti. Dewasa ini, di tengah kemajuan media informasi, masyarakat seperti diantarkan menuju perang argumentasi. Saling sikut tidak hanya terjadi antar fraksi ataupun antara oposisi dengan afirmasi, tetapi juga deretan simpatisan fanatik yang tak segan memamerkan anarki.
Terlihat seperti pil pahit untuk ditelan, karena nyatanya kita sebagai masyarakat justru berperan menjadi katalisator kehancuran. Kebrutalan dalam mengedepankan ego dan kepentingan kini menyeret alur demokrasi kita ke jurang kemunduran yang lebih dalam. Sejarah yang seharusnya dijadikan pelajaran malah dinomorsekian-kan demi tercapainya kepentingan. Kemajuan dan kemudahan di era digital seperti disia-siakan. Demokrasi itu sendiri pun seperti disia-siakan keasliannya. Dipoles dan dimanipulasi sedemikian rupa menyesuaikan nafsu dan kebutuhan semata.
Mungkin memang benar kalau pola pikir masyarakat kita sangat prematur untuk dihadapkan pada era digital sehingga ketertinggalan yang harus dikejar menjadi perjalanan panjang dengan PR yang tidak ada habisnya. Walaupun tidak dapat dipungkiri, merosotnya akuntabilitas pemangku kekuasaan serta kurangnya transparansi dalam tiap penetapan keputusan agaknya juga berperan besar dalam mencederai nilai dan prasarat demokrasi.
Pada akhirnya, keputusan untuk bersikap akan dikembalikan kepada hati nurani dan akal sehat pribadi. Selalu ada opsi untuk berempati. Selalu ada jalan untuk mencegah diri akan sikap terlena dengan kemajuan teknologi. Juga yang paling pasti, selalu ada pilihan untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam berekspresi agar substansi demokrasi tidak sepenuhnya mati.
Penulis: Abdul Hayyi (Mahasiswa Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga)