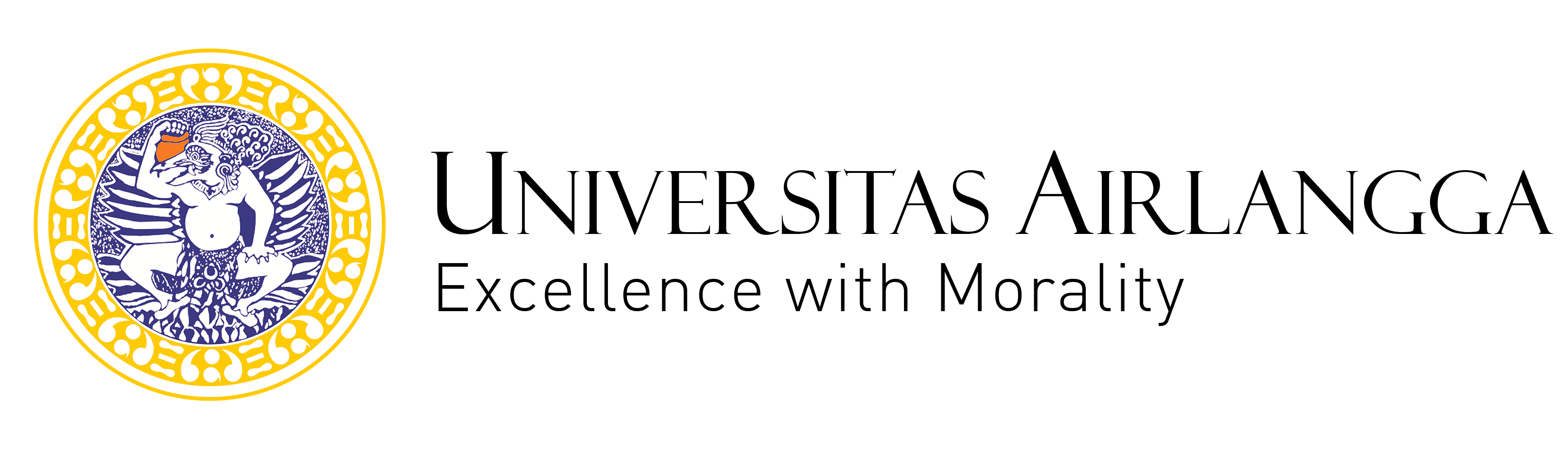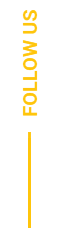Invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai di 24 Februari 2022 telah menjadi perbincangan utama bagi masyarakat dunia selama satu tahun ke belakang. Di banyak penjuru dunia, bermunculan tokoh, institusi, partai, maupun kelompok yang membenarkan dan menormalisasi tindakan Rusia (dan Presidennya, Vladimir Putin), serta menganggap apa yang dilakukan Rusia adalah hal yang wajar dan normal.
Dalam tulisan terbarunya, Radityo Dharmaputra, bersama dengan beberapa partner seperti Andrey Makarychev dan Aliaksei Kazharski, menelaah berbagai wacana yang menormalkan logika perang Putin melawan Ukraina. Beberapa mungkin hanya mengulang propaganda Rusia, sementara yang lain disesuaikan konteks nasional masing-masing negara. Yang menarik bagi pembaca adalah kerangka komparatif yang memberi landasan bagi perspektif Eropa dan non-Eropa pada topik yang beresonansi dan berkomunikasi satu sama lain.
Analisis wacana ini patut mendapat perhatian karena dua alasan utama. Pertama, mereka mencerminkan cara pandang tertentu, mulai dari penekanan realisme struktural dengan menyalahkan Barat akan ekspansi keanggotaan NATO. Banyak argumen Westsplainers yang mengklaim bahwa Ukraina, bersama dengan negara lain di Eropa Timur dan Tengah, harus menemukan opsi yang mengakomodasi dan menghindari eskalasi dalam hubungan dengan Rusia. Argumen ini dengan kuat dibantah oleh para sarjana yang berpegang pada prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan tidak melihat alasan untuk memberi justifikasi kepada aggressor seperti Rusia.
Kedua, wacana yang menormalkan dan merasionalisasi kebijakan luar negeri Rusia menjadi dasar untuk melegitimasi berbagai opsi kebijakan, termasuk gencatan senjata tanpa syarat, perdamaian dengan harga berapa pun, dan pemaksaan bagi Ukraina untuk menerima kerugian territorial serta menyerahkan sebagian wilayahnya demi “perdamaian”. Logika akademik dan politik saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Di Eropa, perpaduan narasi ini menyebabkan perpecahan di antara mereka yang percaya bahwa Putin seharusnya dibiarkan untuk menyelamatkan harga dirinya di Ukraina, dan mereka yang bersikeras bahwa Rusia harus menghadapi kekalahan yang memalukan di medan perang. Dilema ini diterjemahkan ke dalam perpecahan lain – seperti, misalnya, antara mereka yang skeptis tentang keanggotaan Ukraina di NATO, di satu sisi, dan pendukung integrasi Ukraina dengan Euro-Atlantik di sisi lain.
Perang di Ukraina merupakan pukulan telak bagi banyak simpatisan Rusia di Eropa. Banyak kelompok tersebut menemukan diri mereka dalam posisi canggung karena mengasosiasikan diri dengan Kremlin dianggap pilihan yang salah oleh mayoritas publik. Namun, di Global South, para “pemaham Putin” di level lokal mampu mengarahkan pilihan politik dan preferensi pemerintah yang berkuasa untuk menjadi lebih pro-Rusia. Walaupun begitu, tidak semua negara non-Barat bisa dianggap bersimpati terhadap Putin. Jepang, Taiwan, dan Singapura menunjukkan bahwa di beberapa negara, narasi dominan justru jauh dari kecenderungan pro-Rusia.
Ada dua kesimpulan penting dari studi kasus non-Barat. Pertama, dua perspektif menyatu dalam konteks Asia: pasca-kolonial (Indonesia sebagai contoh negara poskolonial) dan dekolonial (Rusia dianggap sebagai negara yang tadinya negara kolonial). Apa yang paling penting adalah bagaimana tepatnya paradigma poskolonial dipahami di negara-negara Global South, dan apa yang mencegah mereka memperluas paradigma ini menjadi dukungan eksplisit untuk Ukraina, yang sedang berjuang melawan imperialisme bekas kekuatan kolonialnya (Rusia). Khusus untuk Indonesia, narasi pro-Rusia cukup tersebar luas negara ini, namun sebagai tuan rumah KTT G20 2022 presiden Joko Widodo justru mengundang dan memberikan kesempatan kepada presiden Zelenskiy untuk berpidato.
Kedua, beberapa pemimpin negara non-Euro-Atlantik sedang mencari rumusan yang tepat dari strategi penyeimbangan mereka, mengacu pada konsep keseimbangan, netralitas dan ketidakberpihakan sebagai poin utama dari sikap mereka terhadap perang Rusia di Ukraina. Selain itu, mereka mungkin akan menggunakan konsep lain seperti equidistance, multilateralisme, dan mungkin versi baru dari Gerakan Non-Blok. Perbedaan ini menarik, terutama di negara-negara yang sangat terpengaruh oleh agresi Rusia terhadap Ukraina, namun karena berbagai alasan enggan memihak dalam pertempuran antara agresor dan korbannya. Keragu-raguan posisi ini, yang sangat diapresiasi oleh Rusia dengan propaganda konsep multipolaritas, justru menimbulkan pertanyaan: jika multipolaritas membutuhkan invasi dan banyak korban, seberapa menarik lantas konsep ini bagi masyarakat internasional?
Penulis: Andrey Makarychev, Yulia Kurnyshova, Stefano Braghiroli, Aliaksei Kazharski, Sanshiro Hosaka, Radityo Dharmaputra, dan Clarissa Tabosa.
Informasi detail dapat dilihat pada tulisan di: