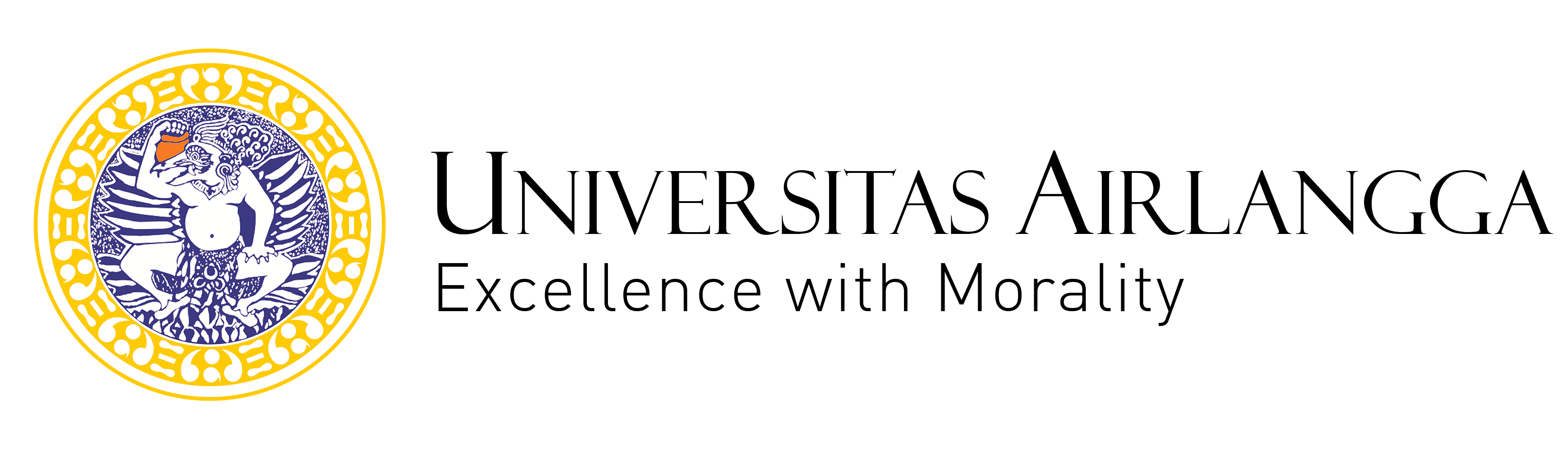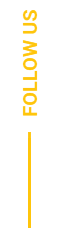Bayangkan pagi itu dunia berjalan seperti biasa. Anak-anak berangkat sekolah, orang dewasa menuju kantor, pedagang menata lapaknya. Lalu dalam hitungan detik, semuanya berubah—ledakan, teriakan, debu yang menutup pandangan. Pada 19 Agustus 2003, ledakan bom mengguncang Kantor PBB di Baghdad, Irak, merenggut nyawa 22 pekerja kemanusiaan, termasuk Sérgio Vieira de Mello, seorang diplomat yang telah mengabdikan hidupnya di medan bencana dan konflik. Tragedi itu menjadi titik balik.
Enam tahun kemudian, Majelis Umum PBB menetapkan 19 Agustus sebagai Hari Kemanusiaan Sedunia, bukan sekadar untuk mengenang, tapi untuk mengingatkan bahwa di balik setiap krisis, ada orang-orang yang memilih melangkah masuk ke pusat bahaya demi menyelamatkan nyawa yang bukan miliknya. Tahun 2025, peringatan ini mengusung tema “Strengthening Global Solidarity and Empowering Local Communities” — sebuah seruan yang terasa relevan di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, penuh ketidakpastian, dan sering kali memilih diam saat kemanusiaan dipertaruhkan.
Namun mari kita jujur, solidaritas global sering kali terdengar megah di forum internasional, tapi rapuh di lapangan. Menurut Global Humanitarian Overview 2025, kebutuhan dana kemanusiaan dunia mencapai 46 miliar dolar AS, tapi hingga pertengahan tahun ini, hanya sekitar 15,9 persen yang terpenuhi. Itu artinya, di saat konflik meningkat di Gaza, Sudan, Myanmar, dan belasan wilayah lain, bantuan yang datang seperti setetes air di padang pasir. Di Haiti, yang kini terjerat kekerasan geng dan krisis pangan, permintaan bantuan sebesar 900 juta dolar AS baru terpenuhi 9,2 persen. Di Afrika Timur, jutaan orang menghadapi risiko kelaparan ekstrem, sementara stok pangan darurat dipangkas karena kurangnya dana. Bahkan Program Pangan Dunia (WFP) terpaksa memangkas jangkauan bantuannya dari target 123 juta orang menjadi hanya sekitar 98 juta. Angka-angka ini bukan sekadar statistik; ini adalah wajah anak yang perutnya kosong, keluarga yang malamnya tanpa lampu, dan pasien yang tak sempat mendapat perawatan.
Yang ironis, pekerja kemanusiaan—terutama yang berasal dari komunitas lokal—menanggung risiko terbesar. Data menunjukkan, 98 persen pekerja kemanusiaan yang menjadi korban serangan adalah staf lokal. Mereka bukan datang dengan pesawat charter atau rombongan media, mereka ada di sana bahkan sebelum bencana diakui dunia. Mereka yang pertama tiba di lokasi, dan seringkali, yang terakhir pergi. Tapi penghargaan untuk mereka masih minim. Dana kemanusiaan global yang dijanjikan lewat kesepakatan Grand Bargain 2016 seharusnya mengalir 25 persen langsung ke organisasi lokal, nyatanya hingga kini angkanya bahkan belum menyentuh 5 persen. Akibatnya, organisasi lokal yang paling paham konteks budaya dan kebutuhan warganya, justru harus menunggu “restu” dan aliran dana dari lembaga besar yang berkantor ribuan kilometer jauhnya.
Memberdayakan komunitas lokal bukan hanya soal keadilan, tapi strategi cerdas. Bukti menunjukkan, bantuan yang dikelola langsung oleh aktor lokal lebih cepat sampai, lebih tepat sasaran, dan lebih murah biayanya. Contohnya, saat banjir besar melanda Pakistan pada 2022, jaringan relawan lokal mampu menjangkau desa-desa terpencil dalam waktu kurang dari 24 jam, sementara bantuan internasional baru tiba beberapa hari kemudian. Tapi untuk memperkuat kapasitas lokal, dibutuhkan investasi yang konsisten: pelatihan tanggap darurat, sistem peringatan dini, infrastruktur yang tangguh, dan—yang sering dilupakan—dukungan psikososial bagi para pekerja kemanusiaan agar mereka tidak patah di tengah jalan.
Tantangan kemanusiaan 2025 tidak berdiri sendiri. Perubahan iklim memicu bencana alam yang lebih sering dan lebih parah, konflik bersenjata memaksa jutaan orang mengungsi, ketimpangan ekonomi memperlebar jurang kemiskinan, dan disinformasi di media sosial membuat korban bencana kadang justru jadi sasaran kebencian. Dalam lanskap ini, solidaritas global bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan mendesak. Namun solidaritas itu harus bertemu dengan realitas: tanpa mendengar dan mempercayai suara lokal, bantuan akan kehilangan arah.
Pertanyaannya, dimana kita berdiri? Apakah kemanusiaan hanya berhenti di layar ponsel saat kita menekan tombol “share” berita bencana, atau diucapkan lewat caption penuh empati di Instagram? Atau kita mau melangkah lebih jauh, bahkan dalam skala kecil? Kemanusiaan tidak selalu berarti terjun ke zona perang. Ia bisa dimulai dari hal sederhana: menyisihkan sebagian penghasilan untuk membantu korban bencana, menjadi relawan di dapur umum saat banjir melanda kota kita, mendukung UMKM dari daerah terdampak, atau bahkan sekadar mendengarkan cerita pengungsi tanpa menghakimi.
Tanggal 19 Agustus seharusnya tidak menjadi satu-satunya hari kita peduli. Jika kemanusiaan hanya hidup di tanggal peringatannya, maka ia mati di sisa 364 hari lainnya. Justru di hari biasa, di saat tak ada sorotan, kemanusiaan diuji. Apakah kita tetap membantu ketika tidak ada yang melihat? Apakah kita tetap peduli saat tidak ada label “donatur” yang disematkan pada nama kita? Di sinilah perbedaan antara solidaritas seremonial dan solidaritas sejati. Tentu saja, tanggung jawab terbesar ada pada pemerintah dan lembaga internasional. Mereka punya sumber daya dan mandat untuk membuat sistem kemanusiaan yang adil, transparan, dan responsif. Tapi kita juga punya peran, sekecil apapun. Karena pada akhirnya, kemanusiaan adalah tentang rantai tindakan—dan setiap mata rantai, sekecil apapun, menentukan kekuatan keseluruhan. Mengabaikan satu artinya melemahkan semua.
Maka di Hari Kemanusiaan Sedunia 2025 ini, mari kita berhenti melihat kemanusiaan sebagai sesuatu yang jauh, eksklusif, atau “tugas orang lain.” Mari kita melihatnya seperti udara—tak kasat mata, tapi vital, dan hanya terasa saat mulai hilang. Kita tidak harus menjadi Sérgio Vieira de Mello untuk punya dampak; kita hanya perlu keberanian untuk tidak menutup mata. Karena di dunia yang kian bising, kadang yang paling dibutuhkan adalah mereka yang mau mendengar.
Kemanusiaan bukanlah proyek sekali jadi, melainkan proses tanpa akhir. Ia akan terus menuntut kita untuk memilih: menjadi penonton yang nyaman di tribun, atau pemain yang turun langsung ke lapangan, meski kaki kita akan kotor dan baju kita akan basah. Dan jika kita memilih untuk terlibat, mungkin kita tidak akan selalu bisa mengubah seluruh dunia, tapi kita bisa mengubah dunia seseorang. Dan itu, sesungguhnya, sudah cukup untuk membuat kemanusiaan tetap hidup.