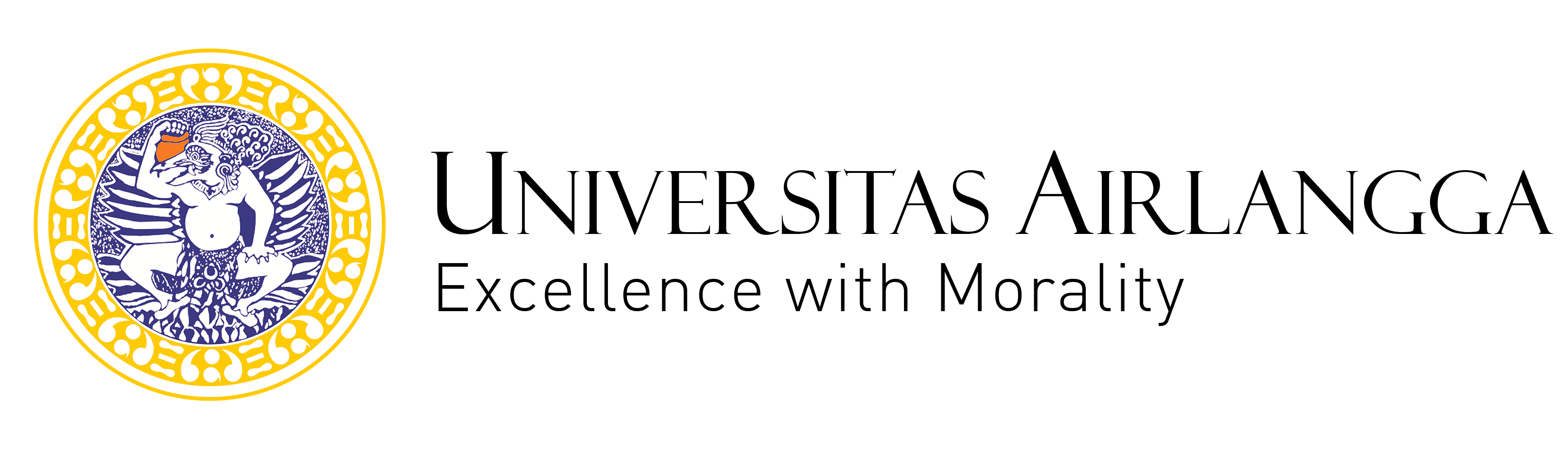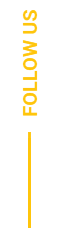Salah satu tantangan serius kualitas sumber daya manusia (SDM) terkait kesehatan ibu di Indonesia adalah masih tingginya angka kematian ibu (AKI) karena kehamilan dan persalinan. Berdasarkan data BPS hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 menurut Provinsi tahun 2020, di Indonesia (catatan, data diperbarui hingga Juli 2023) AKI di Indonesia adalah setinggi 173 untuk setiap 100.000 kelahiran hidup. Data UNICEF menyebutkan bahwa peringkat AKI di Indonesia menduduki peringkat ke-3 di wilayah ASEAN, di bawah Singapura (7), Malaysia (21), Thailand (29), Brunei Darussalam (44), Philipina (78), Vietnam (124). Adapun negara dengan AKI di bawah Indonesia adalah Myanmar (179), dan Timor Leste (204).
Bahkan jumlah kematian ibu di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4.005, selanjutnya tahun 2023 meningkat menjadi 4.129, melansir CNN Indonesia. Tentu kondisi ini menjadi beban Indonesia di tengah berjuang untuk menurunkan angka kematian ibu yang merupakan salah satu tujuan dari SDGs (Goals ketiga, yakni “Kehidupan Sehat dan Sejahtera”.
Di dalam negeri, AKI tinggi lebih banyak terdapat di wilayah Indonesia Bagian Timur, seperti provinsi-provinsi di Papua, NTT, NTB, Maluku dan Maluku Utara. Tercatat hanya dua provinsi yakni Bali (85), DI Yogjakarta (58), dan DKI Jakarta (48). Adapun provinsi-provinsi di Jawa, Sumatra, dan sebagian di Kalimantan diantara 127 hingga 274, menurut data BPS.
Dalam banyak studi disebutkan bahwa tingginya AKI lebih banyak disebabkan oleh keterlambatan dalam menegakkan diagnosis. Hal ini juga diperparah oleh jarak dan ketidakmerataan infrastruktur fisik yang mempersulit ibu hamil untuk mendapatkan perawatan tepat waktu, terutama dalam situasi darurat. Faktor ekonomi dan demografi seperti problem kemiskinan dan menikah terlalu muda juga dituding menjadi salah satu pemicu tingginya AKI di Indonesia.
Dalam konteks demografi, menikah terlalu muda atau dikenal dengan pernikahan anak berkaitan dengan usia nikah pertama kali. Usia nikah pertama (UNP) mengindikasikan saat seseorang (terutama perempuan) memasuki masa reproduksi. UNP yang rendah berpengaruh terhadap tingkat fertilitas individu maupun bangsa. Semakin muda UNP semakin panjang masa reproduksinya. Kondisi ini berpengaruh terhadap tingginya tingkat fertilitas yang selanjutnya berdampak negatif terhadap tingkat kesejahteraannya bangsa/pertumbuhan ekonomi (Sah dan Valeriani, 2024; Bloom dkk, 2009).
Kondisi ekonomi keluarga tidak jarang menjadi faktor pemicu kasus pernikahan anak. Kemiskinan keluarga menjadi salah satu penyebab orangtua segera menikahkan anak. Orang tua beranggapan, anak perempuan merupakan beban ekonomi, sehingga mempercepat pernikahan adalah upaya untuk mempertahankan ekonomi keluarga. Harapan keluarga, dengan menikahkan anak usia sedini mungkin akan memindahkan beban ekonomi kepada calon suami anaknya.
Di samping itu, faktor ekonomi, sosial-budaya-agama, gencarnya media sosial, dan keterbatasan prasarana pendidikan mempengaruhi tingginya pernikahan anak khususnya anak perempuan di pedesaan. Orang tua takut anak dikatakan perawan tua. Di beberapa wilayah masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan, di mana anak sejak kecil telah melalui perjodohan “calon” suaminya yang masih tergolong anak pula. Mereka segera dinikahkan sesaat setelah “aqil baligh” pada sekitar umur 12-13 tahun bahkan kurang. Umur tersebut jauh di bawah batas usia minimal yang menjadi syarat, yakni 19 tahun seperti yang ada dalam UU Nomor 16 Tahun 2019.
Bila pernikahan anak menjadi salah satu pemicu tingginya angka kematian ibu (AKI) sekaligus angka kematian bayi (AKB), maka di dalam “Peta Jalan SDGs Indonesia 2030”, percepatan penurunan AKI dan AKB telah ditetapkan menjadi target dalam capaian SDGs. Implementasi ini dipertegas dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Solusi Strategis
Memperhatikan kondisi kinerja AKI di Indonesia sebagai bagian dari pembangunan Kesehatan Ibu dan Anak belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, maka perlu solusi strategis dalam rangka percepatan penurunan AKI sebagai bagian dari pencapaian SDGs di Indonesia sebagai berikut: (i) Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana promosi digital melalui kecerdasan buatan dengan konten animatif. Langkah ini merupakan strategi advokasi peningkatan edukasi bagi ibu muda dan Gen Z di wilayah kantung kemiskinan terkait dengan pendewasaan usia pernikahan.
(ii) Pemanfaatan media sosial dengan konten yang bertemakan pembangunan keluarga, kesehatan reproduksi remaja, dan kesehatan gender diyakini akan dapat meningkatkan pendewasaan usia nikah serta membuka kesempatan untuk berpartisipasi dalam pasar kerja sekaligus kemandirian bagi kaum perempuan itu sendiri.
(iii) Penajaman Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai perwujudan dan implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) dalam menurunkan AKI, karena daerah merupakan ujung tombak penurunan AKI di wilayah tertinggal, terdapan, dan terluar yang kurang tersentuh layanan kesehatan.
(iv) Meningkatkan fungsi kelambagaan Kantor Urusan Agama (KUA) yang selama ini lebih dari urusan administratif. Memberikan peran lebih proaktif dan pendampingan dalam melayani masyarakat terkait dengan pembangunan keluarga dalam arti luas.
(v) Pelibatan Toga-Toma, yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mengadvokasi pentingnya pendewasaan usia pernikahan di atas 21 tahun sangat perlu. Terutama di wilayah pedesaan, pesisir, dan terisolisasi sebagai kantung kemiskinan. Penggalangan remaja influencer sebagai konselor “teman sebaya” dalam meningkatkan Lifeskill (pemberdayaan ekonomi) remaja terutama pada komunitas informal.
Pendewasaan usia pernikahan melalui jalur edukasi yang akan berdampak terhadap penurunan angka pernikahan anak dan muaranya penurunan AKI. Indikator AKI dan AKB dalam konteks global dewasa ini sangat penting bagi reputasi negara Indonesia dalam pencapaian tujuan pembangunan global berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) yang UNDP-PBB dan telah diratifikasi oleh 193 negara.
Penulis: Sjafii Achmad, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR