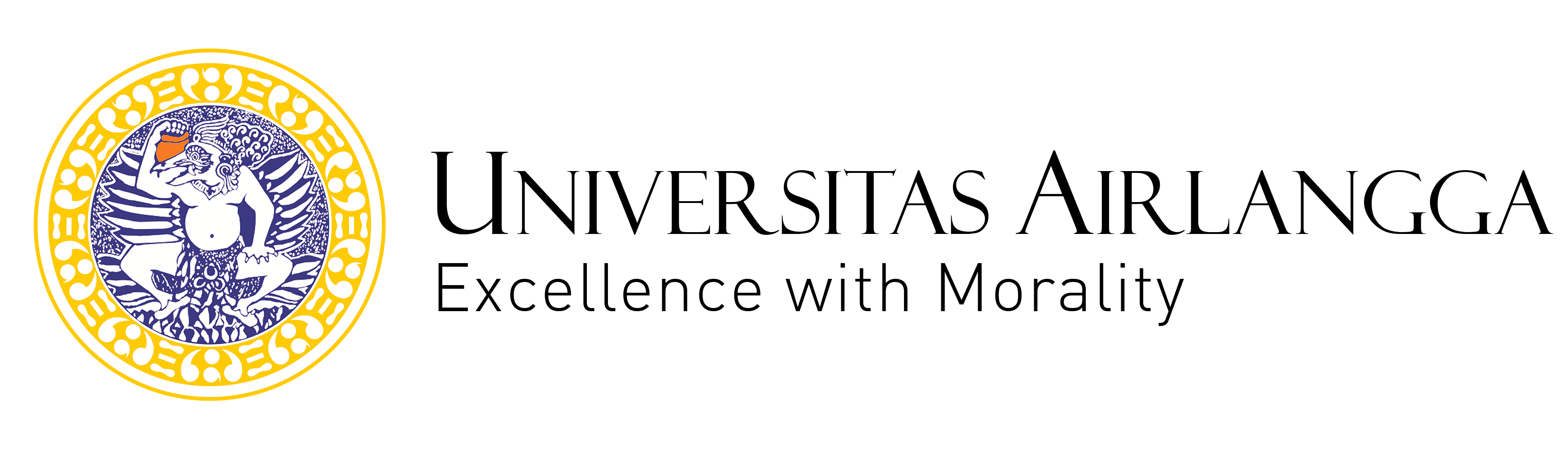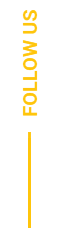Membicarakan soal pangan selalu menjadi perbincangan yang menarik. Sebab, hal itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia yang utama untuk melanjutkan hidup. Makan menjadi kebutuhan dasar yang mutlak dipenuhi. Karena bagaimanapun, sistem organ kita akan bekerja normal, apabila telah dimasuki nutrisi dari makanan.
Di tahun 2019, saya pernah menulis terkait bab pangan. Saya tulis di Media besutan Farid Gaban, Geotimes, dengan judul “Lahan Menyempit, Petani Sedikit, Mau Makan Apa?”. Waktu itu, saya mencoba menjelaskan bagaimana Thomas Malthus (1766-1834) membuat teori tentang pangan. Ringkasnya, Malthus menyatakan jika peningkatan produksi pangan, mengikuti deret hitung dan pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur. Yang artinya, manusia di masa depan akan mengalami ancaman kekurangan pangan, karena penduduk semakin bertambah, sedang jumlah pangan semakin berkurang.
Bertahun-tahun kemudian, pasca Perang Dunia 2. Teori dari Malthus ini digunakan oleh Lembaga ‘Taipan’ Ford Foundation dan Rockefeller Foundation untuk melakukan penelitian lanjutan. Hasilnya, lewat seorang Agronomis bernama Norman Ernest Borlaug, dicetuskanlah apa yang disebut dengan Revolusi Hijau. Revolusi itu dimaknai sebagai upaya atau cikal bakal kemajuan teknologi pertanian untuk peningkatan produktivitas hasil pangan. Ditebarkanlah bibit-bibit investasi dan program ini ke negara-negara berkembang. Diawali dengan penanaman gandum di Meksiko (1950), dan pemuliaan Padi di Filipina (1960), sampai masuk ke Indonesia masa Orde Baru.
Orde Baru menurunkan kebijakan Revolusi Hijau dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Tujuan utama Revolusi Hijau masa Orde Baru adalah pemenuhan pasokan pangan untuk swasembada beras pada tahun 1984. Dengan berbagai upaya seperti Intensifikasi dan Ekstensifikasi pertanian, Orde Baru menggalakkan pertanian yang lebih modern – dengan mencerabut sistem tradisional – di masyarakat. Secara luas, masyarakat ditekankan untuk menanam padi dengan bibit subsidi dari pemerintah, dan penggunaan pestisida secara massal. Benar saja, hasilnya di tahun 1984 Indonesia dinyatakan swasembada pangan (beras) atas kebijakan Revolusi Hijau Orde Baru.
Jika dikaji, keberhasilan itu tak ubahnya swasembada semu. Pemenuhan kebutuhan pangan nasional hanya bertahan beberapa tahun dan malah meninggalkan lubang besar setelahnya. Masyarakat sangat tergantung dengan beras dan petani begitu tergantung dengan penggunaan pestisida. Bahkan, hingga kini, Pupuk seperti Urea, NPK, dan Za sangat diperlukan mayoritas petani. Padahal, dahulu masyarakat masih menggunakan sistem tradisional yang lebih ramah lingkungan.
Saat ini, setelah saya terlibat dalam dunia swadaya masyarakat (LSM). Saya mendapatkan inside baru mengenai gagasan yang saya tulis tahun 2019. Ada antitesis berupa solusi untuk mengantisipasi ancaman pangan dengan pendekatan sosiokultural.
Menurut saya, Teori Malthus sampai saat ini masih relevan. Setidaknya sebagai peringatan untuk menggunakan pangan sekucupnya. Namun teori itu sudah tidak berlaku untuk diterapkan sebagai dasar kebijakan di masa sekarang, apalagi di masa depan. Kita telah berkaca pada kebijakan Revolusi Hijau yang malah mencederai Sejarah Lingkungan dan Agraria di Indonesia. Dengan pandangan “gebyah-uyah”, kebijakan itu tidak berhasil karena menurut saya, anggapan pemenuhan pangan dengan pola peningkatan jumlah pangan dan lahan itu berdampak kurang baik di masyarakat.
Inovasi Gotong Royong
Anggapan Malthus tentang pangan menurut saya adalah terfokus pada jumlah kuantitas, bukan kualitas. Bagi saya, jumlah pangan itu tetap apabila ada pendistribusian makanan itu merata. Tidak lagi bicara tentang peningkatan produksi pangan, tapi bagaimana alur pendistribusiannya itu tepat sasaran.
Saat ini, kita mengenal konsep Circular Economy, yang kurang lebih, berarti menahan selama mungkin pangan yang dihasilkan dari faktor produksi. Ditahan agar tidak cepat masuk tempat sampah. Atau dengan kata lain digunakan sampai tidak dapat dimanfaatkan. Konsep ini merupakan deskonstruksi dari pangan yang dimaksud Malthus, bahwa makanan itu akan langsung habis setelah dimakan. Padahal, jika kita melihat sekitar, masih ada makanan sisa yang dibuang ke tempat sampah atau dibiarkan tidak diolah kembali.
Sebagai contoh, saat ini ada – gerakan kecil yang berdampak besar – seperti Garda Pangan. Bagaimana kita tidak terpikirkan, ketika makanan sisa itu bisa diolah menjadi makanan yang layak? Makanan sisa jika diolah dengan baik, akan layak dikonsumsi karena masih mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Misalnya makanan yang berasal dari hotel, apakah itu tidak berasal dari bahan-bahan yang berkualitas?.
Gerakan Garda Pangan menjadi inovasi Gotong royong yang amat baik diterapkan di masa depan. Utamanya untuk pemberdayaan masyarakat kecil yang inklusif. Tentu, ada banyak gerakan-gerakan sosial kolaboratif yang saling berkaitan, bahkan membantu satu dengan yang lain.
Alih Teknologi Untuk Masyarakat
Tahun lalu, Asosiasi Pengusaha Desa di Indonesia (Apedi) menyelenggarakan pertemuan online yang membahas tentang pemerataan kebutuhan di Indonesia. Salah satu yang menarik adalah mereka berinisiatif untuk dapat menghubungkan daerah satu dengan yang lain melalui bank data. Mereka menggunakan Blockchain sebagai penyimpanan data yang memuat tentang jumlah komoditas pangan tertentu di suatu daerah. Jika ada daerah yang surplus, maka akan berbagi dengan desa yang kurang. Atau sebaliknya. Sistem bank data yang terintegrasi/satu atap menjadi cita-cita yang ingin dicapai untuk pemerataan. Dan peran utamanya adalah masyarakat kecil yang langsung sebagai pelaku sekaligus penerima.
Kemudian, jangan lupakan, rekayasa teknologi pangan saat ini semakin berkembang. Saat ini dengan adanya kampus merdeka, bergeliatnya UMKM, dan upaya-upaya pendekatan antara masyarakat dengan pemerintah. Kita perlu terlibat peran dan mendorong pelibatan dan kolaborasi-kolaborasi ini untuk mengkampanyekan penggunaan teknologi yang dapat membantu masyarakat kedepannya.
Dana Abadi Desa/Kampung
Sejak 2014, periode akhir Presiden SBY, kita mengenal adanya Undang-Undang Desa. Salah satu perhatian yang menjadi fokus utama, menurut saya, adalah jika dulu di masa Orde Baru, dikenal istilah “Membangun Desa”. Yaitu upaya pembangunan yang berasal dari pemerintah. Seperti ABRI masuk desa, pembangunan fisik jembatan, sekolah, dan sebagainya. Maka, hari ini kita sudah mempunyai narasi pembangunan yang lebih baik, yakni “Desa Membangun”. Peran pemerintah dan akademisi hanya sebagai parsipatory/pendamping saja dari masyarakat.
Gelontoran dana kurang lebih Rp. 400 triliun untuk desa di Indonesia oleh pemerintah merupakan gerakan kearah yang lebih baik. Kita hari ini sudah dapat melihat di beberapa desa ada industri padat karya, Desa Wisata, BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa), dan sebagainya. Kedepan, diharapkan dana desa menjadi dana abadi yang dikelola secara transparan dan tepat sasaran. Karena jika itu dapat dicapai, maka penghidupan masyarakat desa/kampung akan aman dan sejahtera. Ancaman krisis pangan akan jauh dari pandangan mereka. Semoga itu semua tadi tidak utopis, karena sampai sekarang kita terus optimis melakukan perbaikan dan gerakan ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan.
Penulis: Fariz Ilham Rosyidi (Mahasiswa Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga)