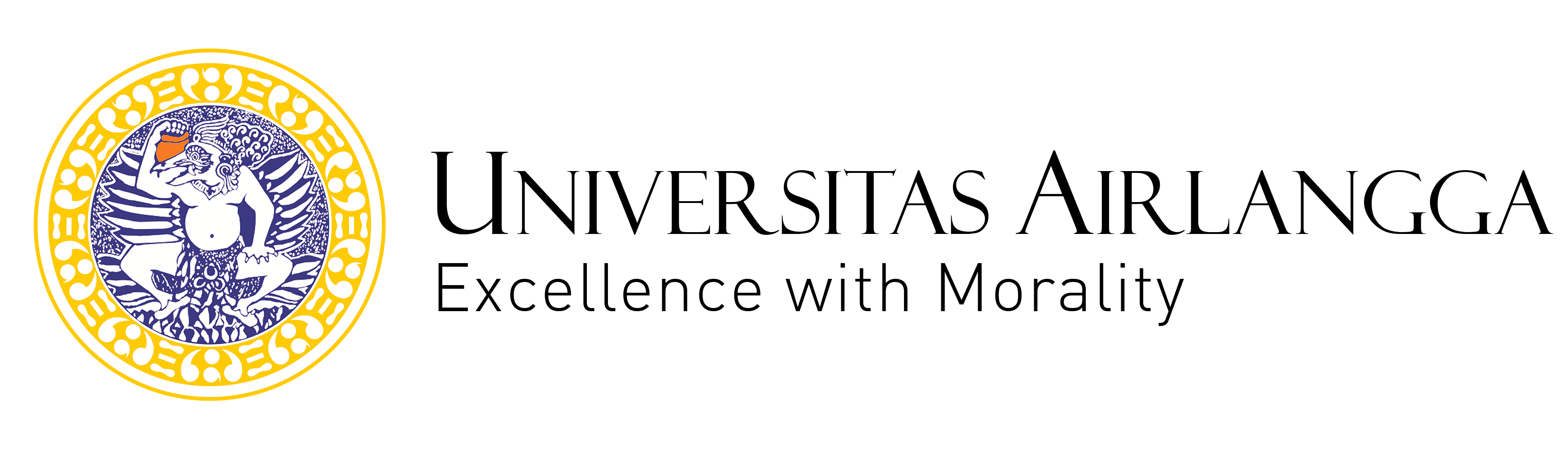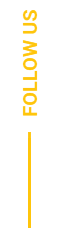Garam merupakan salah satu bahan kimia penting yang dibutuhkan dalam industri makanan, kimia, farmasi, hingga kehidupan sehari-hari. Jumlah kebutuhan garam industri nasional pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 4,6 juta ton. Namun hingga saat ini Indonesia masih harus mengimpor garam dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Hal ini disebabkan rendahnya kualitas nasional garam dimana dapat dilihat dari banyaknya garam yang diolah oleh petani garam dan pabrik pengolahan garam belum memenuhi baku mutu jika dilihat dari kadar NaClnya. Luas tambak garam di Indonesia sekitar 30.786 Ha dan terletak di berbagai wilayah. Tambak garam terluas terdapat di Pulau Jawa yang luasnya 25.541 Ha. Garam juga diproduksi di Nusa Tenggara Barat dengan luas 1.155 Ha, Sulawesi Selatan 2.205 Ha. Selanjutnya, di Sumatera dan wilayah lainnya seluas 1.885 Ha.
Permasalahan yang ada pada produksi garam rakyat saat ini adalah rendahnya kualitas dan kuantitas garam nasional. Kebutuhan garam seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pesatnya perkembangan industri yang menggunakan garam. Permasalahan pokok lainnya yang perlu diselesaikan bersama oleh instansi terkait produksi garam nasional meliputi teknologi dan teknis produksi.
Petani garam dalam memproduksi garam menggunakan cara yang sangat sederhana dengan menguapkan air laut di petakan penggaraman dengan sinar matahari tanpa sentuhan teknologi apa pun. Sehingga meskipun bahan bakunya melimpah namun memiliki variasi salinitas dan larutnya bahan pengotor sangat beragam. Air laut yang telah mengalami proses penguapan dan kristalisasi menghasilkan garam yang biasa disebut garam kasar (krosok) yang rata-rata mengandung natrium klorida (NaCl) kandungan < 85% dan mengandung pengotor seperti magnesium sulfat (MgSO4), kalsium sulfat (CaSO4), magnesium klorida (MgCl2), kalium klorida (KCl) dan pengotor tanah.
Kategori garam yang terbaik berkisar jika mengandung kadar NaCl > 95%, kategori kedua adalah garam dengan NaCl 90-95%, dan kategori ketiga adalah kadar NaCl sedang antara 80-90%. Sistem budidaya garam rakyat sampai saat ini menggunakan proses kristalisasi garam sederhana sehingga menghasilkan produktivitas dan kualitas garam yang masih kurang dengan kadar NaCl rata-rata kurang dari 85% dan banyak mengandung pengotor. Secara umum pembuatan garam dari air lama hanya dilakukan di kolam garam dengan metode geomembran dan prisma dengan bantuan penguapan dari sinar matahari,
Garam alami mengandung senyawa magnesium klorida, magnesium sulfat, magnesium bromida dan senyawa lainnya. Garam merupakan kumpulan senyawa kimia dengan kandungan terbesar adalah natrium klorida (NaCl) dan pengotor yaitu kalsium sulfat (CaSO4), magnesium sulfat (MgSO4) dan magnesium klorida (MgCl2). Selama ini garam di Indonesia diproduksi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di PT. Garam (Persero) dan petambak garam atau dikenal dengan sebutan budidaya garam rakyat. Kandungan terlarut dalam garam < 20% terdiri dari MgCl2 0,3 – 1%, MgSO4 0,2 – 0,6% dan CaSO4 0,5 -1%. Komposisi kimia natrium klorida (NaCl) terdiri dari 39,3% natrium (Na) dan 60,7% klorin (Cl).
Natrium klorida adalah bubuk kristal putih yang berbentuk kubus. Ciri-ciri garam dibedakan menjadi ciri-ciri fisik yang meliputi kenampakan, rasa, bau dan warna, serta sifat kimia yang meliputi kadar air, kadar NaCl, kadar iodium dan konten pengotor. Kotoran atau zat pengotor pada garam sangat mempengaruhi kualitas garam tersebut. Kotoran dalam kaleng garam menjadi CaSO4, MgSO4, MgCl2, serta komponen pengotor lainnya. Pengotor unsur kalsium (Ca) adalah biasanya cast dan carbonat. Kristal cast sangat halus dan mengendap sangat lambat, sehingga terjadi kristalisasi. Hal ini menyebabkan kemurnian garam yang diperoleh dengan cara penguapan menggunakan tenaga surya lebih rendah dibandingkan dengan penguapan buatan. Senyawa magnesium (Mg) yang terkandung dalam larutan induk merupakan hasil sisa pengendapan NaCl yang menempel pada bagian luar kristal garam dan menyebabkan sifat higroskopis menjadi besar dan memberikan rasa pahit.
Natrium klorida (NaCl) adalah zat ikatan ionik. Gaya kohesi pada molekul ionik berasal dari tarikan elektrostatik antara ion dan ion. Bahan seperti itu dianggap mudah membentuk padatan, karena ion dapat langsung menarik ion sehingga membangun struktur molekul. NaCl memiliki struktur kisi fcc (face centered cube) sehingga NaCl mempunyai ikatan yang kuat. Karena sumber ikatannya bersifat elektrostatis sehingga semakin banyak ion negative yang mengelilingi ion positif membuat semakin stabil dan memperkuat soliditas suatu zat.
Metode yang digunakan untuk uji NaCl adalah Mohr Argentometry. Argentometry ada 4 macam, yaitu Mohr Argentometry, Volhard Argentometry, Fajans Argentometry dan Liebig Argentometry. Metode yang sering digunakan untuk kadar klorida adalah Mohr Argentometry yang digunakan untuk penentuan garam halogenida dengan larutan standar AgNO3. Indikator yang digunakan adalah larutan K2CrO4 dan titik akhir titrasi ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna merah muda. Titrasi harus dilakukan dalam keadaan netral sehingga tidak boleh dilakukan dalam kondisi asam atau basa.
Air tua adalah istilah untuk kandungan NaCl jenuh. Istilahnya berawal dari petambak garam yang mengartikan air jenuh sebagai “air tua”, rata-rata air laut mempunyai 0-3oBe kemudian diuapkan sehingga menjadi air tua dengan kandungan garam di atas 20oBe. Be merupakan tingkat salinitas air laut dan digunakan sebagai bahan baku pembuatan garam. Alat yang digunakan untuk mengukur derajat Be adalah Be (baume) meter. Air tua yang sudah mencapai Be standar kebutuhan produksi kemudian dialirkan pada meja garam hingga dihasilkan kristal garam yang siap pakai untuk panen.
Dasar titrasi argentometry adalah reaksi pengendapan dimana zat yang akan diakhiri dengan munculnya larutan mentah perak nitrat (AgNO3) dan indikator kromat (K2CrO4). Zat-zat tersebut antara lain garam halogenida (Cl, Br, I), sianida, tiosianida dan fosfat. Titik akhir titrasi ditunjukkan dengan adanya endapan berwarna. Titrasi dalam suasana asam menyebabkan perak kromat menjadi larut karena terbentuk dikromat dan dalam suasana basa akan terbentuk endapan perak hidroksida. Ketika ion klorida atau bromida telah diendapkan oleh ion perak (Ag+), terjadi kondisi kromatik. Ion tersebut akan bereaksi dengan perak (Ag) berlebih membentuk endapan perak bata coklat/merah (Ag2CrO4) pada saat titrasi.
Kadar air merupakan persentase kandungan suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah (wet base) atau berdasarkan berat kering (dry base). Kadar air berat basah mempunyai batas maksimum teoritis sebesar 100%, sedangkan kadar air berdasarkan berat kering bisa lebih dari 100%. Peningkatan air dalam kandungan garam dapat mempengaruhi kandungan NaCl. Semakin tinggi kandungan air dalam garam maka konsentrasi senyawa lain juga akan berkurang termasuk senyawa NaCl. Penentuan kadar air pada dasarnya dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan metode pengeringan (thermogravimetry), metode distilasi (thermovolumetry), metode fisik dan metode kimia (Metode Karl Fischer) mengacu SNI 3556-2010.
Nilai kadar air pada garam tradisional dapat menunjukkan adanya hubungan interaksi antara suhu dan waktu pembuatan air lama dengan kadar air garam tradisional (P<0,05), juga diperoleh adanya interaksi yang nyata antara suhu dan waktu pemanasan terhadap kadar NaCl (P<0,05). Hasil uji sensorik (warna, rasa, tekstur) menunjukkan bahwa terdapat interaksi nyata antara suhu dan waktu pemanasan terhadap warna, rasa dan tekstur (P<0,05).
Kadar air merupakan salah satu sifat kimia suatu bahan yang menunjukkan banyaknya air yang terkandung di dalam bahan makanan. Air merupakan komponen yang paling banyak terkandung dalam garam sekitar 0,37% hingga 5,14%. Syarat jumlah kadar air maksimum untuk bahan baku industri garam iodium mengacu pada SNI 01-3556-2010 dan persyaratan mutu garam konsumsi yodium maksimal 7% (SNI 01-3556-2010). Semakin tinggi suhu dan kecepatan aliran udara pengeringan maka semakin cepat pula proses pengeringan berlangsung. Semakin tinggi suhu udara pengering maka energi panas yang dibawa oleh udara pengering semakin besar sehingga semakin banyak massa cair yang menguap dari permukaan material yang dikeringkan. Jika semakin tinggi kecepatan aliran udara pengering maka semakin cepat massa uap air dipindahkan dari bahan ke atmosfer.
NaCl merupakan komponen penyusun utama garam serta komponen lainnya sebagai pengotor, biasanya berasal dari ion Ca2+, Mg2+, SO42-. Pengotor tersebut terikat pada pelarut sehingga tersuspensi dan dapat dipisahkan melalui penyaringan. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian zat padat dari adanya campuran atau pengotor dengan mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dengan pelarut. Rekristalisasi juga dapat diaplikasikan pada proses pemurnian garam yang diawali dengan kelarutan garam dengan menggunakan air panas yang kemudian disaring untuk memisahkan kotoran.
Penulis : Prof. Ir. Mochammad Amin Alamsjah, M.Si., Ph.D.
Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Airlangga
E Susilowati1, Mochammad Amin Alamsjah, Dwi Yuli Pujiastuti. 2023. The effect of old water making time and heating temperature on moisture content and NaCl on traditional salt production. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 1273 012028. IOP Publishing. doi:10.1088/1755-1315/1273/1/012028