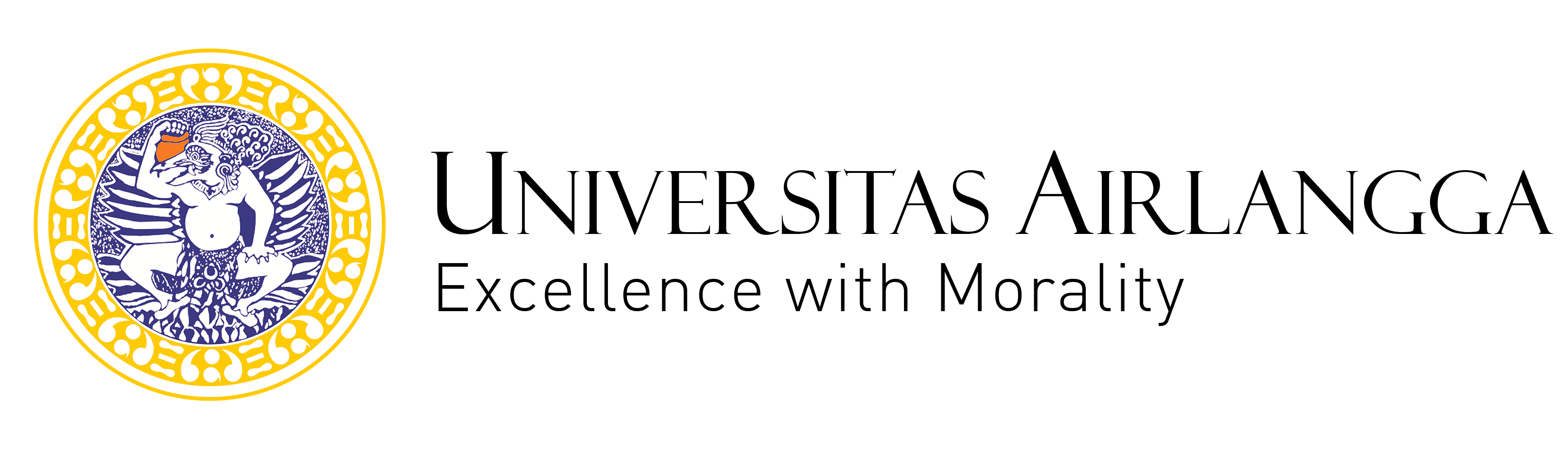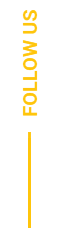Pertumbuhan pesat aktivitas industri telah menyebabkan berbagai dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah pencemaran lingkungan seperti pencemaran udara, tanah, dan air. Berbagai industri seperti elektroplating, pembuatan kertas, peleburan, tekstil, pewarna, pupuk, pestisida, dan pertambangan mengeluarkan sejumlah besar limbah cair yang terkontaminasi unsur beracun ke lingkungan perairan. Kadmium (Cd(II)) adalah salah satu unsur beracun yang diklasifikasikan sebagai polutan yang sangat berbahaya di lingkungan perairan. Pembuangan limbah pertanian dan industri yang tidak diolah, seperti tekstil, batik, baterai nikel-kadmium, plastik, elektroplating, dan pigmen cat merupakan sumber utama pencemaran Cd(II). Cd(II) dapat dengan mudah terakumulasi di berbagai organ tubuh manusia seperti ginjal, paru-paru, dan hati. Paparan Cd(II) dapat memicu pembentukan radikal bebas di dalam tubuh manusia yang merusak protein, lipid, dan DNA.
Menurut standar kualitas kesehatan lingkungan di lingkungan perairan untuk tujuan kebersihan sanitasi di Indonesia, tingkat maksimum Cd(II) adalah 0,005 mg/L. Oleh karena itu, beberapa teknik digunakan untuk menghilangkan ion logam dari larutan, seperti metode fisikokimia tradisional hingga metode bioremediasi. Namun, metode ini memiliki beberapa kelemahan utama termasuk pembentukan kotoran beracun, penghilangan logam yang tidak lengkap, efisiensi rendah, dan konsumsi energi serta reagen yang tinggi. Hingga saat ini, penelitian sebelumnya telah memanfaatkan berbagai pendekatan tradisional untuk menghilangkan ion Cd dari air, termasuk osmosis balik, presipitasi kimia, flokulasi, dan pertukaran ion. Meskipun strategi ini dapat diterapkan dan bermanfaat, pendekatan-pendekatan tersebut memiliki biaya operasi dan infrastruktur yang tinggi serta menghasilkan sejumlah besar bahan perantara yang beracun. Adsorpsi adalah metode yang unik karena memiliki beberapa fitur luar biasa seperti sederhana, efektifitas, dan konsumsi energi yang rendah.
Di antara berbagai teknologi pemrosesan, adsorpsi telah berkembang sebagai metode yang sangat disukai untuk mengolah air limbah. Hal ini disebabkan karena adsorpsi adalah teknik yang ramah lingkungan, mudah dioperasikan, sangat efisien, bebas dari pencemaran sekunder, mudah untuk diregenerasi, dan hemat biaya. Metode biosorpsi dianggap cukup efektif karena selain kemampuannya mengikat ion logam, pemulihan (desorpsi) ion logam yang terikat relatif mudah. Metode ini menggunakan biomassa yang berasal dari tanaman sebagai adsorben. Bahan pertanian yang mengandung selulosa menunjukkan kapasitas penyerapan yang potensial untuk berbagai polutan unsur beracun. Bahan-bahan ini dianggap ekonomis dan ramah lingkungan karena memiliki komposisi kimia yang unik, ketersediaan yang melimpah, dan dapat diperbarui. Adsorben yang menggunakan biomassa telah mendapatkan perhatian dari para peneliti dan dipelajari seperti bagas, sekam padi, sekam wijen, sekam bunga matahari, ampas teh, kulit jeruk, serbuk gergaji, jamur shitake (Lentinula edodes), limbah buah zaitun, kulit melon dew, dan lainnya.
Salah satu jenis tanaman pertanian yang banyak dikembangkan di Indonesia adalah tanaman serealia seperti sorgum. Tanaman ini merupakan tanaman serealia makanan ketiga setelah padi dan jagung. Budidaya sorgum menghasilkan sejumlah besar limbah pertanian bagas sorgum setiap tahun, yang biasanya digunakan sebagai pakan ternak, biofuel selulosa, dan bahan baku industri. Kandungan nutrisi tanaman sorgum cukup tinggi dan beragam, seperti karbohidrat, lemak, kalsium, besi, dan fosfor. Bagas sorgum terdiri dari 43,58% selulosa, 24,51% hemiselulosa, dan 26,22% lignin. Namun, pemanfaatan limbah pertanian bagas sorgum masih di bawah tingkat yang diharapkan, sehingga keberadaannya masih berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pemanfaatan limbah pertanian bagas sorgum perlu dieksplorasi lebih lanjut, misalnya sebagai adsorben yang berpotensi menghilangkan unsur beracun. Kelompok fungsional karboksil dan hidroksil yang terdapat di permukaan bagas sorgum dapat memfasilitasi mekanisme adsorpsi logam.
Menurut penelitian sebelumnya, penggunaan biosorben alami untuk penghilangan unsur beracun dianggap menunjukkan kinerja yang buruk karena kapasitas serapannya yang rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan perlakuan terhadap biosorben alami untuk meningkatkan kapasitas adsorpsi terhadap unsur beracun. Perlakuan biosorben alami dapat dilakukan secara fisik atau kimia. Perlakuan fisik biasanya dianggap sederhana dan murah, tetapi metode ini tidak banyak digunakan karena efektivitasnya yang rendah. Perlakuan kimia, di sisi lain, lebih disukai karena operasinya sederhana dan juga efisien dalam meningkatkan selektivitas terhadap polutan unsur beracun yang ditargetkan. Perlakuan kimia yang umum adalah perlakuan asam atau alkali, pencangkokan dengan EDTA, glutaraldehid, dan epiklorohidrin. Perlakuan alkali, terutama menggunakan NaOH dapat menghilangkan kotoran di permukaan adsorben, membuka situs aktif untuk adsorpsi logam, menghidrolisis dan mendeasetilasi selulosa dalam biosorben. Proses ini dapat melarutkan hemiselulosa dan lignin dari dinding sel adsorben.
Berdasarkan deskripsi di atas, penggunaan biomassa sebagai adsorben untuk polutan unsur beracun memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Selain itu, pemanfaatan limbah pertanian bagas sorgum masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah memanfaatkan limbah pertanian bagas sorgum yang diaktifkan dengan NaOH sebagai biosorben untuk menghilangkan Cd(II) dalam larutan berair.
Kondisi optimal adsorpsi Cd(II) dicapai menggunakan massa adsorben sebesar 600 mg dengan waktu kontak selama 70 menit, konsentrasi awal larutan sebesar 100 mg/L, pada pH 5 dan suhu larutan 30oC, dengan kapasitas adsorpsi (Qads) dan persentase penyerapan maksimum masing-masing sebesar 4,219 mg/g dan 96,48%. Karakterisasi adsorben bagas sorgum (SB) sebelum dan setelah diaktivasi dengan NaOH menunjukkan bahwa permukaan adsorben menjadi lebih halus, lebih berpori, dan memiliki luas permukaan dan ukuran pori yang lebih besar. Hasil uji pHpzc untuk adsorben SB-NaOH adalah 5,8. Adsorpsi Cd(II) mengikuti model isoterm Langmuir dengan kapasitas adsorpsi sebesar 4,924 mg/g dan nilai RL menunjukkan adsorpsi yang menguntungkan. Proses adsorpsi ion Cd(II) mengikuti hukum laju orde kedua, dimana mekanisme adsorpsi adalah kemisorpsi, yang didukung oleh model Elovich. Perilaku termodinamik adsorpsi menunjukkan bahwa proses adsorpsi ion Cr(VI) bersifat eksotermik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa adsorben SB-NaOH dapat berfungsi sebagai adsorben yang menjanjikan untuk adsorpsi ion Cd(II) dengan efisiensi adsorpsi yang baik, penggunaan yang relatif sederhana, dan sifatnya yang ekonomis. Tim peneliti menyarankan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas adsorpsi dan aplikasinya sebagai adsorben untuk unsur beracun lainnya.
Penulis: Dr. Handoko Darmokoesoemo, Drs., DEA
Link: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02757540.2024.2376044