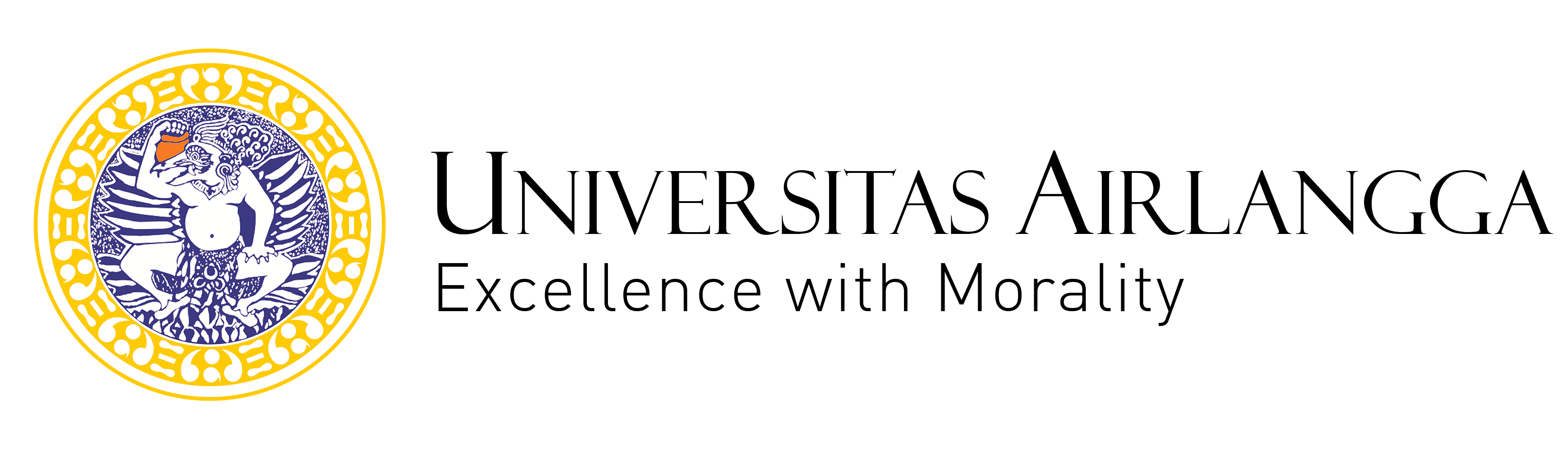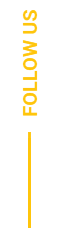Pemalsuan dokumen merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak signifikan terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks kehidupan sosial dan ekonomi, dokumen digunakan sebagai dasar administratif dalam kegiatan hukum, bisnis, dan pemerintahan. Ketika dokumen palsu digunakan untuk memperoleh hak atau keuntungan tertentu, hal tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengancam integritas sistem hukum itu sendiri. Kasus-kasus pemalsuan dokumen yang terus meningkat di Indonesia menunjukkan bahwa kejahatan ini memiliki kompleksitas tersendiri karena dapat terjadi lintas waktu dan baru terungkap setelah jangka waktu yang panjang.
Sebelum adanya perubahan hukum, masa daluwarsa (statute of limitations) terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dihitung sejak tanggal terjadinya perbuatan pidana. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 79 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan bahwa tenggang waktu daluwarsa dimulai pada hari setelah perbuatan dilakukan. Dalam praktiknya, ketentuan ini sering kali tidak memberikan keadilan bagi korban karena banyak kasus pemalsuan baru diketahui setelah bertahun-tahun dokumen tersebut digunakan atau disalahgunakan. Akibatnya, hak korban untuk memperoleh keadilan sering kali terhambat oleh kedaluwarsanya kasus.
Perubahan mendasar terjadi setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022, yang menegaskan bahwa perhitungan masa daluwarsa pemalsuan dokumen tidak lagi dimulai sejak perbuatan dilakukan, tetapi sejak dokumen palsu tersebut diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian. Putusan ini menandai pergeseran paradigma besar dalam hukum pidana Indonesia, karena menempatkan kepentingan korban dan asas keadilan substantif di atas formalitas waktu semata. Dengan demikian, hukum tidak lagi sekadar berorientasi pada kepastian prosedural, melainkan juga pada perlindungan hak-hak masyarakat yang dirugikan.
Perubahan ini juga membawa implikasi luas terhadap praktik penegakan hukum, khususnya bagi kepolisian dan kejaksaan. Aparat penegak hukum kini memiliki tanggung jawab baru untuk menilai secara kumulatif tiga unsur penting, yaitu waktu penemuan, penggunaan, dan timbulnya kerugian, guna menentukan apakah suatu perkara masih dalam batas waktu penuntutan. Hal ini menuntut profesionalisme dan ketelitian tinggi dalam proses penyidikan, karena kesalahan menafsirkan unsur waktu dapat berakibat pada tidak sahnya proses hukum yang dijalankan.
Secara teoretis, perubahan tersebut mencerminkan penguatan prinsip kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan (justice) sebagai dua asas fundamental dalam hukum pidana. Kepastian hukum memberikan batasan yang jelas bagi pelaku kejahatan, sedangkan keadilan substantif menjamin agar korban tetap mendapat perlindungan hukum, meskipun waktu telah berlalu. Oleh karena itu, pembahasan artikel ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 118/PUU-XX/2022 terhadap sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam menentukan batas waktu penuntutan tindak pidana pemalsuan dokumen.
Konsekuensi Hukum Putusan MK terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 118/PUU-XX/2022 lahir dari adanya ketidakpastian hukum dalam praktik penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen. Sebelum adanya putusan ini, aparat penegak hukum sering kali menghentikan penyidikan karena perkara dianggap telah daluwarsa berdasarkan perhitungan waktu sejak perbuatan dilakukan. Padahal, banyak korban baru menyadari bahwa dirinya dirugikan setelah dokumen palsu digunakan dalam transaksi hukum, seperti jual beli tanah atau pengalihan hak kepemilikan. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan karena korban kehilangan kesempatan untuk menuntut keadilan akibat keterlambatan penemuan fakta.
Dalam permohonannya, para pemohon dalam perkara MK tersebut mengajukan keberatan terhadap ketentuan Pasal 79 ayat (1) KUHP yang dianggap tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang jaminan kepastian hukum yang adil. Mereka menilai bahwa norma tersebut menutup akses keadilan bagi korban karena waktu daluwarsa dihitung tanpa mempertimbangkan kapan korban mengetahui adanya pemalsuan. Mahkamah Konstitusi kemudian menyetujui permohonan tersebut dan memutuskan bahwa ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1) harus dimaknai secara baru agar selaras dengan prinsip konstitusional.
Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa perbuatan pemalsuan dokumen memiliki karakter khusus, di mana akibat hukum dari tindak pidana tidak langsung terjadi saat perbuatan dilakukan. Pemalsuan baru dapat diketahui setelah dokumen tersebut digunakan dan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, MK menyatakan bahwa daluwarsa harus dihitung secara kumulatif sejak terpenuhinya tiga unsur: penemuan, penggunaan, dan kerugian. Penafsiran baru ini menutup kekosongan hukum yang selama ini menimbulkan perbedaan penegakan di antara aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.
Dari sisi dogmatik hukum, putusan ini membawa konsekuensi pada perubahan interpretasi norma dalam KUHP. Pasal 79 ayat (1) kini harus dibaca sebagai ketentuan bersyarat (conditionally constitutional), artinya tetap berlaku sepanjang ditafsirkan sesuai dengan putusan MK. Dengan demikian, putusan ini memiliki daya ikat erga omnes, yang berarti mengikat seluruh warga negara dan lembaga penegak hukum tanpa kecuali. Hal ini mempertegas peran MK sebagai penjaga konstitusi dan sumber tafsir final atas norma hukum nasional.
Dengan diberlakukannya penafsiran baru ini, negara memberikan ruang yang lebih besar bagi korban kejahatan dokumen untuk memperoleh keadilan. Putusan tersebut juga memperkuat posisi penyidik dalam menangani perkara lama yang baru terungkap, tanpa terhambat alasan formal daluwarsa. Di sisi lain, perubahan ini menuntut peningkatan kapasitas penyidik dalam mengumpulkan bukti dan memastikan keterpenuhan tiga unsur kumulatif yang menjadi dasar sahnya proses hukum.
Implementasi Mahkamah Konstitusi No. 118/PUU-XX/2022 dalam Proses Penyidikan dan Penegakan Hukum
Pasca Putusan MK No. 118/PUU-XX/2022, mekanisme penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen mengalami penyesuaian mendasar. Penyidik kini wajib menelusuri kapan korban mengetahui adanya pemalsuan, kapan dokumen digunakan, serta bagaimana kerugian timbul akibat penggunaan tersebut. Ketiga unsur ini harus dibuktikan secara hukum agar dapat menentukan kapan tenggang waktu daluwarsa mulai berjalan. Proses ini memerlukan pendekatan hukum yang cermat, karena setiap unsur memiliki konsekuensi yuridis berbeda terhadap sah atau tidaknya tindakan penyidikan.
Dalam praktiknya, penyidik Polri harus mengumpulkan bukti yang berkaitan langsung dengan penemuan dan penggunaan dokumen palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Bukti dapat berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa. Surat atau dokumen menjadi alat bukti utama, mengingat kasus pemalsuan umumnya berhubungan dengan keaslian dan penggunaan dokumen tertentu. Oleh karena itu, penyidik dituntut memahami karakteristik alat bukti tertulis agar dapat menentukan dengan tepat kapan tindak pidana dianggap mulai berjalan dari segi waktu daluwarsa.
Dari perspektif kelembagaan, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penegak hukum harus menyesuaikan sistem administrasi penyidikan mereka dengan tafsir baru MK. Setiap laporan atau pengaduan yang berhubungan dengan pemalsuan dokumen kini harus diverifikasi berdasarkan tiga unsur kumulatif tersebut. Selain itu, laporan hasil penyelidikan wajib mencantumkan analisis waktu penemuan, penggunaan, dan kerugian agar keputusan penghentian atau pelimpahan perkara ke penuntut umum memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan gugatan praperadilan.
Putusan ini juga memiliki implikasi terhadap asas lex posterior derogat legi priori, terutama setelah disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (KUHP 2023). Walaupun KUHP baru akan menjadi lex posterior, tafsir MK sebagai lex prior tetap memiliki kekuatan konstitusional. Dengan demikian, dalam penerapan hukum, aparat penegak hukum harus memperhatikan keselarasan antara norma baru KUHP dengan tafsir konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak terjadi kontradiksi dalam pelaksanaan di lapangan.
Secara sosiologis, implementasi putusan ini memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Korban yang sebelumnya tidak dapat menuntut keadilan karena kendala waktu kini memiliki kesempatan untuk memperjuangkan haknya. Namun, di sisi lain, aparat penegak hukum perlu mengantisipasi potensi penyalahgunaan aturan ini oleh pihak-pihak yang sengaja menunda pelaporan untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, profesionalisme penyidik dan hakim sangat diperlukan agar asas kepastian hukum dan keadilan dapat berjalan secara seimbang.
Penulis: Sapta Aprilianto
Informasi detail artikel: https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/76259